1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Sirimavo Bandaranaike memiliki latar belakang keluarga yang kaya dan terpandang, serta mendapatkan pendidikan yang membentuk pandangan hidupnya sebelum ia terjun ke dunia politik.
1.1. Kelahiran dan Keluarga
Sirimavo Bandaranaike lahir dengan nama Sirima Ratwatte pada tanggal 17 April 1916 di Ellawala Walawwa, kediaman bibinya di Ratnapura, British Ceylon. Ibunya adalah Rosalind Hilda Mahawalatenne Kumarihamy, seorang praktisi pengobatan Ayurveda informal, dan ayahnya adalah Barnes Ratwatte, seorang kepala suku dan politikus pribumi. Kakek dari pihak ibunya, Mahawalatenne, dan kemudian ayahnya, menjabat sebagai Rate Mahatmaya, seorang kepala suku pribumi di Balangoda.

Ayahnya adalah anggota keluarga Radala Ratwatte, para kepala suku Kerajaan Kandy. Silsilah keluarga ayahnya termasuk pamannya, Sir Jayatilaka Cudah Ratwatte, orang pertama dari Kandy yang menerima gelar kebangsawanan Inggris, serta para abdi dalem yang melayani monarki Sinhala. Salah satu dari mereka, Ratwatte, Dissawa dari Matale, adalah penandatangan Konvensi Kandyan tahun 1815.
Sirima adalah anak tertua dari enam bersaudara. Ia memiliki empat saudara laki-laki, Barnes Jr., Seevali, Mackie, dan Clifford, serta satu saudara perempuan, Patricia, yang menikah dengan Kolonel Edward James Divitotawela, pendiri Komando Pusat Angkatan Darat Ceylon. Keluarga ini tinggal di walawwa, atau rumah bangsawan kolonial, milik kakek dari pihak ibu Sirima, Mahawalatenne, dan kemudian di walawwa mereka sendiri di Balangoda. Sejak usia muda, Sirima memiliki akses ke perpustakaan luas kakeknya yang berisi karya sastra dan ilmiah.
1.2. Pendidikan
Bandaranaike pertama kali bersekolah di taman kanak-kanak swasta di Balangoda. Pada tahun 1923, ia pindah sebentar ke kelas-kelas dasar Ferguson High School di Ratnapura, dan kemudian dikirim ke sekolah asrama di St Bridget's Convent, Colombo. Meskipun pendidikannya berada dalam sistem sekolah Katolik, Sirima tetap menjadi penganut Buddha sepanjang hidupnya dan fasih berbahasa Inggris maupun Sinhala.
1.3. Kegiatan Sosial Awal
Setelah menyelesaikan sekolah pada usia 19 tahun, Sirima Ratwatte terlibat dalam pekerjaan sosial. Ia mendistribusikan makanan dan obat-obatan ke desa-desa di hutan, mengorganisir klinik, dan membantu menciptakan industri pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan desa. Ia menjadi bendahara Liga Pelayanan Sosial, menjabat dalam kapasitas tersebut hingga tahun 1940. Selama enam tahun berikutnya, ia tinggal bersama orang tuanya sambil mereka mengatur pernikahannya.
Bandaranaike bergabung dengan Lanka Mahila Samiti (Asosiasi Wanita Lankan) pada tahun 1941, organisasi sukarela wanita terbesar di negara itu. Ia berpartisipasi dalam banyak proyek sosial yang diprakarsai oleh Mahila Samiti untuk pemberdayaan perempuan pedesaan dan bantuan bencana. Salah satu proyek pertamanya adalah program pertanian untuk mengatasi kekurangan produksi pangan. Jabatan pertamanya, sebagai sekretaris organisasi, melibatkan pertemuan dengan para ahli pertanian untuk mengembangkan metode baru dalam menghasilkan panen padi. Seiring waktu, Bandaranaike menjabat sebagai bendahara, wakil presiden, dan akhirnya presiden Mahila Samiti, dengan fokus pada isu-isu pendidikan anak perempuan, hak-hak politik perempuan, dan keluarga berencana. Ia juga merupakan anggota Asosiasi Wanita Buddha Seluruh Ceylon, Masyarakat Kanker, Asosiasi Nasional Ceylon untuk Pencegahan Tuberkulosis, dan Asosiasi Kesejahteraan Perawat.
2. Pernikahan dan Keluarga
Pernikahan Sirimavo dengan S. W. R. D. Bandaranaike dan peran anak-anaknya memiliki dampak signifikan terhadap perjalanan politiknya dan dinamika politik Sri Lanka.
2.1. Pernikahan dengan S. W. R. D. Bandaranaike
Setelah menolak dua pelamar-seorang kerabat dan putra dari keluarga pertama Ceylon-orang tua Ratwatte dihubungi oleh seorang mak comblang yang mengusulkan pernikahan dengan Solomon West Ridgeway Dias (S.W.R.D.) Bandaranaike. S.W.R.D. adalah seorang pengacara lulusan Oxford yang beralih menjadi politikus, dan pada saat itu menjabat sebagai Menteri Administrasi Lokal di Dewan Negara Ceylon. Awalnya, S.W.R.D. Bandaranaike tidak dianggap berasal dari keluarga yang "dapat diterima", karena keluarga Ratwatte adalah keluarga bangsawan Kandyan yang mewarisi pelayanan mereka kepada keluarga kerajaan tradisional, sementara keluarga Bandaranaike adalah keluarga kaya dari dataran rendah yang telah melayani penguasa kolonial selama berabad-abad. Para astrolog melaporkan bahwa horoskop mereka cocok, manfaat penyatuan kedua keluarga dipertimbangkan, dan persetujuan diberikan oleh keluarga Ratwatte. Pasangan itu, yang sebelumnya telah bertemu, setuju dengan pilihan tersebut.
Pada tanggal 2 Oktober 1940, Ratwatte dan Bandaranaike menikah di Mahawelatenne Walawwa dalam apa yang disebut pers sebagai "pernikahan abad ini" karena kemegahannya. Pasangan yang baru menikah itu pindah ke Wendtworth di Guildford Crescent, Colombo, yang mereka sewa dari Lionel Wendt.

Putri-putri mereka, Sunethra (lahir 1943) dan Chandrika (lahir 1945), lahir di Wendtworth tempat keluarga itu tinggal hingga tahun 1946, ketika ayah S.W.R.D. membelikan mereka sebuah rumah besar yang dikenal sebagai Tintagel di Rosmead Place, Colombo. Sejak saat itu, keluarga tersebut tinggal sebagian tahun di Tintagel dan sebagian tahun di manor leluhur S.W.R.D., Horagolla Walawwa. Seorang putra, Anura, lahir di Tintagel pada tahun 1949. Selama 20 tahun berikutnya, Sirima Bandaranaike mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membesarkan keluarganya dan menjadi nyonya rumah bagi banyak kenalan politik suaminya.
Bandaranaike sering menemani S.W.R.D. dalam perjalanan resmi, baik di dalam maupun luar negeri. Ia dan suaminya sama-sama hadir setelah rumah sakit jiwa di Angoda dibom oleh Jepang selama Serangan Minggu Paskah pada tahun 1942, yang menewaskan banyak orang. Ketika Ceylon bergerak menuju status pemerintahan sendiri pada tahun 1947, S.W.R.D. menjadi lebih aktif dalam gerakan nasionalis. Ia mencalonkan diri-dan terpilih-ke Dewan Perwakilan Rakyat dari Distrik Pemilihan Attanagalla. Ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan dan menjabat sebagai Pemimpin Dewan, tetapi semakin frustrasi dengan cara kerja internal dan kebijakan Partai Nasional Bersatu. Meskipun ia tidak mendorong Bandaranaike untuk terlibat dalam topik politik dan meremehkannya di depan rekan-rekan, S.W.R.D. mulai menghormati penilaiannya. Pada tahun 1951, ia membujuknya untuk mengundurkan diri dari Partai Nasional Bersatu dan mendirikan Partai Kebebasan Sri Lanka (Partai Kebebasan, alias SLFP).
Bandaranaike berkampanye di daerah pemilihan Attanagalla S.W.R.D. selama pemilihan parlemen 1952, sementara suaminya berkeliling negara untuk menggalang dukungan. Meskipun Partai Kebebasan hanya memenangkan sembilan kursi dalam pemilihan tersebut, S.W.R.D. terpilih menjadi anggota Parlemen dan menjadi Pemimpin Oposisi. Ketika pemilihan baru diadakan pada tahun 1956 oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala, S.W.R.D. melihat peluang dan membentuk Mahajana Eksath Peramuna (MEP), sebuah koalisi empat partai yang luas, untuk mengikuti pemilihan 1956. Bandaranaike sekali lagi berkampanye untuk suaminya di Attanagalla, di kota asalnya Balangoda, dan di Ratnapura untuk Partai Kebebasan. Mahajana Eksath Peramuna memenangkan kemenangan telak dan S.W.R.D. menjadi perdana menteri.
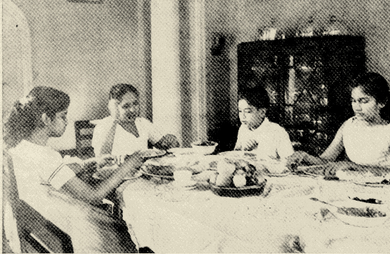
2.2. Anak-anak
Ketiga anak Bandaranaike dididik di luar negeri. Sunethra belajar di Oxford, Chandrika di University of Paris, dan Anura di University of London. Ketiganya kemudian kembali dan menjabat di pemerintahan Sri Lanka.
3. Masuk ke Dunia Politik
Terjunnya Sirimavo Bandaranaike ke dunia politik didorong oleh tragedi pribadi yang mengubah arah hidupnya dan lanskap politik Sri Lanka.
3.1. Pembunuhan Suami dan Transisi Politik
Bandaranaike berada di rumah di Rosmead Place pada pagi hari tanggal 25 September 1959, ketika S.W.R.D. Bandaranaike ditembak berkali-kali oleh seorang biksu Buddha, yang tidak puas karena ia percaya kurangnya dukungan untuk pengobatan tradisional. Bandaranaike menemani suaminya ke rumah sakit, di mana ia meninggal dunia akibat luka-lukanya keesokan harinya.
Dalam kekacauan politik yang terjadi di bawah pemerintahan sementara Wijeyananda Dahanayake, banyak menteri kabinet dicopot, dan beberapa ditangkap serta diadili atas pembunuhan tersebut. Koalisi Mahajana Eksath Peramuna runtuh tanpa pengaruh S.W.R.D., dan pemilihan umum diadakan pada Maret 1960 untuk mengisi kursi daerah pemilihan Attanagalla. Bandaranaike dengan enggan setuju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independen, tetapi sebelum pemilihan dapat diadakan, Parlemen dibubarkan, dan ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri. Ketika pemilihan diadakan pada Maret 1960, Partai Nasional Bersatu memenangkan mayoritas empat kursi atas Partai Kebebasan Sri Lanka. Dudley Senanayake, perdana menteri baru, dikalahkan dalam waktu sebulan dalam mosi tidak percaya dan pemilihan umum kedua diadakan pada Juli 1960.
3.2. Menjadi Ketua Partai
Pada Mei 1960, Bandaranaike terpilih secara aklamasi sebagai presiden partai oleh komite eksekutif Partai Kebebasan, meskipun saat itu ia masih ragu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Juli. Menolak ikatan partai sebelumnya dengan Komunis dan Trotskyis, pada awal Juni ia berkampanye dengan janji untuk melanjutkan kebijakan suaminya - khususnya, mendirikan sebuah republik, memberlakukan undang-undang untuk menjadikan Sinhala sebagai bahasa resmi negara, dan mengakui dominasi Buddhisme, meskipun mentoleransi penggunaan bahasa mereka sendiri dan kepercayaan Hindu oleh Tamil perkebunan.
Meskipun telah ada populasi Tamil di negara itu selama berabad-abad, mayoritas Tamil perkebunan telah dibawa ke Ceylon dari India oleh otoritas Inggris sebagai pekerja perkebunan. Banyak orang Ceylon memandang mereka sebagai imigran sementara, meskipun mereka telah tinggal selama beberapa generasi di Ceylon. Dengan kemerdekaan Ceylon, Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 mengecualikan Tamil India ini dari kewarganegaraan, membuat mereka tanpa kewarganegaraan. Kebijakan S.W.R.D. terhadap Tamil tanpa kewarganegaraan bersifat moderat, memberikan sebagian kewarganegaraan dan mengizinkan pekerja produktif untuk tetap tinggal. Penggantinya, Dudley Senanayake, adalah yang pertama merekomendasikan repatriasi wajib bagi populasi tersebut. Bandaranaike berkeliling negara dan menyampaikan pidato emosional, sering kali menangis saat ia berjanji untuk melanjutkan kebijakan mendiang suaminya. Tindakannya membuatnya dijuluki "Janda Menangis" oleh lawan-lawannya.
4. Periode Perdana Menteri Pertama (1960-1965)
Masa jabatan pertama Sirimavo Bandaranaike sebagai perdana menteri ditandai oleh kebijakan-kebijakan ambisius yang bertujuan untuk mereformasi Ceylon, namun juga menghadapi tantangan ekonomi dan ketegangan etnis.
4.1. Menjadi Perdana Menteri Wanita Pertama
Pada tanggal 21 Juli 1960, setelah kemenangan telak Partai Kebebasan, Bandaranaike dilantik sebagai perdana menteri wanita pertama di dunia, sekaligus Menteri Pertahanan dan Urusan Luar Negeri. Karena ia bukan anggota parlemen terpilih pada saat itu, tetapi pemimpin partai yang memegang mayoritas di parlemen, konstitusi mengharuskannya menjadi anggota Parlemen dalam waktu tiga bulan jika ia ingin terus menjabat sebagai perdana menteri. Untuk memberinya tempat, Manameldura Piyadasa de Zoysa mengundurkan diri dari kursinya di Senat. Pada tanggal 5 Agustus 1960, Gubernur Jenderal Goonetilleke mengangkat Bandaranaike ke Senat Ceylon, majelis tinggi Parlemen.

Awalnya, ia berjuang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi negara, mengandalkan anggota kabinet dan keponakannya, Felix Dias Bandaranaike. Para lawan melontarkan komentar meremehkan tentang "kabinet dapur"nya: ia akan terus menghadapi seksisme serupa saat menjabat.
4.2. Kebijakan Ekonomi dan Nasionalisasi
Untuk melanjutkan kebijakan suaminya dalam menasionalisasi sektor-faktor kunci ekonomi, Bandaranaike mendirikan sebuah korporasi dengan pemegang saham publik-swasta, mengambil alih kendali tujuh surat kabar. Ia menasionalisasi perbankan, perdagangan luar negeri, dan asuransi, serta industri perminyakan. Dalam mengambil alih Bank of Ceylon dan mendirikan cabang-cabang Bank Rakyat yang baru dibentuk, Bandaranaike bertujuan untuk menyediakan layanan kepada komunitas yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas perbankan, mendorong pengembangan bisnis lokal.
Pada Desember 1960, Bandaranaike menasionalisasi semua sekolah paroki yang menerima dana negara. Dengan demikian, ia membatasi pengaruh minoritas Katolik, yang cenderung menjadi anggota elit ekonomi dan politik, dan memperluas pengaruh kelompok Buddha.
4.3. Kebijakan Bahasa dan Dampak Etnis
Pada Januari 1961, Bandaranaike menerapkan undang-undang yang menjadikan Sinhala sebagai bahasa resmi, menggantikan bahasa Inggris. Tindakan ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan lebih dari dua juta penutur bahasa Tamil. Didorong oleh anggota Partai Federal, kampanye pembangkangan sipil dimulai di provinsi-provinsi dengan mayoritas Tamil. Tanggapan Bandaranaike adalah dengan mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan untuk memulihkan perdamaian.
Mulai tahun 1961, serikat pekerja memulai serangkaian pemogokan sebagai protes terhadap inflasi dan pajak yang tinggi. Salah satu pemogokan tersebut melumpuhkan sistem transportasi, memotivasi Bandaranaike untuk menasionalisasi dewan transportasi.
4.4. Hubungan Internasional dan Gerakan Non-Blok
Dalam upaya menyeimbangkan kepentingan timur-barat dan menjaga netralitas, Bandaranaike memperkuat hubungan negara dengan Tiongkok, sambil memutuskan hubungan dengan Israel. Ia berusaha menjaga hubungan baik dengan India dan Rusia, sambil mempertahankan hubungan dengan kepentingan Inggris melalui ekspor teh dan mendukung hubungan dengan Bank Dunia. Mengutuk kebijakan apartheid Afrika Selatan, Bandaranaike mengangkat duta besar dan mencari hubungan dengan negara-negara Afrika lainnya. Pada tahun 1961, ia menghadiri Konferensi Perdana Menteri Persemakmuran di London dan KTT Gerakan Non-Blok Pertama di Belgrade, SFR Yugoslavia, menjadikan Sri Lanka salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok.

Ia adalah pemain kunci dalam mengurangi ketegangan antara India dan Tiongkok setelah sengketa perbatasan mereka pada tahun 1962 meletus menjadi Perang Sino-India. Pada November dan Desember tahun itu, Bandaranaike mengadakan konferensi di Colombo dengan delegasi dari Burma, Kamboja, Ceylon, Ghana, dan Republik Arab Bersatu untuk membahas sengketa tersebut. Ia kemudian melakukan perjalanan bersama Menteri Kehakiman Ghana Kofi Ofori-Atta ke India dan Peking, Tiongkok dalam upaya menengahi perdamaian. Pada Januari 1963, Bandaranaike dan Orofi-Atta dihargai di New Delhi, ketika Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, setuju untuk mengajukan mosi di Parlemen India yang merekomendasikan penyelesaian yang diadvokasi Bandaranaike.
Di dalam negeri, kesulitan semakin meningkat. Meskipun sukses di luar negeri, Bandaranaike dikritik karena hubungannya dengan Tiongkok dan kurangnya kebijakan pembangunan ekonomi. Ketegangan masih tinggi atas favoritisme pemerintah yang jelas terhadap Buddha Ceylonese berbahasa Sinhala. Ketidakseimbangan impor-ekspor, diperparah oleh inflasi, berdampak pada daya beli warga kelas menengah dan bawah. Dalam pemilihan sela pertengahan tahun, meskipun Bandaranaike memegang mayoritas, Partai Nasional Bersatu memperoleh keuntungan, menunjukkan bahwa dukungannya menurun.
Kurangnya dukungan untuk langkah-langkah penghematan, khususnya ketidakmampuan untuk mengimpor beras yang memadai - makanan pokok utama - menyebabkan pengunduran diri Menteri Felix Dias Bandaranaike. Menteri kabinet lainnya dirotasi dalam upaya membendung pergeseran menuju kemitraan perdagangan Soviet, yang telah mendapatkan pijakan setelah pembentukan Ceylon Petroleum Corporation. Perusahaan Perminyakan telah diluncurkan pada tahun 1961 untuk menghindari harga monopoli yang dikenakan pada impor minyak Timur Tengah, memungkinkan Ceylon mengimpor minyak dari Republik Arab Bersatu dan Uni Soviet. Beberapa fasilitas penyimpanan operator minyak barat diambil alih dengan perjanjian kompensasi, tetapi perselisihan yang terus berlanjut mengenai non-pembayaran mengakibatkan penangguhan bantuan asing dari Amerika Serikat pada Februari 1963. Sebagai reaksi terhadap penangguhan bantuan, Parlemen mengesahkan Ceylon Petroleum Corporation Amendment Act yang menasionalisasi semua distribusi, impor-ekspor, penjualan, dan pasokan sebagian besar produk minyak di negara itu, mulai Januari 1964.
Juga pada tahun 1964, pemerintah Bandaranaike menghapuskan Layanan Sipil Ceylon yang independen dan menggantinya dengan Layanan Administratif Ceylon, yang tunduk pada pengaruh pemerintah. Ketika koalisi United Left Front antara Partai Komunis, Sosialis Revolusioner, dan Partai Trotskyis dibentuk pada akhir tahun 1963, Bandaranaike bergerak ke kiri untuk mencoba mendapatkan dukungan mereka. Pada Februari 1964, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mengunjungi Bandaranaike di Ceylon dengan tawaran bantuan, hadiah beras dan tekstil, serta diskusi untuk memperluas perdagangan. Keduanya juga membahas sengketa perbatasan Sino-India dan perlucutan senjata nuklir. Hubungan dengan Tiongkok menarik, karena pengakuan resmi Bandaranaike baru-baru ini terhadap Jerman Timur telah menghilangkan bantuan yang masuk dari Jerman Barat dan nasionalisasinya terhadap industri asuransi telah memengaruhi hubungannya dengan Australia, Inggris, dan Kanada.
Sebagai persiapan untuk Konferensi Non-Blok kedua, Bandaranaike menjadi tuan rumah bagi presiden Tito dan Nasser di Colombo pada Maret 1964, tetapi gejolak domestik yang terus-menerus menyebabkannya menangguhkan sesi parlemen hingga Juli. Sementara itu, ia menjalin koalisi dengan United Left Front dan berhasil memperkuat mayoritasnya, meskipun hanya dengan selisih tiga kursi.
Pada September 1964, Bandaranaike memimpin delegasi ke India untuk membahas repatriasi 975.000 Tamil tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Ceylon. Bersama dengan Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri, ia menyusun ketentuan Pakta Srimavo-Shastri, sebuah perjanjian penting untuk kebijakan luar negeri kedua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, Ceylon akan memberikan kewarganegaraan kepada 300.000 Tamil dan keturunan mereka, sementara India akan memulangkan 525.000 Tamil tanpa kewarganegaraan. Selama 15 tahun yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban mereka, para pihak setuju untuk menegosiasikan ketentuan untuk 150.000 sisanya. Pada Oktober, Bandaranaike menghadiri dan menjadi salah satu sponsor Konferensi Non-Blok yang diadakan di Kairo.
Pada Desember 1964, pemerintah Front Persatuan mengajukan "Rancangan Undang-Undang Pengambilalihan Pers" dalam upaya menasionalisasi surat kabar negara. Oposisi dan kritik Bandaranaike mengklaim bahwa langkah itu untuk membungkam pers bebas dan menyerang kritikus utamanya, Lake House Group yang dipimpin oleh baron pers Esmond Wickremesinghe. Wickremesinghe menanggapi dengan kampanye untuk mencopotnya dari jabatan untuk menjaga kebebasan pers. Pada 3 Desember 1964, C. P. de Silva, yang pernah menjadi wakil S. W. R. D. Bandaranaike, memimpin tiga belas anggota parlemen SLFP dan membelot ke oposisi dengan mengutip Rancangan Undang-Undang Pengambilalihan Pers. Pemerintah Sirima Bandaranaike kalah dalam pidato takhta dengan satu suara dan pemilihan umum diadakan pada Maret 1965. Koalisi politiknya dikalahkan dalam pemilihan 1965, mengakhiri masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri.
5. Pemimpin Oposisi (1965-1970)
Setelah kekalahan dalam pemilihan umum 1965, Sirimavo Bandaranaike mengambil peran penting sebagai pemimpin oposisi, berupaya mengonsolidasikan partainya dan mempersiapkan diri untuk kembali berkuasa.
5.1. Peran dalam Oposisi
Dalam pemilihan umum 1965, Bandaranaike memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Distrik Pemilihan Attanagalla. Dengan partainya memperoleh 41 kursi, ia menjadi Pemimpin Oposisi, wanita pertama yang pernah memegang jabatan tersebut. Dudley Senanayake dilantik sebagai perdana menteri pada 25 Maret 1965.
Tak lama setelah itu, posisi Bandaranaike sebagai anggota parlemen ditantang, ketika tuduhan dibuat bahwa ia telah menerima suap, dalam bentuk mobil, saat menjabat. Sebuah komite ditunjuk untuk menyelidiki dan ia kemudian dibebaskan dari tuduhan tersebut.
Selama lima tahun masa jabatannya di oposisi, ia mempertahankan aliansinya dengan partai-partai sayap kiri. Dari tujuh pemilihan sela yang diadakan antara November 1966 dan April 1967, enam dimenangkan oleh oposisi di bawah kepemimpinan Bandaranaike. Inflasi yang terus-menerus, ketidakseimbangan perdagangan, pengangguran, dan kegagalan bantuan asing yang diharapkan terwujud menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Hal ini semakin dipicu oleh langkah-langkah penghematan, yang mengurangi tunjangan beras mingguan.
5.2. Konsolidasi Partai
Pada tahun 1969, Bandaranaike secara aktif berkampanye untuk kembali berkuasa. Di antara janji-janji lainnya, ia berjanji untuk memberikan dua takaran beras per rumah tangga, menasionalisasi bank-bank asing dan industri impor-ekspor, membentuk kelompok pengawas untuk memantau korupsi bisnis dan pemerintah, kembali ke kebijakan luar negeri yang menjauh dari mitra "imperialis", dan mengadakan Majelis Konstituen yang bertugas menyusun Konstitusi baru.
6. Periode Perdana Menteri Kedua (1970-1977)
Masa jabatan kedua Sirimavo Bandaranaike sebagai perdana menteri ditandai oleh reformasi konstitusional yang signifikan, tantangan ekonomi yang parah, dan gejolak sosial yang mengancam stabilitas negara.
6.1. Konstitusi Baru dan Republik Sri Lanka
Bandaranaike kembali berkuasa setelah koalisi Front Persatuan antara Partai Komunis, Partai Lanka Sama Samaja, dan Partai Kebebasannya sendiri memenangkan pemilihan umum 1970 dengan mayoritas besar pada Mei 1970. Pada Juli, ia telah mengadakan Majelis Konstituen untuk menggantikan konstitusi yang disusun Inggris dengan yang disusun oleh orang Ceylon. Ia memperkenalkan kebijakan yang mensyaratkan sekretaris tetap di kementerian pemerintah memiliki keahlian di bidangnya. Misalnya, mereka yang bertugas di Kementerian Perumahan haruslah insinyur terlatih, dan mereka yang bertugas di Kementerian Kesehatan, praktisi medis. Semua pegawai pemerintah diizinkan untuk bergabung dengan Dewan Pekerja dan di tingkat lokal ia membentuk Komite Rakyat untuk memungkinkan masukan dari masyarakat luas mengenai administrasi pemerintah. Perubahan-perubahan itu dimaksudkan untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial Inggris dan pengaruh asing dari institusi-institusi negara.

Pada Mei 1972, Ceylon digantikan oleh Republik Sri Lanka setelah konstitusi baru diratifikasi. Meskipun negara itu tetap berada dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Ratu Elizabeth II tidak lagi diakui sebagai penguasanya. Berdasarkan ketentuannya, Senat, yang ditangguhkan sejak 1971, secara resmi dihapuskan dan Majelis Negara Nasional unikameral yang baru dibentuk, menggabungkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam satu otoritas.
Konstitusi mengakui supremasi Buddhisme, meskipun menjamin perlindungan yang sama bagi Buddhisme, Kristen, Hindu, dan Islam. Namun, konstitusi ini gagal menyediakan piagam hak-hak yang tidak dapat dicabut, mengakui Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi, dan tidak mengandung "elemen federalisme".
Konstitusi baru juga memperpanjang masa jabatan Bandaranaike selama dua tahun, mengatur ulang masa jabatan lima tahun perdana menteri agar bertepatan dengan pembentukan republik. Batasan-batasan ini menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai sektor populasi, khususnya mereka yang tidak nyaman dengan aturan otoriter, dan populasi berbahasa Tamil. Sebelum bulan itu berakhir, ketidakpuasan meningkat sebelum menyebabkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Hakim, yang membentuk tribunal terpisah untuk menangani pemberontak yang dipenjara dari tahun sebelumnya. Mereka yang menentang tribunal berpendapat bahwa mereka melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada Juli, insiden kekerasan sporadis muncul kembali, dan pada akhir tahun, gelombang kedua pemberontakan diantisipasi. Pengangguran yang meluas memicu kekecewaan publik yang semakin besar terhadap pemerintah, meskipun program redistribusi tanah diberlakukan untuk membentuk koperasi pertanian dan membatasi ukuran tanah milik pribadi.
6.2. Kebijakan Ekonomi dan Krisis
Menghadapi defisit anggaran sebesar 195.00 M USD - yang disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan impor makanan serta penurunan pendapatan dari ekspor kelapa, karet, dan teh - Bandaranaike berusaha memusatkan ekonomi dan menerapkan kontrol harga. Ditekan oleh anggota sayap kiri koalisinya untuk menasionalisasi bank-bank asing asal Inggris, India, dan Pakistan, ia menyadari bahwa tindakan tersebut akan memengaruhi kebutuhan kredit. Seperti yang ia lakukan pada rezim sebelumnya, ia mencoba menyeimbangkan aliran bantuan asing dari mitra kapitalis dan komunis.
Pada Desember 1970, Undang-Undang Akuisisi Usaha Bisnis disahkan, yang memungkinkan negara untuk menasionalisasi bisnis apa pun dengan lebih dari 100 karyawan. Konon, langkah ini bertujuan untuk mengurangi kendali asing atas produksi teh dan karet utama, tetapi menghambat investasi domestik dan asing dalam industri dan pembangunan.

Pada tahun 1972, Bandaranaike memperkenalkan reformasi tanah besar di Sri Lanka, dengan pemberlakuan Land Reform Act of No. 01 of 1972 yang memberlakukan batas maksimum 20 ha pada tanah milik pribadi. Ini kemudian diikuti oleh Land Reform (Amendment) Act pada tahun 1975 yang menasionalisasi perkebunan milik perusahaan publik. Tujuan reformasi tanah ini adalah untuk memberikan tanah kepada petani tak bertanah. Para kritikus mengklaim bahwa gelombang kedua reformasi menargetkan pemilik tanah kaya yang secara tradisional mendukung Partai Nasional Bersatu. Sebagai hasil dari reformasi ini, negara menjadi pemilik perkebunan terbesar dan dua entitas, Sri Lanka State Plantations Corporation, Janatha Estate Development Board (Dewan Pembangunan Perkebunan Rakyat), dan USAWASAMA (Dewan Pembangunan Perkebunan Koperasi Dataran Tinggi) didirikan untuk mengelola perkebunan ini. Pada tahun-tahun setelah reformasi tanah ini, produksi tanaman ekspor utama yang diandalkan Sri Lanka untuk pemasukan mata uang asing menurun.
Krisis minyak 1973 memiliki efek traumatis pada ekonomi Sri Lanka. Masih bergantung pada bantuan asing, barang, dan bantuan moneter dari Australia, Kanada, Tiongkok, Denmark, Hongaria, dan Bank Dunia, Bandaranaike melonggarkan program penghematan yang membatasi impor barang konsumsi. Amerika Serikat mengakhiri hibah bantuan, yang tidak memerlukan pembayaran kembali, dan beralih ke kebijakan penyediaan pinjaman luar negeri. Devaluasi mata uang Sri Lanka, ditambah dengan inflasi dan pajak tinggi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan tekanan siklis untuk mengatasi defisit dengan pajak yang lebih tinggi dan langkah-langkah penghematan. Inflasi yang tidak terkontrol antara tahun 1973 dan 1974 menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan ketidakpuasan publik.
Pada tahun 1974, Bandaranaike memaksa penutupan kelompok surat kabar independen terakhir, The Sun, meyakini bahwa kritik mereka memicu kerusuhan. Keretakan muncul dalam koalisi Front Persatuan, sebagian besar diakibatkan oleh pengaruh berkelanjutan Partai Lanka Sama Samaja terhadap serikat pekerja dan ancaman aksi mogok sepanjang tahun 1974 dan 1975. Ketika perkebunan yang baru disita ditempatkan di bawah Kementerian Pertanian dan Tanah, yang dikendalikan oleh Partai Lanka Sama Samaja, kekhawatiran bahwa mereka akan mengorganisir pekerja perkebunan menyebabkan Bandaranaike mengusir mereka dari koalisi pemerintah.
6.3. Pemberontakan Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) 1971
Meskipun upaya Bandaranaike untuk mengatasi masalah ekonomi negara, pengangguran dan inflasi tetap tidak terkendali. Setelah hanya 16 bulan berkuasa, pemerintah Bandaranaike hampir digulingkan oleh Pemberontakan Janatha Vimukthi Peramuna tahun 1971 oleh pemuda sayap kiri. Meskipun menyadari sikap militan Janatha Vimukthi Peramuna (Front Pembebasan Rakyat), administrasi Bandaranaike awalnya gagal mengenali mereka sebagai ancaman yang akan datang, menganggap mereka sebagai idealis.
Pada 6 Maret, militan menyerang Kedutaan Besar A.S. di Colombo, yang menyebabkan deklarasi keadaan darurat pada 17 Maret. Pada awal April, serangan terhadap kantor polisi menunjukkan pemberontakan yang terencana dengan baik yang tidak dapat ditangani oleh tentara kecil Ceylon. Meminta bantuan dari sekutunya, pemerintah sebagian besar diselamatkan karena kebijakan luar negeri netral Bandaranaike. Uni Soviet mengirim pesawat untuk mendukung pemerintah Ceylon; senjata dan peralatan datang dari Inggris, Republik Arab Bersatu, Amerika Serikat, dan Yugoslavia; pasokan medis disediakan oleh Jerman Timur dan Barat, Norwegia, dan Polandia; kapal patroli dikirim dari India; dan baik India maupun Pakistan mengirim pasukan. Pada 1 Mei, Bandaranaike menangguhkan serangan pemerintah dan menawarkan amnesti, yang menghasilkan ribuan penyerahan diri. Bulan berikutnya amnesti kedua ditawarkan. Bandaranaike membentuk Komite Nasional Rekonstruksi untuk membangun kembali otoritas sipil dan menyediakan rencana strategis untuk menangani pemberontak yang ditangkap atau menyerah. Salah satu tindakan pertama Bandaranaike setelah konflik adalah mengusir diplomat Korea Utara, karena ia curiga mereka telah memicu ketidakpuasan radikal. Pepatah "Dia adalah satu-satunya pria di kabinetnya" - yang dikaitkan dengan lawan politiknya pada tahun 1960-an - muncul kembali selama puncak pemberontakan, karena Bandaranaike membuktikan bahwa ia telah menjadi "kekuatan politik yang tangguh".
6.4. Hubungan Internasional dan Bantuan Asing
Pada September 1970, Bandaranaike menghadiri Konferensi Non-Blok ketiga di Lusaka, Zambia. Bulan itu, ia juga melakukan perjalanan ke Paris dan London untuk membahas perdagangan internasional. Memerintahkan perwakilan The Asia Foundation dan Peace Corps untuk meninggalkan negara itu, Bandaranaike mulai mengevaluasi kembali perjanjian perdagangan dan proposal yang telah dinegosiasikan oleh pendahulunya. Ia mengumumkan bahwa pemerintahannya tidak akan mengakui Israel sampai negara itu menyelesaikan masalahnya secara damai dengan negara-negara tetangga Arabnya. Ia secara resmi memberikan pengakuan kepada Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan. Bandaranaike menentang pengembangan pusat komunikasi Anglo-AS di Samudra Hindia, dengan alasan bahwa daerah tersebut harus menjadi "zona netral, bebas nuklir".
Meskipun bergantung pada bantuan asing, barang, dan bantuan moneter dari Australia, Kanada, Tiongkok, Denmark, Hongaria, dan Bank Dunia, Bandaranaike melonggarkan program penghematan yang membatasi impor barang konsumsi. Amerika Serikat mengakhiri hibah bantuan, yang tidak memerlukan pembayaran kembali, dan beralih ke kebijakan penyediaan pinjaman luar negeri.
Pada tahun 1975, sebagai pengakuan atas Tahun Wanita Internasional, Bandaranaike membentuk sebuah lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang kemudian menjadi Kementerian Urusan Wanita dan Anak-anak. Ia mengangkat wanita pertama yang menjabat di Kabinet Sri Lanka, Siva Obeyesekere, pertama sebagai Sekretaris Negara Pertama untuk Kesehatan dan kemudian sebagai Menteri Kesehatan. Ia dihormati di Konferensi Wanita Dunia PBB yang diselenggarakan di Mexico City, hadir sebagai satu-satunya perdana menteri wanita yang terpilih dengan haknya sendiri. Bandaranaike mengambil alih jabatan ketua selama satu tahun pada Konferensi ke-5 Negara-Negara Non-Blok pada tahun 1976, menjadi tuan rumah pertemuan di Colombo.
7. Kemunduran Politik dan Kepemimpinan Oposisi (1977-1994)
Periode ini menandai kemunduran signifikan dalam karier politik Sirimavo Bandaranaike, di mana ia menghadapi kekalahan pemilu, pencabutan hak sipil, dan perjuangan untuk mempertahankan relevansinya di tengah gejolak politik dan perang saudara.
7.1. Kekalahan Pemilu dan Sanksi Politik
Dalam pemilihan umum 1977, Front Persatuan dikalahkan telak, hanya memenangkan enam kursi. Bandaranaike mempertahankan kursi parlemennya di Attanagalla. Pada November 1977, petisi yang menantang posisinya sebagai anggota parlemen ditolak oleh Pengadilan Tinggi Colombo. Pada tahun 1978, konstitusi baru diratifikasi, menggantikan sistem parlementer gaya Inggris dengan sistem presidensial gaya Prancis. Di bawah konstitusi, eksekutif atau Presiden, dipilih oleh suara rakyat untuk menjabat selama enam tahun. Presiden kemudian memilih seorang perdana menteri untuk memimpin Kabinet, yang dikonfirmasi oleh legislatif. Konstitusi ini memberikan deklarasi hak-hak fundamental, menjamin kesetaraan warga negara untuk pertama kalinya. Konstitusi ini juga mengakui bahasa Tamil sebagai bahasa nasional, meskipun bahasa administrasi tetap Sinhala. Meskipun bertujuan untuk menenangkan separatis Tamil, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menghentikan kekerasan antara Tamil dan Sinhala, yang mengakibatkan pengesahan Undang-Undang Pencegahan Terorisme 1979.
Pada tahun 1980, sebuah Komisi Kepresidenan Khusus ditunjuk oleh Presiden J. R. Jayewardene untuk menyelidiki tuduhan terhadap Bandaranaike atas penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatannya sebagai perdana menteri. Setelah penyerahan laporan kepada Jayewardene, pemerintah Partai Nasional Bersatu mengadopsi mosi di parlemen pada 16 Oktober 1980 untuk mencabut hak sipil Bandaranaike dan keponakannya, Felix Dias Bandaranaike - yang dihukum karena korupsi - selama tujuh tahun. Ia diusir dari parlemen, tetapi mempertahankan perannya sebagai pemimpin partai. Mosi tersebut disahkan dengan 139 suara mendukung dan 18 menentang, dengan mudah memenuhi ambang dua pertiga yang disyaratkan.
7.2. Perjuangan di Luar Kekuasaan
Meskipun menjadi pemimpinnya, Bandaranaike tidak dapat berkampanye untuk Partai Kebebasan. Akibatnya, putranya, Anura, menjabat sebagai pemimpin partai parlemen. Di bawah Anura, Partai Kebebasan bergerak ke kanan, dan putri Bandaranaike, Chandrika, menarik diri, membentuk Partai Rakyat Sri Lanka bersama suaminya, Vijaya Kumaratunga. Tujuan partai baru itu terkait dengan rekonsiliasi dengan Tamil.
Sejak tahun 1980, konflik antara pemerintah dan kelompok separatis dari berbagai kelompok yang bersaing, termasuk Macan Tamil, People's Liberation Organisation of Tamil Eelam, Tamil Eelam Liberation Army, dan Tamil Eelam Liberation Organization, menjadi lebih sering dan semakin kejam. Selama kampanye pemilihan lokal pada tahun 1981, ekstremis Tamil membunuh Arumugam Thiagarajah, seorang politikus Partai Nasional Bersatu yang terkemuka. Partai Tamil United Liberation Front menyerukan boikot pemilihan presiden 1982. Pemberontak mendukung larangan tersebut, karena mereka berpendapat bahwa kerja sama dengan pemerintah melegitimasi kebijakannya dan bertentangan dengan keinginan untuk mencapai negara Tamil yang independen.
Pada tahun 1983, pemberontak Tamil menyergap patroli tentara, menewaskan tiga belas tentara. Kekerasan balasan oleh massa Sinhala memicu kerusuhan terhadap Tamil non-pemberontak dan properti mereka di seluruh negeri, yang kemudian disebut sebagai Black July.
Langkah Jayewardene menuju pasar bebas dan fokus pada pertumbuhan ekonomi merugikan petani Tamil di utara dengan menghapus perlindungan perdagangan. Demikian pula, kebijakan tersebut berdampak negatif tidak hanya pada bisnis Sinhala selatan yang menghadapi persaingan dari pasar India, tetapi juga pada kaum miskin kota, yang subsidi makanannya sangat dikurangi. Pengeluaran pemerintah yang besar untuk pembangunan ekonomi menciptakan defisit anggaran dan inflasi, mengkhawatirkan administrator Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Pada gilirannya, lembaga donor mengurangi bantuan untuk membujuk pemerintah mengendalikan pengeluaran. Akselerasi Mahaweli Development programme meningkatkan lapangan kerja dan menstabilkan pasokan makanan, juga mengurangi ketergantungan pada pasokan energi asing dengan selesainya empat fasilitas pembangkit listrik tenaga air.
Fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur gagal mengatasi masalah sosial. Misalnya, inisiatif perumahan pedesaan - yang membangun sekitar 100.000 rumah baru pada tahun 1984 - mempolarisasi komunitas karena perumahan didistribusikan berdasarkan aliansi politik daripada kebutuhan. Privatisasi industri, setelah tahun 1982, menciptakan kesenjangan signifikan antara orang kaya dan miskin dan inflasi kembali, membuat barang sulit diperoleh dan menurunkan standar hidup.
Pada Januari 1986, hak sipil Bandaranaike dipulihkan oleh dekret presiden yang dikeluarkan oleh Jayewardene. Konflik antara pemerintah dan separatis, yang telah meningkat sejak 1983, berubah menjadi Perang Saudara pada tahun 1987.
Jayewardene menunjukkan sedikit simpati terhadap masalah yang menjadi perhatian Tamil dan malah menyalahkan kerusuhan pada faksi sayap kiri yang merencanakan penggulingan pemerintah. Kegagalan dalam negosiasi dengan pemberontak akhirnya menyebabkan Jayewardene mengizinkan intervensi Pemerintah India. Ditandatangani pada tahun 1987, Indo-Sri Lanka Accord menetapkan syarat-syarat gencatan senjata antara Pemerintah Sri Lanka dan pemberontak, mengizinkan Pasukan Penjaga Perdamaian India untuk menduduki negara itu dalam upaya mempromosikan perlucutan senjata.
Bandaranaike dan Partai Kebebasan menentang masuknya pasukan India, meyakini pemerintah telah mengkhianati rakyatnya sendiri dengan mengizinkan India campur tangan atas nama Tamil. Sebagai reaksi terhadap kekerasan yang disetujui negara dan keinginan mereka akan fokus nasionalis, militan Janatha Vimukthi Peramuna muncul kembali di selatan. Dengan latar belakang ini, Bandaranaike memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 1988. Ia dikalahkan tipis oleh Ranasinghe Premadasa, yang menggantikan Jayewardene sebagai presiden.

Pada 6 Februari 1989, saat berkampanye untuk Partai Kebebasan dalam pemilihan umum 1989, Bandaranaike selamat dari serangan bom. Meskipun ia tidak terluka, salah satu ajudannya menderita cedera kaki. Dalam hasil akhir pada tanggal 19, Partai Kebebasan dikalahkan oleh Partai Nasional Bersatu di bawah Ranasinghe Premadasa, tetapi memperoleh 67 kursi, cukup bagi Bandaranaike untuk menjabat sebagai Pemimpin Oposisi untuk masa jabatan kedua. Ia berhasil terpilih kembali menjadi anggota parlemen di Distrik Pemilihan Gampaha. Pada tahun yang sama, pemerintah menghancurkan pemberontak Janatha Vimukthi Peramuna, menewaskan sekitar 30.000 hingga 70.000 dari mereka, alih-alih memilih pengadilan atau pemenjaraan seperti yang dilakukan Bandaranaike pada tahun 1971.
Pada tahun 1990, ketika gencatan senjata 13 bulan dilanggar oleh Macan Tamil, setelah milisi lain menyerahkan senjata mereka, pemerintah memutuskan untuk menghentikan negosiasi dengan Macan dan menggunakan solusi militer. Anura mendukung langkah tersebut, tetapi ibunya, Bandaranaike, menentang rencana tersebut. Ketika kekuasaan darurat diambil alih oleh presiden, ia menuntut agar keadaan darurat dicabut, menuduh pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Selama masa jabatannya sebagai pemimpin oposisi, ia mendukung pemakzulan Premadasa pada tahun 1991, yang dipimpin oleh anggota senior Partai Nasional Bersatu seperti Lalith Athulathmudali dan Gamini Dissanayake. Pemakzulan tersebut gagal, karena Premadasa menunda Parlemen dan Ketua M. H. Mohamed menolak mosi pemakzulan, menyatakan tidak ada cukup tanda tangan yang mendukungnya. Putri Bandaranaike, Chandrika Kumaratunga, yang telah hidup dalam pengasingan di London sejak tahun 1988, ketika suaminya dibunuh, kembali ke Sri Lanka dan bergabung kembali dengan Partai Kebebasan pada tahun 1991. Pada tahun yang sama, Bandaranaike, yang semakin terganggu oleh radang sendi, menderita stroke.
Pada tahun 1992, Premadasa Udugampola, kepala Biro Operasi Khusus, terpaksa pensiun setelah muncul protes internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Udugampola memberikan pernyataan tertulis bahwa pasukan pembunuh yang digunakan terhadap pemberontak telah didukung oleh pemerintah. Bandaranaike mendukung buktinya, tetapi Udugampola didakwa karena menumbuhkan permusuhan publik terhadap pemerintah. Ketika Presiden Premadasa dibunuh oleh seorang pembom bunuh diri pada 1 Mei 1993, Perdana Menterinya Dingiri Banda Wijetunga dilantik sebagai penjabat presiden dan dinominasikan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan presiden hingga 2 Januari 1995. Anggota Parlemen diminta untuk memberikan suara pada suksesi dalam waktu sebulan. Karena kesehatannya yang memburuk, Bandaranaike memilih untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi untuk melanjutkan sebagai pemimpin oposisi, dan Wijetunga mencalonkan diri tanpa lawan.
Wijetunga meyakinkan putra Bandaranaike, Anura, untuk membelot ke Partai Nasional Bersatu dan memberinya jabatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Pembelotannya membuat Bandaranaike dan Kumaratunga bertanggung jawab atas Partai Kebebasan. Karena kesehatan ibunya yang menurun, Kumaratunga memimpin pembentukan koalisi baru, Aliansi Rakyat (PA), untuk mengikuti pemilihan provinsi 1993 di Provinsi Barat Sri Lanka pada Mei. Aliansi tersebut memenangkan kemenangan telak, dan Kumaratunga diangkat sebagai kepala menteri pada tahun 1993. Selanjutnya, koalisi yang dipimpin oleh Kumaratunga juga memenangkan pemilihan dewan provinsi selatan. Kumaratunga memimpin kampanye Aliansi Rakyat untuk pemilihan parlemen 1994, karena ibunya sedang pulih dari operasi. Aliansi tersebut memenangkan kemenangan yang menentukan, dan Bandaranaike mengumumkan bahwa Kumaratunga akan menjadi perdana menteri. Pada saat ini Kumaratunga juga telah menggantikannya sebagai pemimpin Partai Kebebasan. Meskipun secara mental waspada tetapi menderita penyakit kaki dan komplikasi dari diabetes, Bandaranaike terpaksa menggunakan kursi roda. Setelah terpilih kembali menjadi anggota parlemen, ia diangkat ke kabinet putrinya sebagai Menteri tanpa Portofolio pada upacara pelantikan yang diadakan pada 19 Agustus 1994.
8. Periode Perdana Menteri Ketiga (1994-2000)
Masa jabatan ketiga Sirimavo Bandaranaike sebagai perdana menteri menandai kembalinya ia ke tampuk kekuasaan, meskipun dalam peran yang lebih seremonial di bawah kepresidenan putrinya.
8.1. Kembalinya ke Kekuasaan
Dalam pemilihan presiden yang menyusul pada November, saingan politik utama Kumaratunga, Gamini Dissanayake, dibunuh dua minggu sebelum pemilihan. Janda beliau, Srima Dissanayake, dipilih sebagai kandidat presiden Partai Nasional Bersatu. Keunggulan Kumaratunga diprediksi sekitar satu juta suara bahkan sebelum pembunuhan; ia memenangkan pemilihan dengan selisih yang lebar.
8.2. Peran dalam Pemerintahan Presiden
Menjadi presiden wanita pertama Sri Lanka, Kumaratunga mengangkat ibunya sebagai perdana menteri, yang berdasarkan ketentuan konstitusi 1978 berarti Bandaranaike bertanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri. Meskipun jabatan perdana menteri telah menjadi jabatan yang sebagian besar seremonial, pengaruh Bandaranaike dalam Partai Kebebasan tetap kuat. Meskipun mereka sepakat dalam kebijakan, Kumaratunga dan Bandaranaike berbeda dalam gaya kepemimpinan.
8.3. Pengunduran Diri dan Akhir Karier
Pada tahun 2000, Kumaratunga menginginkan perdana menteri yang lebih muda, dan Bandaranaike, dengan alasan kesehatan, mengundurkan diri pada Agustus 2000.
9. Kematian dan Warisan
Kematian Sirimavo Bandaranaike menandai berakhirnya karier politik yang panjang dan berpengaruh. Warisannya mencakup dampak pada politik perempuan serta kontribusi sosial dan kebijakan yang membentuk Sri Lanka modern.
9.1. Kematian dan Pemakaman
Bandaranaike meninggal pada 10 Oktober 2000 karena serangan jantung di Kadawatha, saat ia sedang dalam perjalanan pulang ke Colombo. Ia telah memberikan suaranya dalam pemilihan parlemen, yang diadakan pada hari itu. Sri Lanka mengumumkan dua hari berkabung nasional, dan stasiun radio negara menghentikan program reguler mereka untuk memutar lagu-lagu duka. Jenazah Bandaranaike disemayamkan di parlemen, dan pemakamannya kemudian berlangsung di Horagolla, di mana ia dimakamkan di mausoleum, Horagolla Bandaranaike Samadhi, yang awalnya dibangun untuk suaminya.

9.2. Dampak pada Politik Perempuan
Pada masa ketika gagasan seorang wanita memimpin sebuah negara hampir tidak terpikirkan oleh publik, Bandaranaike membantu meningkatkan persepsi global tentang kemampuan wanita. Selain kontribusinya sendiri terhadap Sri Lanka, anak-anaknya juga terlibat dalam pembangunan negara. Ketiga anaknya memegang posisi penting di tingkat nasional; selain peran Anura dan Chandrika dalam pemerintahan, putri Bandaranaike, Sunethra, bekerja sebagai sekretaris politiknya pada tahun 1970-an dan kemudian menjadi seorang filantropis. Pernikahan keluarga Bandaranaike membantu meruntuhkan penghalang sosial di Sri Lanka selama bertahun-tahun, melalui kebijakan sosialis yang mereka berlakukan.
Meskipun Bandaranaike terkenal sebagai perdana menteri wanita pertama di dunia, para sarjana politik berpendapat bahwa Bandaranaike secara simbolis kuat, tetapi pada akhirnya memiliki sedikit dampak pada representasi politik wanita di Sri Lanka. Meskipun Bandaranaike menyatakan kebanggaan atas statusnya sebagai pemimpin wanita, menganggap dirinya sebagai "Ibu Rakyat", ia tidak terlalu menekankan masalah wanita secara pribadi maupun politik, dan pemilihannya sebagai perdana menteri tidak secara signifikan meningkatkan jumlah wanita dalam politik Sri Lanka. Pengangkatan menteri wanita pertama, Siva Obeyesekere, ke Kabinet Sri Lanka pada tahun 1976, kurang revolusioner karena fakta bahwa Obeyesekere adalah kerabat Bandaranaike. Pengangkatan itu mengikuti pola Bandaranaike yang mengangkat anggota keluarga ke posisi tinggi pemerintah.
Pada tahun 1994, meskipun Bandaranaike dan putrinya Kumaratunga memegang posisi politik tertinggi sebagai perdana menteri dan presiden, Sri Lanka terus memiliki salah satu tingkat partisipasi politik terendah untuk wanita di antara negara-negara Asia mana pun. Pada tahun 2010, pada peringatan 50 tahun pemilihan Bandaranaike sebagai perdana menteri wanita pertama di dunia, anggota parlemen Sri Lanka Rosy Senanayake mengatakan kepada pers bahwa Sri Lanka belum membuat kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender dalam politik: hanya 4,5 persen anggota parlemen adalah wanita. Senanayake sebelumnya menyerukan "kuota khusus" untuk mencapai representasi gender yang lebih baik; kuota tersebut, yang mencadangkan 25% dari semua kursi legislatif untuk wanita, disahkan pada tahun 2016.
9.3. Warisan Politik dan Sosial
Selama tiga masa jabatannya, Bandaranaike memimpin negara itu menjauh dari masa lalu kolonialnya dan menuju kemerdekaan politiknya sebagai sebuah republik. Menerapkan kebijakan sosialis selama Perang Dingin, ia berusaha menasionalisasi sektor-sektor kunci ekonomi dan melakukan reformasi tanah untuk kepentingan penduduk asli, dengan tujuan mengakhiri favoritisme politik yang dinikmati oleh elit berpendidikan Barat. Salah satu tujuan utama kebijakannya adalah mengurangi disparitas etnis dan sosial-ekonomi di negara itu, meskipun kegagalannya untuk secara memadai mengatasi kebutuhan penduduk Tamil menyebabkan puluhan tahun perselisihan dan kekerasan di negara itu. Sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok, Bandaranaike membawa Sri Lanka menjadi menonjol di antara negara-negara yang berusaha tetap netral terhadap pengaruh negara adidaya. Ia bekerja untuk membentuk aliansi antara negara-negara di Belahan Bumi Selatan, dan berusaha menyelesaikan masalah secara diplomatis, menentang ekspansi nuklir.
10. Kritik dan Kontroversi
Meskipun diakui secara internasional, pemerintahan Sirimavo Bandaranaike juga menghadapi kritik dan kontroversi yang signifikan, terutama terkait kebijakan ekonomi, dampak etnis, dan tuduhan korupsi.
10.1. Kritik Kebijakan Ekonomi
Meskipun ia dipandang tinggi secara internasional, ia terus berjuang di dalam negeri di bawah tuduhan korupsi dan nepotisme, sementara ekonomi terus menurun. Inflasi yang tidak terkontrol antara tahun 1973 dan 1974 menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan ketidakpuasan publik.
Kritikus mengklaim bahwa gelombang kedua reformasi tanah menargetkan pemilik tanah kaya yang secara tradisional mendukung Partai Nasional Bersatu. Pada tahun-tahun setelah reformasi tanah ini, produksi tanaman ekspor utama yang diandalkan Sri Lanka untuk pemasukan mata uang asing menurun.
10.2. Kritik Terkait Konflik Etnis
Keputusan Bandaranaike untuk menjadikan Sinhala sebagai bahasa resmi, menggantikan bahasa Inggris, menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan lebih dari dua juta penutur bahasa Tamil. Didorong oleh anggota Partai Federal, kampanye pembangkangan sipil dimulai di provinsi-provinsi dengan mayoritas Tamil. Tanggapan Bandaranaike adalah dengan mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan untuk memulihkan perdamaian. Kegagalannya untuk secara memadai mengatasi kebutuhan penduduk Tamil menyebabkan puluhan tahun perselisihan dan kekerasan di negara itu.
Konstitusi baru yang diratifikasi pada tahun 1972, yang mengakui supremasi Buddhisme dan Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi, tetapi tidak mengandung "elemen federalisme", menyebabkan kekhawatiran bagi berbagai sektor populasi, khususnya mereka yang tidak nyaman dengan aturan otoriter, dan populasi berbahasa Tamil.
10.3. Tuduhan Korupsi dan Nepotisme
Meskipun ia dipandang tinggi secara internasional, ia terus berjuang di dalam negeri di bawah tuduhan korupsi dan nepotisme. Pengangkatannya sebagai menteri wanita pertama, Siva Obeyesekere, ke Kabinet Sri Lanka pada tahun 1976, kurang revolusioner karena fakta bahwa Obeyesekere adalah kerabat Bandaranaike. Pengangkatan itu mengikuti pola Bandaranaike yang mengangkat anggota keluarga ke posisi tinggi pemerintah.
Pada tahun 1980, sebuah Komisi Kepresidenan Khusus ditunjuk oleh Presiden J. R. Jayewardene untuk menyelidiki tuduhan terhadap Bandaranaike atas penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatannya sebagai perdana menteri. Setelah penyerahan laporan kepada Jayewardene, pemerintah Partai Nasional Bersatu mengadopsi mosi di parlemen pada 16 Oktober 1980 untuk mencabut hak sipil Bandaranaike dan keponakannya, Felix Dias Bandaranaike - yang dihukum karena korupsi - selama tujuh tahun. Ia diusir dari parlemen, tetapi mempertahankan perannya sebagai pemimpin partai.
11. Sejarah Pemilu
Berikut adalah ringkasan hasil pemilihan umum yang diikuti oleh Sirimavo Bandaranaike sepanjang karier politiknya:
| Pemilu | Daerah Pemilihan | Partai | Suara | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Parlemen 1965 | Attanagalla | Partai Kebebasan Sri Lanka | 26.150 | Terpilih |
| Parlemen 1970 | Attanagalla | Partai Kebebasan Sri Lanka | 31.612 | Terpilih |
| Parlemen 1977 | Attanagalla | Partai Kebebasan Sri Lanka | 30.226 | Terpilih |
| Presiden 1988 | Sri Lanka | Partai Kebebasan Sri Lanka | 2.289.860 | Tidak Terpilih |
| Parlemen 1989 | Distrik Gampaha | Partai Kebebasan Sri Lanka | 214.390 | Terpilih |
12. Lihat Pula
- Daftar Perdana Menteri Sri Lanka
- S. W. R. D. Bandaranaike
- Chandrika Kumaratunga
- Anura Bandaranaike
- Sunethra Bandaranaike
- Partai Kebebasan Sri Lanka
- Gerakan Non-Blok