1. Biografi
Ismail Raji al-Faruqi memiliki latar belakang yang kaya dari Palestina yang dipimpin Inggris, pengalaman pendidikan yang beragam di Timur Tengah dan Amerika Serikat, serta karier akademik yang berdedikasi dalam studi Islam dan dialog antaragama.
1.1. Masa Muda dan Pendidikan
Al-Faruqi lahir pada 1 Januari 1921, di Jaffa, Palestina yang kala itu berada di bawah Mandat Inggris. Ayahnya, 'Abd al-Huda al-Faruqi, adalah seorang hakim Islam terkemuka. Pendidikan agama awalnya diterima di rumah dan di masjid setempat, dengan pengaruh signifikan dari ayahnya yang membentuk fondasi agama dan moralnya. Pada tahun 1936, ia melanjutkan pendidikannya di Collège des Frères de Jaffa, sebuah institusi Dominikan Prancis.
Setelah itu, ia pindah ke Beirut, Lebanon, untuk melanjutkan studi di American University of Beirut (AUB). Di AUB, al-Faruqi sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan nasionalis Arab dan para nasionalis Arab Kristen terkemuka seperti Constantin Zureiq, Nabih Amin Faris, dan Nicola Ziadeh, yang turut membentuk pemikiran awalnya mengenai Arabisme. Lingkungan akademik di AUB, termasuk kuliah misi Kristen yang wajib dihadiri dan kursus yang mempromosikan modernitas Barat, juga memengaruhi perkembangan ideologisnya.
Menyusul Perang Arab-Israel 1948, al-Faruqi melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar Master dalam filsafat dari Indiana University pada tahun 1949 dengan tesis berjudul The Ethics of Reason and the Ethics of Life (Kantian and Nietzschean Ethics). Dalam tesis ini, ia menganalisis etika Immanuel Kant dan Friedrich Nietzsche, yang menjadi dasar bagi kritik-kritik selanjutnya terhadap sistem etika Barat dan pengembangan pemikiran etika Islamnya. Ia kemudian meraih gelar Master kedua dalam filsafat dari Harvard University pada tahun 1951, dan memperoleh gelar Doktor Filsafat (Ph.D.) dari Indiana University pada tahun 1952 dengan tesis berjudul On Justifying the Good. Dalam disertasi doktoralnya, al-Faruqi berpendapat bahwa nilai-nilai bersifat absolut dan mandiri, dikenal secara a priori melalui intuisi emosional. Ia mendasarkan teorinya pada penggunaan fenomenologi oleh Max Scheler dan studi etika oleh Nicolai Hartmann.
Selama periode studinya di Amerika, ia bertemu dan menikah dengan Lois Lamya al-Faruqi. Studi-studinya mengantarkannya pada kesimpulan bahwa ketiadaan fondasi transenden dapat menyebabkan relativisme moral, mendorongnya untuk mengevaluasi kembali warisan Islamnya. Dalam enam tahun setelah tiba di Amerika Serikat, ia menyadari perlunya studi Islam yang lebih mendalam, yang membawanya untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dari tahun 1954 hingga 1958. Pada saat ia meninggalkan Amerika Serikat untuk studi di Al-Azhar, ia telah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai kewajiban moral dan berupaya mengintegrasikan pencarian intelektualnya dengan identitas Islamnya.
1.2. Karier Awal
Sebelum memulai karier akademiknya yang utama, al-Faruqi memegang beberapa jabatan administratif penting di pemerintahan Palestina di bawah Mandat Inggris. Pada tahun 1942, ia ditunjuk sebagai pendaftar masyarakat koperasi di Yerusalem. Kemudian, pada tahun 1945, ia diangkat sebagai gubernur distrik Galilee. Posisi-posisi ini memberinya pengalaman langsung dalam administrasi publik dan pemerintahan.
1.3. Karier Akademik
Pada tahun 1958, al-Faruqi ditawari posisi sebagai seorang sarjana tamu di Fakultas Teologi McGill University di Montreal, Kanada. Ia bergabung dengan Institut Studi Islam atas undangan pendirinya, Wilfred Cantwell Smith, dan mengajar bersama Smith dari tahun 1958 hingga 1961. Selama masa ini, ia mempelajari teologi Kristen dan Yudaisme, serta menjalin perkenalan dengan filsuf Pakistan, Fazlur Rahman. Rahman mencatat bahwa keterlibatan al-Faruqi dalam tradisi-tradisi ini di bawah bimbingan Smith sangat penting dalam menyempurnakan pandangan komparatifnya tentang studi agama dan dialog antaragama.
Pada tahun 1961, Fazlur Rahman memfasilitasi penunjukan dua tahun bagi al-Faruqi di Institut Pusat Penelitian Islam di Karachi, Pakistan, di mana ia menjabat sebagai profesor tamu hingga tahun 1963. Rahman kemudian menekankan bahwa pengalaman ini memperdalam pemahaman al-Faruqi tentang keragaman budaya dalam Islam, sebuah pengaruh yang membentuk teori-teori selanjutnya tentang perbandingan agama dan meta-agama.
Pada tahun 1964, al-Faruqi kembali ke Amerika Serikat dan memegang peran ganda sebagai profesor tamu di Divinity School University of Chicago dan sebagai profesor asosiasi di Syracuse University. Pada tahun 1968, ia bergabung dengan Temple University sebagai profesor agama, tempat ia mendirikan Program Studi Islam dan menjabat posisi tersebut hingga kematiannya pada tahun 1986. Selama masa jabatannya di Temple University, al-Faruqi membimbing banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa doktoral pertamanya, John Esposito. Ia tidak hanya fokus pada bimbingan akademik tetapi juga memperluas pengaruhnya melalui inisiatif seperti Muslim Students Association (MSA), yang ia dirikan untuk mendukung komunitas mahasiswa Muslim. Rumahnya sering menjadi pusat pertemuan intelektual, di mana para mahasiswa dan cendekiawan dapat bertukar pandangan. Menurut Osman Bakar, dedikasi al-Faruqi dalam membantu mahasiswa melampaui bidang akademik, bahkan mempermudah proses pendaftaran di Temple berkat upaya langsungnya.
Pada Maret 1977, al-Faruqi memainkan peran penting dalam Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Muslim di Makkah. Konferensi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Kamal Hassan, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan Syed Ali Ashraf. Konferensi ini menjadi landasan bagi pendirian universitas-universitas Islam di Dhaka, Islamabad, Kuala Lumpur, Kampala, dan Niger. Al-Faruqi berperan penting dalam pembahasan dan pengembangan rencana aksi konferensi tersebut.
Ia juga menjabat sebagai penasihat bagi para pemimpin politik di dunia Muslim, termasuk Muhammad Zia-ul-Haq di Pakistan dan Mahathir Mohamad di Malaysia. Selama pemerintahan Zia-ul-Haq, al-Faruqi berkontribusi pada pendirian International Islamic University di Islamabad pada tahun 1980, yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin akademik kontemporer. Di Malaysia, al-Faruqi menasihati Perdana Menteri Mahathir Mohamad, membantu pendirian International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 1983. Kedua institusi ini didirikan untuk menggabungkan pengetahuan agama dan sekuler dalam kerangka pendidikan yang holistik.
Pada tahun 1980, Ismail al-Faruqi turut mendirikan International Institute of Islamic Thought (IIIT) bersama Taha Jabir Alalwani, Abdul Hamid AbuSulayman, dan Anwar Ibrahim. Keterlibatannya dalam dialog antaragama mempromosikan pemahaman dan kerja sama bersama di antara komunitas agama, membina lingkungan global yang damai dan saling menghormati yang menyoroti kesamaan antara Islam, Kristen, dan Yudaisme. Selain itu, al-Faruqi adalah akademisi Muslim pertama yang menggunakan pendekatan fenomenologi dan sejarah agama, yang ia pandang penting untuk memahami Islam sebagai bagian dari sejarah agama manusia dan memungkinkan Muslim untuk terlibat dalam studi agama modern.
2. Pemikiran dan Filsafat
Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi berkembang sepanjang hidupnya, bergeser dari fokus awal pada Arabisme ke identitas Islam yang lebih luas, dan mencakup kontribusi signifikan dalam etika, teori nilai, tauhid, meta-agama, perbandingan agama, dan Islamisasi ilmu pengetahuan.
2.1. Pemikiran Awal: Arabisme
Fokus intelektual awal al-Faruqi berpusat pada konsep 'urubahBahasa Arab (Arabisme). Ia berpendapat bahwa urubah adalah inti identitas yang menyatukan semua Muslim menjadi satu komunitas orang beriman (ummah) dan bahwa bahasa Arab, sebagai bahasa Al-Qur'an, sangat penting untuk memahami sepenuhnya ajaran Islam. Al-Faruqi meyakini bahwa urubah memiliki dimensi linguistik dan agama yang terjalin erat, dengan menyatakan bahwa Islam dan monoteisme merupakan kontribusi Arabisme bagi kemanusiaan. Ia berpendapat bahwa pemulihan peradaban Islam bergantung pada revitalisasi bahasa Arab sebagai kekuatan budaya pemersatu bagi Muslim secara global.
Konsepnya tentang Arabisme melampaui nasionalisme, menempatkannya sebagai jembatan ideologis melintasi perpecahan etnis dalam Islam. Ia juga menekankan tauhid (monoteisme) sebagai elemen penentu kesadaran agama Arab, yang berakar pada budaya dan bahasa Arab, serta ditemukan dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Al-Faruqi berpendapat bahwa kebangkitan Islam memerlukan peningkatan bahasa dan budaya Arab sebagai elemen pemersatu bagi Muslim di berbagai wilayah.
Meskipun al-Faruqi sangat berkomitmen pada 'urubah, beberapa cendekiawan mengkritik pendiriannya sebagai esensialis, dengan alasan bahwa hal itu berisiko meminggirkan Muslim non-Arab. Kritik ini, terutama dari intelektual Muslim non-Arab, menyoroti kekhawatiran bahwa filosofi awalnya memprioritaskan budaya Arab di atas aspek universal Islam. Namun, pengalamannya di luar negeri, terutama di Pakistan yang kaya akan keragaman budaya Muslim, mulai memengaruhi perspektifnya, secara bertahap menjauhkannya dari pandangan yang hanya berpusat pada Arab. Pergeseran ini mencerminkan keyakinan al-Faruqi pada peradaban Islam transnasional yang mempromosikan persatuan lintas batas linguistik dan budaya, dengan prioritas pada dimensi spiritual dan etika bersama.
2.2. Etika dan Teori Nilai
Penyelidikan filosofis al-Faruqi mencakup kritik terhadap etika Kantian, khususnya mengenai universalitas moral, yang ingin ia kembangkan lebih lanjut dalam kerangka etika Islam. Dalam disertasi doktoralnya, On Justifying the Good (1952), al-Faruqi membahas pertanyaan filosofis tentang kebaikan, nilai, dan etika, sambil secara kritis berinteraksi dengan teori etika Barat. Mengambil inspirasi dari karya-karya filsuf seperti Max Scheler dan Immanuel Kant, al-Faruqi mengidentifikasi dua kesalahan utama dalam penalaran etis: sesat pikir naturalistik dan sesat pikir ambiguitas. Ia berpendapat bahwa sesat pikir naturalistik muncul ketika konsep etis disamakan dengan keinginan alami manusia. Al-Faruqi mengkritik asosiasi John Stuart Mill antara kebahagiaan dengan keinginan, dengan alasan bahwa pandangan ini berisiko menyamakan nilai etis dengan keinginan subjektif, yang ia anggap berpotensi mengarah pada relativisme etis.
Analisis al-Faruqi tentang sesat pikir ambiguitas berfokus pada apa yang ia gambarkan sebagai atribusi nilai berdasarkan standar yang tidak jelas. Ia berpendapat bahwa para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel kadang-kadang menyamakan istilah seperti "utilitas" dan "nilai" tanpa memberikan perbedaan yang jelas. Menurut al-Faruqi, mendefinisikan kebajikan terutama dalam hal kebahagiaan dapat mengaburkan sifat sejati nilai etis. Ia mengusulkan bahwa nilai-nilai harus dipahami secara independen dari standar empiris atau relatif, dan mengklaim bahwa nilai-nilai tersebut diketahui secara a priori melalui intuisi emosional, bukan observasi empiris.
Dalam pemeriksaannya terhadap teori-teori Scheler, al-Faruqi mengusulkan klasifikasi nilai, membedakan antara nilai intrinsik dan absolut. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai ini ada secara independen dari pengaruh empiris dan menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut mewakili fondasi untuk penyelidikan etis. Kerangka kerja al-Faruqi dalam teori nilai dimaksudkan untuk memberikan alternatif terhadap apa yang ia pandang sebagai keterbatasan dalam pemikiran etika Barat. Disertasinya meletakkan dasar bagi upaya-upaya selanjutnya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam disiplin akademik modern, berkontribusi pada konsepnya yang lebih luas tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan.
2.3. Pergeseran ke Islamisme
Pandangan al-Faruqi bergeser secara signifikan setelah ia pindah ke Amerika Serikat, di mana keterlibatannya dengan Muslim Students Association (MSA) di Temple University mempertemukannya dengan beragam mahasiswa Muslim. Pengalaman ini mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali penekanan awalnya pada Arabisme, beralih ke identitas Islam yang lebih luas daripada nasionalisme Arab. Malik Badri menggambarkan transformasi ini, mencatat bahwa, "Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, al-Faruqi bertemu sekelompok mahasiswa muda yang menghancurkan konsep Arabisme-nya. Ia harus tunduk pada Islam sebagai kekuatan pengikat sejati ummah-terutama karena Arab hanya merupakan minoritas kecil di dalamnya." Al-Faruqi sendiri mengartikulasikan pergeseran ini dengan menyatakan, "Sampai beberapa bulan yang lalu, saya adalah seorang Palestina, seorang Arab, dan seorang Muslim. Sekarang saya adalah seorang Muslim yang kebetulan seorang Arab dari Palestina." Ia lebih lanjut berkomentar, "Saya bertanya pada diri sendiri: Siapakah saya? Seorang Palestina, seorang filsuf, seorang humanis liberal? Jawaban saya adalah: Saya seorang Muslim."
Dalam tahun-tahun terakhirnya, al-Faruqi menekankan pentingnya hukum Islam sebagai kerangka kerja untuk membentuk norma-norma etis dan sosial. Ia menggambarkan langkah-langkah hukum, seperti hukuman untuk pencurian dan perzinahan, sebagai pencegah yang dirancang untuk menumbuhkan disiplin dan mencegah kerugian sosial. Al-Faruqi memandang hukum-hukum ini sebagai bagian dari upaya yang lebih besar, yang berpusat pada pendidikan, untuk menanamkan perilaku etis dan menumbuhkan masyarakat yang adil.
Dalam eksplorasinya tentang peran Islam di Amerika Utara, al-Faruqi juga menyoroti kontribusi sejarah dan tantangan Muslim Afrika, dari permukiman awal hingga pengaruh Elijah Muhammad dan Malcolm X pada gerakan Islam di kalangan Afrika-Amerika. Wawasannya tentang fondasi etis Islam, konsep Ummah, dan tanggung jawab imigran Muslim telah memainkan peran dalam membentuk pengalaman Muslim di Amerika Utara.
Pergeseran ini juga memengaruhi pendekatannya terhadap dialog antaragama. Al-Faruqi percaya bahwa identitas Islam yang bersatu sangat penting untuk memupuk interaksi yang bermakna dengan komunitas non-Muslim. Keterlibatannya dalam MSA dan keterpaparan terhadap beragam latar belakang Muslim di AS memperkuat komitmennya terhadap identitas Islam yang lebih luas dan inklusif daripada pandangan Arab-sentris sebelumnya.
2.4. Pandangan tentang Tawhid
Pandangan al-Faruqi tentang tauhid mencakup perspektif kritis terhadap Sufisme, yang ia anggap terlalu menekankan mistisisme dan praktik esoterisme. Ia mengkritik Sufisme karena mistisismenya, dengan alasan bahwa sering kali mengalihkan perhatian dari aspek rasional dan praktis Islam. Al-Faruqi terinspirasi oleh para teolog Mu'tazili seperti al-Nazzam dan Al-Qadi Abd al-Jabbar, yang menganjurkan penggunaan akal dan logika dalam memahami prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ia menemukan nilai dalam karya-karya Ikhwān al-Ṣafāʾ, yang tulisan-tulisannya menggabungkan ajaran Islam dengan elemen filsafat Yunani.
Penekanan al-Faruqi pada tauhid melampaui teologi, mencakup pendekatan terintegrasi yang menyatukan pemikiran rasional, etika, dan tanggung jawab sosial di semua aspek kehidupan. Ia berpendapat bahwa tauhid adalah "hal yang memberikan peradaban Islam identitasnya, yang mengikat semua konstituennya bersama-sama dan dengan demikian menjadikannya tubuh yang integral dan organik yang kita sebut peradaban." Al-Faruqi menjelaskan:
: "Mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah (SWT) adalah mengakui Dia sebagai satu-satunya Pencipta, Tuhan, dan Hakim dunia. Dari kesaksian ini, lahirlah bahwa manusia diciptakan untuk suatu tujuan, karena Tuhan tidak bekerja sia-sia; dan bahwa tujuan ini adalah perwujudan kehendak ilahi sebagaimana yang berkaitan dengan dunia tempat kehidupan manusia menemukan panggungnya."
Ia juga menyatakan bahwa prinsip ini "membersihkan agama dari segala keraguan mengenai transendensi dan keunikan Ketuhanan."
Pendekatan ini meluas ke visinya tentang sekularisme dan materialisme, yang ia pandang sebagai tantangan terhadap persatuan Islam dan integritas etis. Al-Faruqi berpendapat bahwa visi Islam untuk masyarakat memerlukan pandangan dunia yang terintegrasi di mana tauhid "menandai sekularisasi lengkap dunia alami untuk memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan," sehingga memisahkan yang sakral dari alam sambil mempertahankan kerangka etis yang terpadu. Tanggapannya terhadap ideologi sekuler Barat berakar pada keyakinan bahwa tauhid menyerukan kerangka holistik di mana akal dan iman bekerja bersama, berbeda dengan pembagian spiritual-material yang terlihat dalam ideologi sekuler.
2.5. Meta-agama
Al-Faruqi berusaha untuk menetapkan prinsip-prinsip meta-agama yang didasarkan pada akal, bertujuan untuk mengevaluasi agama-agama berdasarkan standar universal daripada membandingkannya satu sama lain. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan titik temu bagi kerja sama di antara berbagai agama. Inti dari konsep meta-agamanya adalah keyakinan intrinsik yang sama akan Tuhan Yang Esa, yang ia berpendapat mewakili "bentuk murni iman" asli yang mendahului diversifikasi agama-agama. Seperti yang dibayangkan al-Faruqi, meta-agama berbeda dari agama historis, berfokus pada prinsip-prinsip universal yang berakar pada fitrah (agama alami) sebagai dasar untuk saling pengertian dan kerja sama antariman.
Dalam kerangka ini, din al-fitrah adalah disposisi bawaan manusia terhadap ilahi, menunjukkan bahwa meta-agama menyediakan pengakuan kebenaran yang terinternalisasi yang melampaui label agama tertentu. Perspektif ini mendukung bentuk pemahaman antariman yang mengakui fondasi spiritual bersama tanpa menyamakan kekhususan doktrinal setiap agama. Daripada menegaskan pluralisme agama dalam pengertian konvensionalnya, meta-agama menegaskan bahwa agama-agama mencerminkan berbagai tingkat kebenaran monoteistik asli yang melekat dalam sifat manusia.
Untuk memfasilitasi dialog, al-Faruqi mengusulkan beberapa prinsip panduan: semua dialog harus terbuka untuk kritik, komunikasi harus mematuhi hukum koherensi internal dan eksternal, dialog harus selaras dengan realitas dan tetap bebas dari "figurasi kanonik," dan diskusi harus menekankan pertanyaan etis daripada perselisihan teologis. Konsep meta-agama al-Faruqi melibatkan keyakinan akan Tuhan atau Realitas Utama sebagai "yang sama sekali lain." Ia menekankan bahwa Islam, sebagai meta-agama universal yang disampaikan oleh semua nabi, berpusat pada konsep tauhid, yang mencakup keesaan dan transendensi Tuhan serta kewajiban manusia untuk merefleksikan harmoni ilahi di dalam dunia.
Al-Faruqi juga menegaskan bahwa studi agama harus kurang berfokus pada validasi kebenarannya melalui ukuran eksternal atau fungsional dan lebih pada pemahaman kondisi homo religiosus-manusia yang secara alami religius dengan kesadaran bawaan akan ilahi. Bagi al-Faruqi, dialog meta-agama berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat di antara komunitas agama, menjembatani kesenjangan yang diciptakan oleh perbedaan doktrinal. Penekanannya pada etika daripada teologi dimaksudkan untuk mendukung keterlibatan antariman yang lebih konstruktif dan tidak terlalu kontroversial.
2.6. Perbandingan Agama
Karya al-Faruqi dalam perbandingan agama bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja bagi keterlibatan yang saling menghormati di antara berbagai tradisi agama. Ia mengeksplorasi kontras dan konvergensi filosofis antara Islam dan Kristen, khususnya mengenai interpretasi Kitab Suci Ibrani. Ia menekankan bahwa selama puncak peradaban Islam, dialog antaragama adalah hobi publik dan topik umum di kalangan intelektual, menunjukkan keunggulan historisnya. Pendekatannya meneliti metode hermeneutika dan kerangka teologis yang berbeda, mengidentifikasi nilai-nilai bersama yang dapat mendukung dialog antariman sambil menghormati perbedaan doktrinal. Ia percaya pada nilai dialog yang dimulai berdasarkan saling menghormati dan pertimbangan etis, menyatakan bahwa "konversi menuju kebenaran adalah tujuan dialog," mencerminkan komitmennya terhadap keterlibatan antariman yang jujur.
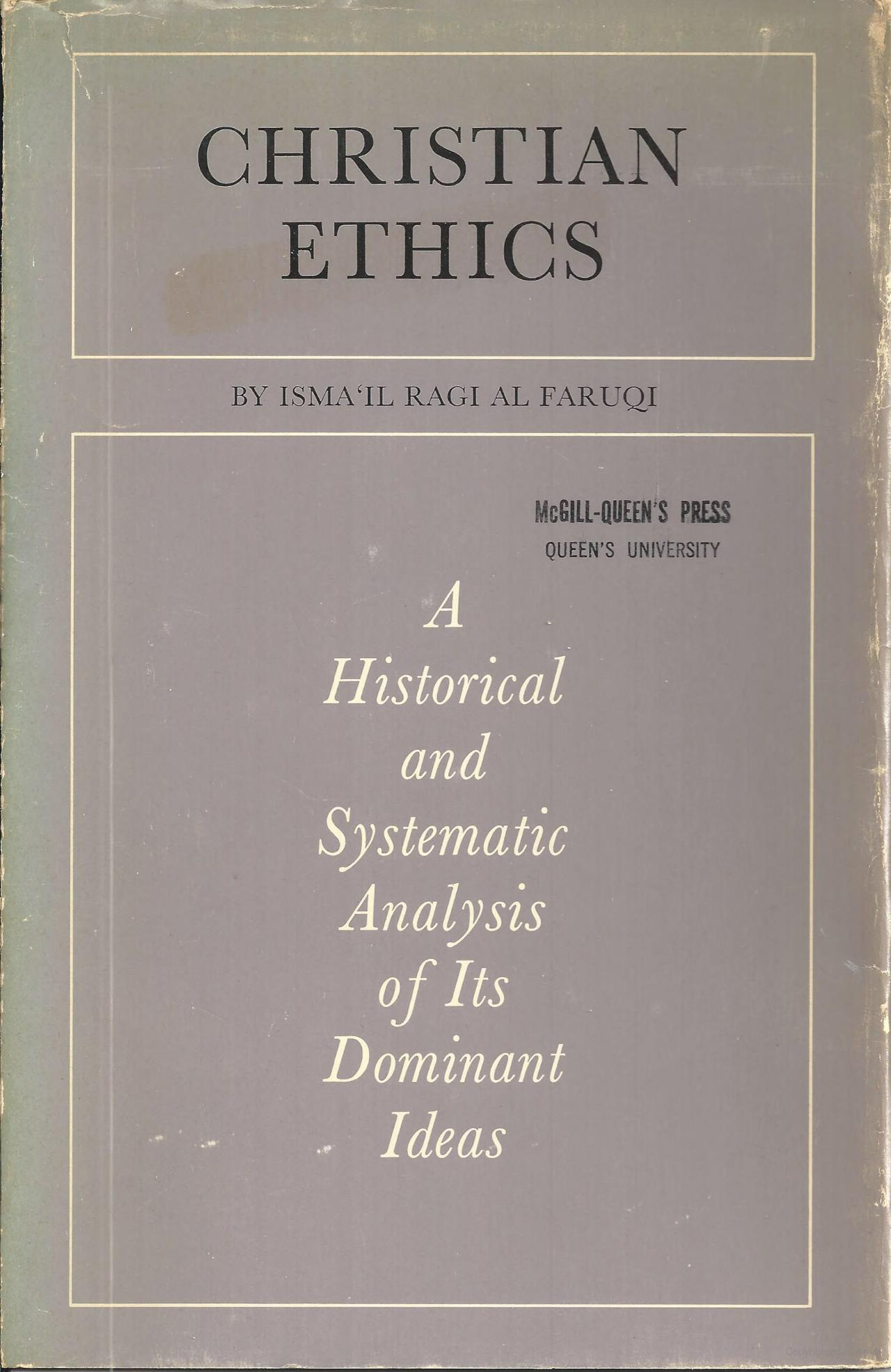
Al-Faruqi berpendapat bahwa, tidak seperti Islam, Kekristenan tidak memiliki fondasi eksplisit untuk menyusun kerangka sosial seperti hukum dan ekonomi, yang ia pandang penting untuk kohesi sosial:
: "Kurangnya fondasi dalam dogma Kristen untuk sosiolisme yang sehat sangat mengganggu pikiran Kristen selama seratus tahun terakhir. Pertumbuhan pusat-pusat kota, industri, sarana komunikasi, membawa pada kesadaran akan kebutuhan akan jenis kohesi sosial yang baru... Tetapi Gereja, sebagai penjaga setia warisan itu, hanya bisa menjawabnya dalam paradoks yang tidak berguna... Bukan karena Gereja bisa membantu tetapi menahan diri-ia benar-benar melakukan yang terbaik-tetapi karena tidak ada cara untuk mengabaikan fakta bahwa pesan Yesus bukanlah pesan sosiolisme."
Ia lebih lanjut mengamati apa yang ia pandang sebagai konflik internal fundamental dalam etika Barat yang berasal dari warisan dualistis ini, menyatakan:
: "Sejak ia menjadi seorang Kristen, manusia Barat telah menjalani kehidupan yang terpecah dan menderita kepribadian yang terpecah. Yesus dan penolakan etisnya di satu sisi, dan alam dengan penegasan diri, penegasan alam, dan 'keduniawian' di sisi lain, membagi kesetiaan dan keberadaannya. Meskipun ia menjalani hidupnya tanpa menyadari penekanan Yesus pada spiritual di atas dan melawan material, namun ia memohon berkat Yesus untuk setiap langkah."
Selain eksplorasinya tentang teologi Kristen, al-Faruqi juga terlibat dengan filosofi Barat kontemporer, meneliti etika melalui pemikir seperti Kant, Scheler, dan Hartmann. Studi komparatifnya juga meluas ke pertanyaan etis dan metafisik, di mana ia menyoroti sistem nilai yang berbeda antara pemikiran Barat dan Islam. Dalam meneliti tradisi agama secara historis, al-Faruqi melihat potensi dialog antariman yang mengakui prinsip-prinsip bersama bersama dengan keyakinan-keyakinan yang khas. Al-Faruqi berpendapat bahwa etika Barat sering menekankan individualisme, sedangkan etika Islam memprioritaskan kesejahteraan komunal dan akuntabilitas ilahi. Kerangka kerja yang kontras ini, ia sarankan, membentuk pandangan yang lebih luas dari setiap tradisi tentang moralitas, keberadaan, dan tujuan.
Beberapa kritikus, seperti Damian Howard, berpendapat bahwa pendekatan al-Faruqi terhadap keterlibatan antariman terlalu menekankan sudut pandang Islam daripada membina pemahaman timbal balik antar agama, yang berpotensi membatasi kedalaman dan inklusivitas dialog.
2.7. Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Al-Faruqi berperan penting dalam mengkonseptualisasikan pengetahuan holistik, sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan disiplin modern, sebuah pendekatan yang sering digambarkan sebagai neo-modernis. Prihatin tentang sekularisasi pengetahuan dalam masyarakat Muslim, al-Faruqi menganjurkan epistemologi holistik, menafsirkan ulang pemikiran Islam untuk mengatasi tantangan kontemporer. Ia menggambarkan apa yang ia sebut "penyakit ummah", dengan alasan bahwa ketergantungan pada alat dan metodologi Barat menyebabkan terputusnya hubungan dari realitas ekologis dan sosial di negara-negara Muslim, sering kali mengabaikan etika Islam yang esensial. Al-Faruqi menekankan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pengetahuan modern untuk membantu menjaga tatanan etis komunitas Muslim.
Bagian akhir dari karier al-Faruqi berpusat pada konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Menanggapi apa yang ia lihat sebagai sekularisasi dan dominasi Barat atas sistem pendidikan Muslim, ia membayangkan integrasi nilai-nilai Islam dengan disiplin ilmiah dan akademik kontemporer, pada akhirnya berusaha untuk epistemologi yang berakar pada integritas etis. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip ekonomi seperti zakat dan larangan riba untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi selaras dengan etika Islam. Gagasan-gagasannya akhirnya mengarah pada pendirian International Institute of Islamic Thought (IIIT), yang bertujuan untuk menciptakan epistemologi dan metodologi Islam yang berlaku di berbagai disiplin ilmu.
Metodologi al-Faruqi juga meluas ke ilmu sosial, di mana ia menganjurkan kerangka kerja yang mempertahankan pertimbangan etis Islam sambil mengkritik sekularisme Barat. Tujuannya adalah untuk mengganti prinsip-prinsip sekuler dengan fondasi yang dibangun di atas etika Islam yang selaras dengan nilai-nilai ummah. Ia membayangkan kurikulum Islam terpadu yang menggabungkan disiplin kontemporer sambil secara tegas mendasarkannya pada pemikiran Islam. Pendekatan ini berusaha untuk menghasilkan para cendekiawan yang mampu mengatasi tantangan modern dari perspektif Islam, menekankan pengembangan kurikulum dan strategi praktis untuk mereformasi sistem pendidikan.
Beberapa cendekiawan, seperti Ibrahim Kalin, mengkritik fokus al-Faruqi pada ilmu humaniora, dengan alasan bahwa hal itu membuat ilmu alam sebagian besar tidak diperiksa. Kalin menggambarkan karya al-Faruqi sebagai contoh bagaimana "gagasan metode atau metodologi (manhajBahasa Arab dan manhajiyyahBahasa Arab)... dapat mengaburkan masalah filosofis yang lebih dalam yang terlibat dalam diskusi sains saat ini." Meskipun tujuan al-Faruqi adalah mengislamkan pengetahuan Barat, Kalin menegaskan, fokusnya "secara eksklusif pada ilmu humaniora, membiarkan pengetahuan ilmiah hampir tidak tersentuh." Kelalaian ini, menurut Kalin, menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan: "Pertama, karya penting Faruqi tentang Islamisasi memberikan pengikutnya kerangka di mana pengetahuan ('ilmBahasa Arab) disamakan dengan disiplin sosial, sehingga berakhir pada semacam sosiologisme... Kedua, pengecualian pengetahuan ilmiah modern dari ruang lingkup Islamisasi telah menyebabkan sikap lalai... terhadap efek sekularisasi dari pandangan dunia ilmiah modern." Kritik Kalin menunjukkan bahwa keterlibatan terbatas al-Faruqi dengan pengetahuan ilmiah berisiko menciptakan kerangka yang terlalu berpusat pada interpretasi sosiologis pengetahuan Islam. Dengan menghilangkan ilmu alam, Kalin berpendapat, pendekatan al-Faruqi secara tidak sengaja memperkuat pemisahan sekuler antara ilmu alam dan ilmu humaniora yang mungkin membuat intelektual Muslim modern tidak siap untuk mengatasi tantangan filosofis dan epistemologis yang diajukan oleh ilmu pengetahuan kontemporer.
2.8. Kritik terhadap Zionisme
Al-Faruqi adalah seorang kritikus vokal terhadap Zionisme, memandangnya sebagai ideologi nasionalis yang tidak sesuai dengan Yudaisme. Ia berpendapat bahwa Zionisme pada dasarnya tidak adil, karena berusaha menggusur penduduk asli Palestina dan merebut tanah, sumber daya, serta rumah mereka. Ia menggambarkannya sebagai "perampokan telanjang dengan kekuatan senjata," disertai dengan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil:
: "Rencananya adalah mengosongkan Palestina dari penduduk aslinya dan menduduki tanah, pertanian, rumah, dan semua propertinya. Zionisme bersalah atas perampokan telanjang dengan kekuatan senjata; pembantaian pria, wanita, dan anak-anak secara semena-mena, tanpa pandang bulu; penghancuran kehidupan dan properti manusia."
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembongkaran Zionisme diperlukan untuk memulihkan keadilan.
Al-Faruqi membayangkan jalur alternatif bagi Yahudi Israel yang menolak Zionisme, menyarankan bahwa mereka dapat hidup sebagai "komunitas ummatik" di dalam dunia Muslim, di mana mereka dapat melestarikan iman mereka di bawah hukum Yahudi sebagaimana ditafsirkan oleh pengadilan rabinik yang didukung dalam kerangka Islam. Perspektif ini menyoroti keyakinannya bahwa pemerintahan Islam dapat mengakomodasi komunitas yang beragam tanpa memaksakan praktik keagamaan mereka:
: "[Islam] mengharuskan orang Yahudi untuk mendirikan pengadilan rabinik mereka sendiri dan menyerahkan seluruh kekuasaan eksekutifnya. Syariah, hukum Islam, menuntut semua orang Yahudi untuk tunduk pada ajaran hukum Yahudi sebagaimana ditafsirkan oleh pengadilan rabinik, dan memperlakukan penentangan atau penghinaan terhadap pengadilan rabinik sebagai pemberontakan terhadap negara Islam itu sendiri, setara dengan tindakan serupa oleh seorang Muslim terhadap pengadilan Islam."
Merenungkan dampak Zionisme, al-Faruqi berpendapat bahwa alih-alih memberikan keamanan bagi orang Yahudi, Zionisme telah menciptakan keberadaan yang genting di Israel, di mana kehidupan menjadi ditentukan oleh konflik dan ketergantungan pada kekuatan asing:
: "Zionisme tidak hanya berkontribusi pada keadaan menyedihkan ini. Ia secara langsung bertanggung jawab untuk itu. Lalu, bagaimana bisa dikatakan bahwa ia berhasil memberikan keamanan bagi orang Yahudi? Bahkan di jantung Zionisme, di Israel, orang Yahudi duduk di tengah gudang senjata, mengelilingi dirinya dengan kawat berduri, ladang ranjau, dan segala jenis persenjataan untuk mencegah serangan yang ia tahu pasti akan datang, cepat atau lambat. Keberadaan mereka adalah spartanisme yang teratur, sebagian besar karena kebaikan imperialisme dan kolonialisme internasional. Jadi, Israel, yang disebut sebagai pencapaian terbesar Zionisme, sebenarnya adalah kegagalan terbesarnya. Karena keberadaan negara Zionis, pada analisis terakhir, bergantung pada keinginan sesaat politik internasional."
Kritik al-Faruqi terhadap Zionisme berakar pada komitmennya terhadap keadilan sebagaimana didefinisikan dalam pandangan dunia Islam.
3. Kehidupan Pribadi
Kehidupan pribadi Ismail Raji al-Faruqi erat kaitannya dengan kehidupan profesionalnya. Ia menikah dengan Lois Lamya al-Faruqi, seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang juga berkontribusi dalam bidang seni dan budaya Islam. Lois Lamya al-Faruqi adalah seorang sarjana seni Islam yang diakui secara internasional. Mereka memiliki hubungan keluarga yang kuat dan sering berkolaborasi dalam berbagai proyek intelektual.
Rumah mereka di Wyncote, Pennsylvania sering menjadi pusat pertemuan intelektual bagi para mahasiswa dan cendekiawan, mencerminkan komitmen mereka yang mendalam terhadap komunitas dan pendidikan Islam. Selain itu, Anis Ahmad berbagi kisah bahwa al-Faruqi pernah menceritakan tentang dua doa ayahnya: agar ia menjadi seorang cendekiawan besar dan meninggal sebagai seorang syahid (martir). Al-Faruqi dilaporkan pernah bertanya, "Sekarang saya seorang cendekiawan, tapi bagaimana saya bisa mati syahid di AS?" Malik Badri merenungkan bahwa "Allah Ta'ala menerima kedua doa tersebut." Kisah ini memberikan wawasan tentang aspirasi spiritual dan takdir yang diyakini al-Faruqi dalam hidupnya.
4. Kematian
Ismail Raji al-Faruqi dan istrinya, Lois Lamya al-Faruqi, menjadi korban pembunuhan tragis di rumah mereka di Wyncote, Pennsylvania, pada tanggal 27 Mei 1986. Insiden ini mengguncang komunitas akademik dan antaragama secara luas.

Pelaku kejahatan tersebut diidentifikasi sebagai Joseph Louis Young, yang juga dikenal dengan nama Yusuf Ali. Young, yang memiliki hubungan sebelumnya dengan komunitas Muslim setempat, mengaku melakukan kejahatan tersebut. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati dan meninggal di penjara karena sebab alami pada tahun 1996.
Selain pasangan al-Faruqi, putri mereka, Anmar el-Zein, yang saat itu sedang hamil, juga menjadi korban serangan tersebut. Ia menderita beberapa luka tusuk yang parah namun berhasil selamat setelah menerima perawatan medis intensif.
Meskipun pelaku telah tertangkap dan mengaku, motif di balik pembunuhan ini masih menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Berbagai teori telah diajukan, mulai dari percobaan perampokan yang gagal hingga kemungkinan adanya motif politik atau religius yang lebih dalam. Kasus ini menarik perhatian luas dan menjadi titik duka bagi banyak pihak yang mengenang kontribusi besar pasangan al-Faruqi dalam bidang keilmuan dan dialog antaragama.
5. Warisan dan Penilaian
Warisan Ismail Raji al-Faruqi tetap berpengaruh dalam studi Islam, dialog antaragama, dan reformasi pendidikan kontemporer, meskipun pemikirannya juga menghadapi kritik dan kontroversi.
5.1. Pencapaian Keilmuan
Al-Faruqi memberikan kontribusi besar pada studi Islam melalui tulisan-tulisannya yang luas dan keterlibatannya aktif dalam organisasi akademik dan antaragama. Ia menulis lebih dari 100 artikel di jurnal dan majalah ilmiah serta menerbitkan 25 buku berpengaruh, termasuk Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (1968), Islam and the Problem of Israel (1980), dan Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life (1982). Karya-karya ini membahas berbagai topik, termasuk etika, teologi, dialog antaragama, dan integrasi pemikiran Islam ke dalam disiplin akademik kontemporer.
Al-Faruqi adalah akademisi Muslim pertama yang terlibat dalam pendekatan fenomenologi dan sejarah agama. Ia memandang pendekatan ini sebagai kontribusi untuk mengapresiasi Islam sebagai bagian dari sejarah agama manusia dan memungkinkan Muslim terlibat dalam studi agama modern serta berpartisipasi dalam membangun pemahaman antaragama.
Pada tahun 1973, al-Faruqi mendirikan Kelompok Studi Islam di American Academy of Religion (AAR) dan memimpinnya selama sepuluh tahun. Inisiatif ini menyediakan platform formal bagi para cendekiawan Muslim untuk terlibat dalam dialog dengan cendekiawan dari tradisi agama lain, khususnya dalam perbandingan agama dan studi antariman. Selain karya akademiknya, al-Faruqi memegang posisi kepemimpinan seperti wakil presiden Kolokium Perdamaian Antar-Agama dan presiden American Islamic College di Chicago.
Pada Maret 1977, al-Faruqi memainkan peran penting dalam Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Muslim di Makkah. Konferensi ini dihadiri oleh peserta seperti Muhammad Kamal Hassan, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan Syed Ali Ashraf, di antara banyak lainnya. Konferensi ini meletakkan dasar bagi pendirian universitas-universitas Islam di Dhaka, Islamabad, Kuala Lumpur, Kampala, dan Niger. Al-Faruqi berperan penting dalam pembahasan konferensi dan pengembangan rencana tindakannya.
Ia juga menjabat sebagai penasihat bagi para pemimpin politik di dunia Muslim, termasuk Muhammad Zia-ul-Haq di Pakistan dan Mahathir Mohamad di Malaysia. Selama pemerintahan Zia-ul-Haq, al-Faruqi berkontribusi pada pendirian International Islamic University di Islamabad pada tahun 1980, yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin akademik kontemporer. Di Malaysia, al-Faruqi menasihati Perdana Menteri Mahathir Mohamad, membantu pendirian International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 1983. Kedua institusi ini didirikan untuk menggabungkan pengetahuan agama dan sekuler dalam kerangka pendidikan yang holistik.
Pada tahun 1980, Ismail al-Faruqi turut mendirikan International Institute of Islamic Thought (IIIT) bersama Taha Jabir Alalwani, Abdul Hamid AbuSulayman, dan Anwar Ibrahim. Keterlibatannya dalam dialog antaragama mempromosikan pemahaman dan kerja sama bersama di antara komunitas agama, membina lingkungan global yang damai dan saling menghormati yang menyoroti kesamaan antara Islam, Kristen, dan Yudaisme.
5.2. Dampak dan Relevansi Kontemporer
Gagasan al-Faruqi tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan terus bergema dalam pemikiran Islam kontemporer, memengaruhi pengembangan kurikulum di universitas-universitas seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) dan International Islamic University, Islamabad. Penekanannya pada integrasi prinsip-prinsip Islam dengan disiplin akademik modern tetap relevan di kalangan para cendekiawan dan pendidik yang bertujuan untuk menyelaraskan iman dan akal. Karyanya sering dikutip dalam konferensi akademik dan publikasi yang berkaitan dengan pemikiran dan pendidikan Islam.
Kontribusi al-Faruqi terhadap dialog antaragama juga diakui secara luas. Pendekatannya menekankan pencarian titik temu etis dan moral di antara tradisi-tradisi agama, khususnya Islam, Kristen, dan Yudaisme. Para cendekiawan mencatat bahwa fokusnya pada prinsip-prinsip etika di atas perbedaan teologis membina saling pengertian dan rasa hormat di antara komunitas-komunitas agama. Kerangka kerjanya telah berpengaruh dalam upaya global untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama lintas perbedaan agama.
Dampak al-Faruqi melampaui akademisi ke dalam aplikasi praktis. Karyanya dalam studi agama menginspirasi penciptaan program akademik terkait, khususnya di institusi-institusi yang telah mengadopsi metodologinya, seperti mata kuliah studi agama wajib di International Islamic University Malaysia, yang bertujuan untuk memahami tradisi spiritual dan signifikansi peradabannya secara komprehensif.
Selain itu, karya-karya ilmiah al-Faruqi, seperti Christian Ethics dan Trialogue of the Abrahamic Faiths, terus berfungsi sebagai sumber daya kunci dalam dialog antaragama dan studi perbandingan agama. Karya-karya ini telah membentuk diskusi di lingkaran akademik Islam dan Barat, menyoroti persimpangan antara tradisi-tradisi agama ini. Kontribusinya telah diakui secara anumerta, khususnya di komunitas seperti Montreal, di mana kesarjanaan dan upaya pembangunan komunitasnya meninggalkan dampak yang abadi.
5.3. Kritik dan Kontroversi
Meskipun Ismail Raji al-Faruqi dihormati atas kontribusinya, beberapa aspek pemikirannya telah menjadi sasaran kritik. Salah satu kritik utama datang dari cendekiawan seperti Ibrahim Kalin, yang berpendapat bahwa fokus al-Faruqi pada Islamisasi ilmu pengetahuan terutama tertuju pada ilmu humaniora, dan secara signifikan mengabaikan ilmu alam. Kalin mengemukakan bahwa kelalaian ini menciptakan bias sosiologis dalam kerangka pengetahuan Islam yang diusulkan al-Faruqi, berpotensi mengabaikan dampak sekularisasi pandangan dunia ilmiah modern. Akibatnya, menurut Kalin, para cendekiawan Muslim mungkin tidak cukup siap untuk menghadapi tantangan filosofis dan epistemologis yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan kontemporer, dan ini dapat memperkuat dikotomi antara ilmu alam dan ilmu humaniora.
Selain itu, pendekatan al-Faruqi terhadap dialog antaragama juga mendapat kritik. Beberapa sarjana, seperti Damian Howard, berpendapat bahwa meskipun al-Faruqi menganjurkan dialog, pendekatannya cenderung lebih menekankan sudut pandang Islam daripada mempromosikan pemahaman timbal balik yang seimbang di antara berbagai keyakinan. Kritik ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatasi kedalaman dan inklusivitas dialog antariman yang ia maksudkan.
6. Warisan dan Penilaian
Warisan Ismail Raji al-Faruqi tetap berpengaruh dalam studi Islam, dialog antaragama, dan reformasi pendidikan kontemporer, meskipun pemikirannya juga menghadapi kritik dan kontroversi.
6.1. Pencapaian Keilmuan
Al-Faruqi memberikan kontribusi besar pada studi Islam melalui tulisan-tulisannya yang luas dan keterlibatannya aktif dalam organisasi akademik dan antaragama. Ia menulis lebih dari 100 artikel di jurnal dan majalah ilmiah serta menerbitkan 25 buku berpengaruh, termasuk Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (1968), Islam and the Problem of Israel (1980), dan Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life (1982). Karya-karya ini membahas berbagai topik, termasuk etika, teologi, dialog antaragama, dan integrasi pemikiran Islam ke dalam disiplin akademik kontemporer.
Al-Faruqi adalah akademisi Muslim pertama yang terlibat dalam pendekatan fenomenologi dan sejarah agama. Ia memandang pendekatan ini sebagai kontribusi untuk mengapresiasi Islam sebagai bagian dari sejarah agama manusia dan memungkinkan Muslim terlibat dalam studi agama modern serta berpartisipasi dalam membangun pemahaman antaragama.
Pada tahun 1973, al-Faruqi mendirikan Kelompok Studi Islam di American Academy of Religion (AAR) dan memimpinnya selama sepuluh tahun. Inisiatif ini menyediakan platform formal bagi para cendekiawan Muslim untuk terlibat dalam dialog dengan cendekiawan dari tradisi agama lain, khususnya dalam perbandingan agama dan studi antariman. Selain karya akademiknya, al-Faruqi memegang posisi kepemimpinan seperti wakil presiden Kolokium Perdamaian Antar-Agama dan presiden American Islamic College di Chicago.
Pada Maret 1977, al-Faruqi memainkan peran penting dalam Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Muslim di Makkah. Konferensi ini dihadiri oleh peserta seperti Muhammad Kamal Hassan, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan Syed Ali Ashraf, di antara banyak lainnya. Konferensi ini meletakkan dasar bagi pendirian universitas-universitas Islam di Dhaka, Islamabad, Kuala Lumpur, Kampala, dan Niger. Al-Faruqi berperan penting dalam pembahasan konferensi dan pengembangan rencana tindakannya.
Ia juga menjabat sebagai penasihat bagi para pemimpin politik di dunia Muslim, termasuk Muhammad Zia-ul-Haq di Pakistan dan Mahathir Mohamad di Malaysia. Selama pemerintahan Zia-ul-Haq, al-Faruqi berkontribusi pada pendirian International Islamic University di Islamabad pada tahun 1980, yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin akademik kontemporer. Di Malaysia, al-Faruqi menasihati Perdana Menteri Mahathir Mohamad, membantu pendirian International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 1983. Kedua institusi ini didirikan untuk menggabungkan pengetahuan agama dan sekuler dalam kerangka pendidikan yang holistik.
Pada tahun 1980, Ismail al-Faruqi turut mendirikan International Institute of Islamic Thought (IIIT) bersama Taha Jabir Alalwani, Abdul Hamid AbuSulayman, dan Anwar Ibrahim. Keterlibatannya dalam dialog antaragama mempromosikan pemahaman dan kerja sama bersama di antara komunitas agama, membina lingkungan global yang damai dan saling menghormati yang menyoroti kesamaan antara Islam, Kristen, dan Yudaisme.
6.2. Dampak dan Relevansi Kontemporer
Gagasan al-Faruqi tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan terus bergema dalam pemikiran Islam kontemporer, memengaruhi pengembangan kurikulum di universitas-universitas seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) dan International Islamic University, Islamabad. Penekanannya pada integrasi prinsip-prinsip Islam dengan disiplin akademik modern tetap relevan di kalangan para cendekiawan dan pendidik yang bertujuan untuk menyelaraskan iman dan akal. Karyanya sering dikutip dalam konferensi akademik dan publikasi yang berkaitan dengan pemikiran dan pendidikan Islam.
Kontribusi al-Faruqi terhadap dialog antaragama juga diakui secara luas. Pendekatannya menekankan pencarian titik temu etis dan moral di antara tradisi-tradisi agama, khususnya Islam, Kristen, dan Yudaisme. Para cendekiawan mencatat bahwa fokusnya pada prinsip-prinsip etika di atas perbedaan teologis membina saling pengertian dan rasa hormat di antara komunitas-komunitas agama. Kerangka kerjanya telah berpengaruh dalam upaya global untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama lintas perbedaan agama.
Dampak al-Faruqi melampaui akademisi ke dalam aplikasi praktis. Karyanya dalam studi agama menginspirasi penciptaan program akademik terkait, khususnya di institusi-institusi yang telah mengadopsi metodologinya, seperti mata kuliah studi agama wajib di International Islamic University Malaysia, yang bertujuan untuk memahami tradisi spiritual dan signifikansi peradabannya secara komprehensif.
Selain itu, karya-karya ilmiah al-Faruqi, seperti Christian Ethics dan Trialogue of the Abrahamic Faiths, terus berfungsi sebagai sumber daya kunci dalam dialog antaragama dan studi perbandingan agama. Karya-karya ini telah membentuk diskusi di lingkaran akademik Islam dan Barat, menyoroti persimpangan antara tradisi-tradisi agama ini. Kontribusinya telah diakui secara anumerta, khususnya di komunitas seperti Montreal, di mana kesarjanaan dan upaya pembangunan komunitasnya meninggalkan dampak yang abadi.
6.3. Kritik dan Kontroversi
Meskipun Ismail Raji al-Faruqi dihormati atas kontribusinya, beberapa aspek pemikirannya telah menjadi sasaran kritik. Salah satu kritik utama datang dari cendekiawan seperti Ibrahim Kalin, yang berpendapat bahwa fokus al-Faruqi pada Islamisasi ilmu pengetahuan terutama tertuju pada ilmu humaniora, dan secara signifikan mengabaikan ilmu alam. Kalin mengemukakan bahwa kelalaian ini menciptakan bias sosiologis dalam kerangka pengetahuan Islam yang diusulkan al-Faruqi, berpotensi mengabaikan dampak sekularisasi pandangan dunia ilmiah modern. Akibatnya, menurut Kalin, para cendekiawan Muslim mungkin tidak cukup siap untuk menghadapi tantangan filosofis dan epistemologis yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan kontemporer, dan ini dapat memperkuat dikotomi antara ilmu alam dan ilmu humaniora.
Selain itu, pendekatan al-Faruqi terhadap dialog antaragama juga mendapat kritik. Beberapa sarjana, seperti Damian Howard, berpendapat bahwa meskipun al-Faruqi menganjurkan dialog, pendekatannya cenderung lebih menekankan sudut pandang Islam daripada mempromosikan pemahaman timbal balik yang seimbang di antara berbagai keyakinan. Kritik ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatasi kedalaman dan inklusivitas dialog antariman yang ia maksudkan.
7. Bibliografi
7.1. Buku
Al-Faruqi menulis 25 buku yang mencakup berbagai topik dalam studi Islam, etika, dan perbandingan agama. Berikut adalah beberapa karya utamanya:
7.1.1. Karya Utama
- 'Urubah and Religion: An Analysis of the Dominant Ideas of Arabism and of Islam as Its Highest Moment of ConsciousnessBahasa Inggris (1962)
- Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant IdeasBahasa Inggris (1968)
- The Great Asian ReligionsBahasa Inggris (1969), ditulis bersama W.T. Chan, P.T. Raju, dan J. Kitagawa
- Historical Atlas of the Religions of the WorldBahasa Inggris (1975)
- Islam and the Problem of IsraelBahasa Inggris (1980)
- The Hijrah: The Necessity of Its Iqamat or VergegenwartigungBahasa Inggris (1981)
- Trialogue of the Abrahamic FaithsBahasa Inggris (1982)
- Islamization of Knowledge: General Principles and Work PlanBahasa Inggris (1982)
- Al-Tawhid: Its Implications For Thought And LifeBahasa Inggris (1982)
- The Cultural Atlas of IslamBahasa Inggris (1986)
7.1.2. Karya Terjemahan
Al-Faruqi juga menerjemahkan beberapa karya penting, termasuk:
- From Here We StartBahasa Inggris karya K.M. Khalid (1953)
- Our Beginning in WisdomBahasa Inggris karya M. al Ghazali (1953)
- The Life of MuhammadBahasa Inggris karya Muḥammad Ḥusayn Haykal (1976)
7.2. Artikel Pilihan
Selain buku-buku, al-Faruqi menulis lebih dari 100 artikel ilmiah. Beberapa di antaranya yang menonjol meliputi:
- "On the Ethics of the Brethren of Purity and Friends of Fidelity (Ikhwan al Safa wa Khillan al WafaBahasa Arab)" (serial artikel dalam The Muslim World)
- "Towards a Historiography of Pre-Hijrah Islam" (1962)
- "Towards a New Methodology for Qur'ānic Exegesis" (1962)
- "Islam and Christianity: Diatribe or Dialogue" (1968)
- "The Problem of the Metaphysical Status of Values in the Western and Islamic Traditions" (1968)
- "The Ideal Social Order in the Arab World, 1800-1968" (1969)
- "Islam and Art" (1973)
- "The Muslim-Christian Dialogue: A Constructionist View" (1977)
- "Islamizing the Social Sciences" (1979)
- "Rights of Non-Muslims under Islam: Social and Cultural Aspects" (1979)
- "Islam and the Problem of Israel" (1980)
- "Al Tawhid wa al Fann" (serial artikel dalam Al Muslim al Mu'asir)
- "Islam and the Theory of Nature" (1982)