1. Ikhtisar
Republik Sudan, sebuah negara di Afrika Timur Laut, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang membentang dari peradaban kuno hingga tantangan politik dan kemanusiaan kontemporer. Artikel ini mengulas Sudan dari perspektif kiri-tengah/liberalisme sosial, menekankan pada perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dampak konflik terhadap warga sipil, dan upaya menuju keadilan sosial. Dimulai dari asal-usul namanya yang merujuk pada "Tanah Orang Kulit Hitam", sejarah Sudan menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kush dan Meroë, penyebaran agama Kristen lalu Islam, periode kolonialisme Inggris-Mesir, hingga kemerdekaan pada tahun 1956. Pasca-kemerdekaan, Sudan menghadapi serangkaian perang saudara yang berkepanjangan antara Utara dan Selatan, serta konflik brutal di Darfur, yang mengakibatkan penderitaan manusia yang luas dan intervensi internasional. Pemerintahan otoriter, seperti rezim Jaafar Nimeiry dan Omar al-Bashir, diwarnai oleh pelanggaran HAM berat, penindasan terhadap oposisi, dan penerapan hukum Syariah yang kontroversial. Revolusi Sudan 2019 membawa harapan baru bagi transisi demokrasi, meskipun jalan menuju stabilitas penuh masih terjal dan diwarnai oleh kudeta militer serta perang saudara yang kembali meletus pada tahun 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang memperburuk krisis kemanusiaan. Secara geografis, Sudan didominasi oleh Sungai Nil dan bentang alam gurun serta sabana, menghadapi tantangan lingkungan seperti desertifikasi. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada pertanian dan minyak, namun terhambat oleh sanksi internasional, konflik internal, kemiskinan, dan utang luar negeri. Masyarakat Sudan terdiri dari beragam kelompok etnis dan bahasa, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Isu-isu hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, hak perempuan dan minoritas, serta kondisi di daerah konflik, menjadi perhatian utama. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Sudan memiliki warisan budaya yang kaya, mencakup tradisi, seni, musik, dan situs-situs bersejarah yang diakui dunia.
2. Etimologi
Nama negara Sudan berasal dari nama yang secara historis diberikan untuk wilayah Sahel yang luas di Afrika Barat hingga ke sebelah barat Sudan modern. Secara historis, Sudan merujuk pada kawasan geografis yang membentang dari Senegal di Pantai Atlantik hingga Afrika Timur Laut dan Sudan modern.
Nama ini berasal dari bahasa Arab بلاد السودانbilād as-sūdānBahasa Arab, yang berarti "Tanah Orang Kulit Hitam". Nama ini adalah salah satu dari berbagai toponim yang memiliki etimologi serupa, merujuk pada kulit penduduk asli yang sangat gelap. Sebelum ini, Sudan dikenal sebagai Nubia dan Ta Nehesi atau Ta Seti oleh orang Mesir Kuno, dinamai berdasarkan pemanah Nubia dan Medjay.
Sejak tahun 2011, Sudan juga kadang-kadang disebut sebagai Sudan Utara untuk membedakannya dari Sudan Selatan.
3. Sejarah
Sejarah Sudan mencakup periode yang sangat panjang, mulai dari zaman prasejarah dengan bukti pemukiman manusia purba, berkembangnya kerajaan-kerajaan Nubia kuno yang megah seperti Kerma dan Kush, hingga masuknya agama Kristen dan kemudian Islam yang membentuk kesultanan-kesultanan. Abad ke-19 menyaksikan penaklukan oleh Mesir Ottoman dan munculnya gerakan Mahdist yang menentangnya, yang kemudian diikuti oleh periode kondominium Inggris-Mesir. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan mengalami serangkaian perang saudara, kudeta militer, dan rezim otoriter, termasuk pemerintahan Omar al-Bashir yang panjang dan kontroversial. Pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011 dan revolusi tahun 2019 yang menggulingkan al-Bashir menandai babak baru, namun negara ini terus menghadapi tantangan besar termasuk kudeta militer lebih lanjut dan perang saudara yang meletus pasca-2023, yang berdampak parah pada hak asasi manusia dan stabilitas regional.
3.1. Zaman Prasejarah


Affad 23 adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di wilayah Affad di Dongola Reach selatan di Sudan utara, yang menjadi tempat "sisa-sisa perkemahan prasejarah yang terawat baik (peninggalan pondok terbuka tertua di dunia) dan berbagai lokasi berburu dan pengumpulan hasil hutan yang berusia sekitar 50.000 tahun". Wilayah yang kini menjadi Sudan juga menyaksikan perkembangan industri Khormusan (40.000-16.000 SM), budaya Halfan (20.500-17.000 SM), budaya Sebilian (13.000-10.000 SM), dan budaya Qadan (15.000-5.000 SM). Perang di Jebel Sahaba, yang merupakan perang tertua yang diketahui di dunia, terjadi sekitar 11.500 SM. Kemudian muncul budaya Kelompok A (sekitar 3800-3100 SM).
Pada milenium kedelapan SM, orang-orang dari budaya Neolitikum telah menetap dalam gaya hidup sedenter di desa-desa bata lumpur yang dibentengi, di mana mereka melengkapi kegiatan berburu dan menangkap ikan di Sungai Nil dengan mengumpulkan biji-bijian dan beternak sapi. Masyarakat Neolitikum membuat pekuburan seperti R12. Selama milenium kelima SM, migrasi dari Sahara yang mengering membawa orang-orang Neolitikum ke Lembah Nil bersama dengan pertanian. Populasi yang dihasilkan dari percampuran budaya dan genetik ini mengembangkan hierarki sosial selama abad-abad berikutnya yang menjadi Kerajaan Kerma pada tahun 2500 SM. Penelitian antropologi dan arkeologi menunjukkan bahwa selama periode predinastik, Nubia dan Nagadan Mesir Hulu secara etnis dan budaya hampir identik, dan dengan demikian, secara bersamaan mengembangkan sistem kerajaan firaun pada tahun 3300 SM.
3.2. Kerajaan Nubia Kuno
Wilayah Nubia kuno merupakan tempat berkembangnya beberapa kerajaan penting yang memiliki peradaban maju. Di antara yang paling menonjol adalah Peradaban Kerma, yang menunjukkan tingkat organisasi sosial dan keahlian arsitektur yang tinggi. Wilayah ini juga mengalami periode kekuasaan Mesir, di mana budaya dan politik Mesir memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian, Kerajaan Kush bangkit sebagai kekuatan regional yang dominan, dengan pusat-pusat penting di Napata dan Meroë, yang terkenal dengan kekayaan, perdagangan, dan piramida-piramida uniknya. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah regional, berinteraksi secara intens dengan Mesir dan peradaban lainnya di Lembah Nil.
3.2.1. Peradaban Kerma

Peradaban Kerma adalah sebuah peradaban awal yang berpusat di Kerma, Sudan. Peradaban ini berkembang dari sekitar 2500 SM hingga 1500 SM di Nubia kuno. Kebudayaan Kerma berpusat di bagian selatan Nubia, atau "Nubia Hulu" (di beberapa bagian Sudan utara dan tengah saat ini), dan kemudian memperluas jangkauannya ke utara hingga Nubia Hilir dan perbatasan Mesir. Entitas politik ini tampaknya merupakan salah satu dari beberapa negara Lembah Nil selama Kerajaan Pertengahan Mesir. Pada fase terakhir Kerajaan Kerma, yang berlangsung dari sekitar 1700-1500 SM, kerajaan ini menyerap kerajaan Sudan Saï dan menjadi sebuah kekaisaran yang cukup besar dan padat penduduk yang menyaingi Mesir.
3.2.2. Kekuasaan Mesir di Nubia

Mentuhotep II, pendiri Kerajaan Pertengahan pada abad ke-21 SM, tercatat telah melakukan kampanye melawan Kush pada tahun ke-29 dan ke-31 pemerintahannya. Ini adalah referensi Mesir paling awal untuk Kush; wilayah Nubia telah menggunakan nama lain di Kerajaan Lama. Di bawah Thutmose I, Mesir melakukan beberapa kampanye ke selatan.
Orang Mesir memerintah Kush di Kerajaan Baru dimulai ketika Raja Mesir Thutmose I menduduki Kush dan menghancurkan ibu kotanya, Kerma. Ini akhirnya mengakibatkan aneksasi Nubia sekitar tahun 1504 SM. Sekitar tahun 1500 SM, Nubia diserap ke dalam Kerajaan Baru Mesir, tetapi pemberontakan terus berlanjut selama berabad-abad. Setelah penaklukan, budaya Kerma semakin di-Mesir-kan, namun pemberontakan berlanjut selama 220 tahun hingga sekitar tahun 1300 SM. Meskipun demikian, Nubia menjadi provinsi kunci Kerajaan Baru, secara ekonomi, politik, dan spiritual. Memang, upacara-upacara penting firaun diadakan di Jebel Barkal dekat Napata. Sebagai koloni Mesir sejak abad ke-16 SM, Nubia ("Kush") diperintah oleh seorang Raja Muda Mesir untuk Kush.
Perlawanan terhadap pemerintahan Dinasti ke-18 Mesir awal oleh Kush yang bertetangga dibuktikan dalam tulisan-tulisan Ahmose, putra Ebana, seorang prajurit Mesir yang bertugas di bawah Nebpehtrya Ahmose (1539-1514 SM), Djeserkara Amenhotep I (1514-1493 SM), dan Aakheperkara Thutmose I (1493-1481 SM). Pada akhir Periode Menengah Kedua (pertengahan abad ke-16 SM), Mesir menghadapi ancaman eksistensial ganda-Hyksos di Utara dan orang Kush di Selatan. Diambil dari prasasti otobiografi di dinding kapel makamnya, orang Mesir melakukan kampanye untuk mengalahkan Kush dan menaklukkan Nubia di bawah pemerintahan Amenhotep I (1514-1493 SM). Dalam tulisan-tulisan Ahmose, orang Kush digambarkan sebagai pemanah, "Sekarang setelah Baginda membunuh orang Bedoin Asia, ia berlayar ke hulu menuju Nubia Hulu untuk menghancurkan para pemanah Nubia." Tulisan makam tersebut berisi dua referensi lain tentang pemanah Nubia dari Kush. Pada tahun 1200 SM, keterlibatan Mesir di Dongola Reach sudah tidak ada lagi.
Prestise internasional Mesir telah menurun drastis menjelang akhir Periode Menengah Ketiga. Sekutu historisnya, penduduk Kanaan, telah jatuh ke tangan Kekaisaran Asiria Pertengahan (1365-1020 SM), dan kemudian Kekaisaran Asiria Baru yang bangkit kembali (935-605 SM). Orang Asiria, sejak abad ke-10 SM dan seterusnya, sekali lagi berekspansi dari Mesopotamia utara, dan menaklukkan kekaisaran yang luas, termasuk seluruh Timur Dekat, dan sebagian besar Anatolia, Mediterania timur, Kaukasus dan Iran Zaman Besi awal.
Menurut Yosefus Flavius, Musa dalam Alkitab memimpin pasukan Mesir dalam pengepungan kota Kush, Meroe. Untuk mengakhiri pengepungan, Putri Tharbis diberikan kepada Musa sebagai pengantin (diplomatik), dan dengan demikian pasukan Mesir mundur kembali ke Mesir.
3.2.3. Kerajaan Kush


Kerajaan Kush adalah negara Nubia kuno yang berpusat pada pertemuan Nil Biru dan Nil Putih, serta Sungai Atbarah dan Sungai Nil. Kerajaan ini didirikan setelah keruntuhan Zaman Perunggu Akhir dan disintegrasi Kerajaan Baru Mesir; berpusat di Napata pada fase awalnya.
Setelah Raja Kashta ("orang Kush") menginvasi Mesir pada abad kedelapan SM, raja-raja Kush memerintah sebagai firaun Dinasti Kedua Puluh Lima Mesir selama hampir satu abad sebelum dikalahkan dan diusir oleh bangsa Asiria. Pada puncak kejayaan mereka, bangsa Kush menaklukkan sebuah kekaisaran yang membentang dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kurdufan Selatan hingga Sinai. Firaun Piye berusaha memperluas kekaisaran ke Timur Dekat tetapi digagalkan oleh raja Asiria Sargon II.
Antara 800 SM dan 100 M, piramida Nubia dibangun, di antaranya dapat disebutkan El-Kurru, Kashta, Piye, Tantamani, Shabaka, Piramida Gebel Barkal, Piramida Meroë (Begarawiyah), piramida Sedeinga, dan Piramida Nuri.
Kerajaan Kush disebutkan dalam Alkitab telah menyelamatkan bangsa Israel dari murka bangsa Asiria, meskipun penyakit di antara para pengepung mungkin menjadi salah satu alasan kegagalan merebut kota tersebut.
Perang yang terjadi antara Firaun Taharqa dan raja Asiria Sennacherib merupakan peristiwa penting dalam sejarah barat, di mana bangsa Nubia dikalahkan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pijakan di Timur Dekat oleh Asiria. Penerus Sennacherib, Esarhaddon, melangkah lebih jauh dan menginvasi Mesir sendiri untuk mengamankan kendalinya atas Levant. Ini berhasil, karena ia berhasil mengusir Taharqa dari Mesir Hilir. Taharqa melarikan diri kembali ke Mesir Hulu dan Nubia, di mana ia meninggal dua tahun kemudian. Mesir Hilir berada di bawah vasalisasi Asiria tetapi terbukti sulit diatur, memberontak tanpa hasil melawan bangsa Asiria. Kemudian, raja Tantamani, penerus Taharqa, melakukan upaya terakhir yang gigih untuk merebut kembali Mesir Hilir dari vasal Asiria yang baru dipulihkan, Necho I. Ia berhasil merebut kembali Memphis, membunuh Necho dalam proses tersebut, dan mengepung kota-kota di Delta Nil. Ashurbanipal, yang telah menggantikan Esarhaddon, mengirim pasukan besar ke Mesir untuk mendapatkan kembali kendali. Ia mengalahkan Tantamani di dekat Memphis dan, mengejarnya, menjarah Thebes. Meskipun bangsa Asiria segera meninggalkan Mesir Hulu setelah peristiwa ini, Thebes yang melemah dengan damai menyerah kepada putra Necho, Psamtik I, kurang dari satu dekade kemudian. Ini mengakhiri semua harapan akan kebangkitan Kekaisaran Nubia, yang lebih tepatnya berlanjut dalam bentuk kerajaan yang lebih kecil yang berpusat di Napata. Kota itu diserbu oleh Mesir pada 590 SM, dan segera setelah itu hingga akhir abad ke-3 SM, bangsa Kush bermukim kembali di Meroë.
3.3. Kerajaan-Kerajaan Kristen Nubia Abad Pertengahan

Pada pergantian abad kelima, bangsa Blemmyes mendirikan negara berumur pendek di Mesir Hulu dan Nubia Hilir, mungkin berpusat di sekitar Talmis (Kalabsha), tetapi sebelum tahun 450 mereka sudah diusir dari Lembah Nil oleh bangsa Nobatia. Bangsa Nobatia akhirnya mendirikan kerajaan sendiri, Nobatia.
Pada abad keenam, secara keseluruhan terdapat tiga kerajaan Nubia: Nobatia di utara, yang beribu kota di Pachoras (Faras); kerajaan pusat, Makuria yang berpusat di Tungul (Dongola Tua), sekitar 13 km selatan Dongola modern; dan Alodia, di jantung kerajaan Kush kuno, yang beribu kota di Soba (sekarang pinggiran kota Khartoum modern). Masih di abad keenam mereka memeluk agama Kristen. Pada abad ketujuh, mungkin antara tahun 628 dan 642, Nobatia digabungkan ke dalam Makuria.
Antara tahun 639 dan 641, orang Arab Muslim dari Kekhalifahan Rasyidin menaklukkan Mesir Bizantium. Pada tahun 641 atau 642 dan lagi pada 652 mereka menyerbu Nubia tetapi berhasil dipukul mundur, menjadikan orang Nubia salah satu dari sedikit yang berhasil mengalahkan orang Arab selama ekspansi Islam. Setelah itu, raja Makuria dan orang Arab menyetujui pakta non-agresi yang unik yang juga mencakup pertukaran hadiah tahunan, sehingga mengakui kemerdekaan Makuria. Meskipun orang Arab gagal menaklukkan Nubia, mereka mulai menetap di sebelah timur Sungai Nil, di mana mereka akhirnya mendirikan beberapa kota pelabuhan dan menikah dengan penduduk lokal Beja.

Dari pertengahan abad kedelapan hingga pertengahan abad kesebelas, kekuatan politik dan perkembangan budaya Kristen Nubia mencapai puncaknya. Pada tahun 747, Makuria menginvasi Mesir, yang pada saat itu merupakan bagian dari Umayyah yang sedang menurun, dan melakukannya lagi pada awal tahun 960-an, ketika Makuria berhasil merangsek hingga sejauh utara Akhmim. Makuria mempertahankan hubungan dinasti yang erat dengan Alodia, yang mungkin menghasilkan penyatuan sementara kedua kerajaan menjadi satu negara. Budaya orang Nubia abad pertengahan telah digambarkan sebagai "Afro-Bizantium", tetapi juga semakin dipengaruhi oleh budaya Arab. Organisasi negara sangat terpusat, didasarkan pada birokrasi Bizantium abad keenam dan ketujuh. Seni berkembang dalam bentuk lukisan tembikar dan terutama lukisan dinding. Orang Nubia mengembangkan alfabet untuk bahasa mereka, Nobiin Kuno, mendasarkannya pada alfabet Koptik, sementara juga menggunakan Yunani, Koptik, dan Arab. Wanita menikmati status sosial yang tinggi: mereka memiliki akses ke pendidikan, dapat memiliki, membeli dan menjual tanah, dan sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai gereja dan lukisan gereja. Bahkan suksesi kerajaan bersifat matrilineal, dengan putra dari saudara perempuan raja menjadi pewaris yang sah.
Dari akhir abad ke-11/ke-12, ibu kota Makuria, Dongola, mengalami kemunduran, dan ibu kota Alodia juga mengalami kemunduran pada abad ke-12. Pada abad ke-14 dan ke-15, suku-suku Bedouin menyerbu sebagian besar Sudan, bermigrasi ke Butana, Gezira, Kordofan, dan Darfur. Pada tahun 1365, perang saudara memaksa istana Makuria melarikan diri ke Gebel Adda di Nubia Hilir, sementara Dongola dihancurkan dan diserahkan kepada orang Arab. Setelah itu, Makuria hanya berlanjut sebagai kerajaan kecil. Setelah pemerintahan yang makmur dari raja Joel (1463-1484), Makuria runtuh. Wilayah pesisir dari Sudan selatan hingga kota pelabuhan Suakin digantikan oleh Kesultanan Adal pada abad kelima belas. Di selatan, kerajaan Alodia jatuh ke tangan orang Arab, yang dipimpin oleh pemimpin suku Abdallah Jamma, atau Funj, orang Afrika yang berasal dari selatan. Penanggalan berkisar dari abad ke-9 setelah Hijrah (1396-1494), akhir abad ke-15, 1504, hingga 1509. Sebuah negara sisa Alodia mungkin bertahan dalam bentuk kerajaan Fazughli, yang berlangsung hingga tahun 1685.
3.4. Islamisasi dan Era Kesultanan
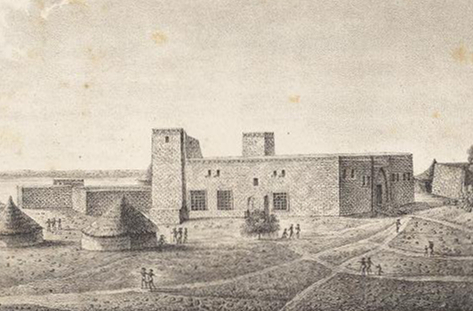
Pada tahun 1504, Funj tercatat telah mendirikan Kerajaan Sennar, di mana kerajaan Abdallah Jamma digabungkan. Pada tahun 1523, ketika penjelajah Yahudi David Reubeni mengunjungi Sudan, negara Funj telah meluas hingga sejauh utara Dongola. Sementara itu, Islam mulai disebarkan di tepi Sungai Nil oleh para suci Sufi yang menetap di sana pada abad ke-15 dan ke-16, dan pada kunjungan David Reubeni, raja Amara Dunqas, yang sebelumnya seorang Pagan atau Kristen nominal, tercatat sebagai Muslim. Namun, Funj akan mempertahankan adat istiadat non-Islam seperti kerajaan ilahi atau konsumsi alkohol hingga abad ke-18. Islam rakyat Sudan mempertahankan banyak ritual yang berasal dari tradisi Kristen hingga masa lalu.
Segera Funj berkonflik dengan Ottoman, yang telah menduduki Suakin sekitar tahun 1526 dan akhirnya bergerak ke selatan di sepanjang Sungai Nil, mencapai daerah katarak Nil ketiga pada tahun 1583/1584. Upaya Ottoman berikutnya untuk merebut Dongola berhasil dipukul mundur oleh Funj pada tahun 1585. Setelah itu, Hannik, yang terletak tepat di sebelah selatan katarak ketiga, akan menandai perbatasan antara kedua negara. Akibat invasi Ottoman adalah upaya perampasan kekuasaan oleh Ajib, seorang raja kecil Nubia utara. Meskipun Funj akhirnya membunuhnya pada tahun 1611/1612, para penerusnya, Abdallab, diberikan hak untuk memerintah semua wilayah di utara pertemuan Nil Biru dan Putih dengan otonomi yang cukup besar.
Selama abad ke-17, negara Funj mencapai jangkauan terluasnya, tetapi pada abad berikutnya mulai mengalami kemunduran. Sebuah kudeta pada tahun 1718 membawa perubahan dinasti, sementara kudeta lainnya pada tahun 1761-1762 menghasilkan Hamaj Regency, di mana Hamaj (orang-orang dari perbatasan Ethiopia) secara efektif memerintah sementara sultan Funj hanyalah boneka mereka. Tak lama setelah itu, kesultanan mulai terfragmentasi; pada awal abad ke-19, kesultanan pada dasarnya terbatas pada Gezira.

Kudeta tahun 1718 memulai kebijakan untuk menerapkan Islam yang lebih ortodoks, yang pada gilirannya mempromosikan Arabisasi negara. Untuk melegitimasi kekuasaan mereka atas rakyat Arab, Funj mulai menyebarkan keturunan Umayyah. Di sebelah utara pertemuan Nil Biru dan Putih, hingga sejauh hilir Al Dabbah, orang Nubia mengadopsi identitas kesukuan Arab Jaalin. Hingga abad ke-19, bahasa Arab berhasil menjadi bahasa dominan di Sudan tengah di tepi sungai dan sebagian besar Kordofan.
Di sebelah barat Sungai Nil, di Darfur, periode Islam pada awalnya menyaksikan kebangkitan kerajaan Tunjur, yang menggantikan kerajaan Daju kuno pada abad ke-15 dan meluas hingga sejauh barat Wadai. Orang Tunjur kemungkinan adalah Berber yang terarabkan dan, setidaknya elite penguasa mereka, adalah Muslim. Pada abad ke-17, Tunjur digulingkan dari kekuasaan oleh Fur kesultanan Keira. Negara Keira, yang secara nominal Muslim sejak pemerintahan Sulayman Solong (memerintah 1660-1680), pada awalnya adalah kerajaan kecil di Jebel Marra utara, tetapi meluas ke barat dan utara pada awal abad ke-18 dan ke timur di bawah pemerintahan Muhammad Tayrab (memerintah 1751-1786), mencapai puncaknya dengan penaklukan Kordofan pada tahun 1785. Puncak kejayaan kekaisaran ini, yang sekarang kira-kira seukuran Nigeria saat ini, akan berlangsung hingga tahun 1821.
3.5. Pemerintahan Ottoman-Mesir dan Gerakan Mahdist
Periode ini ditandai oleh penaklukan dan pemerintahan Sudan oleh Mesir di bawah Dinasti Muhammad Ali, yang dikenal sebagai era Turkiyah. Pemerintahan ini membawa perubahan signifikan namun juga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Sebagai reaksi, muncul Gerakan Mahdist yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad, yang berhasil mendirikan Negara Mahdist. Negara ini berupaya menerapkan hukum Islam dan menentang kekuasaan asing, namun akhirnya dihancurkan oleh pasukan gabungan Inggris-Mesir, membuka jalan bagi periode baru dalam sejarah Sudan.
3.5.1. Era Turkiyah
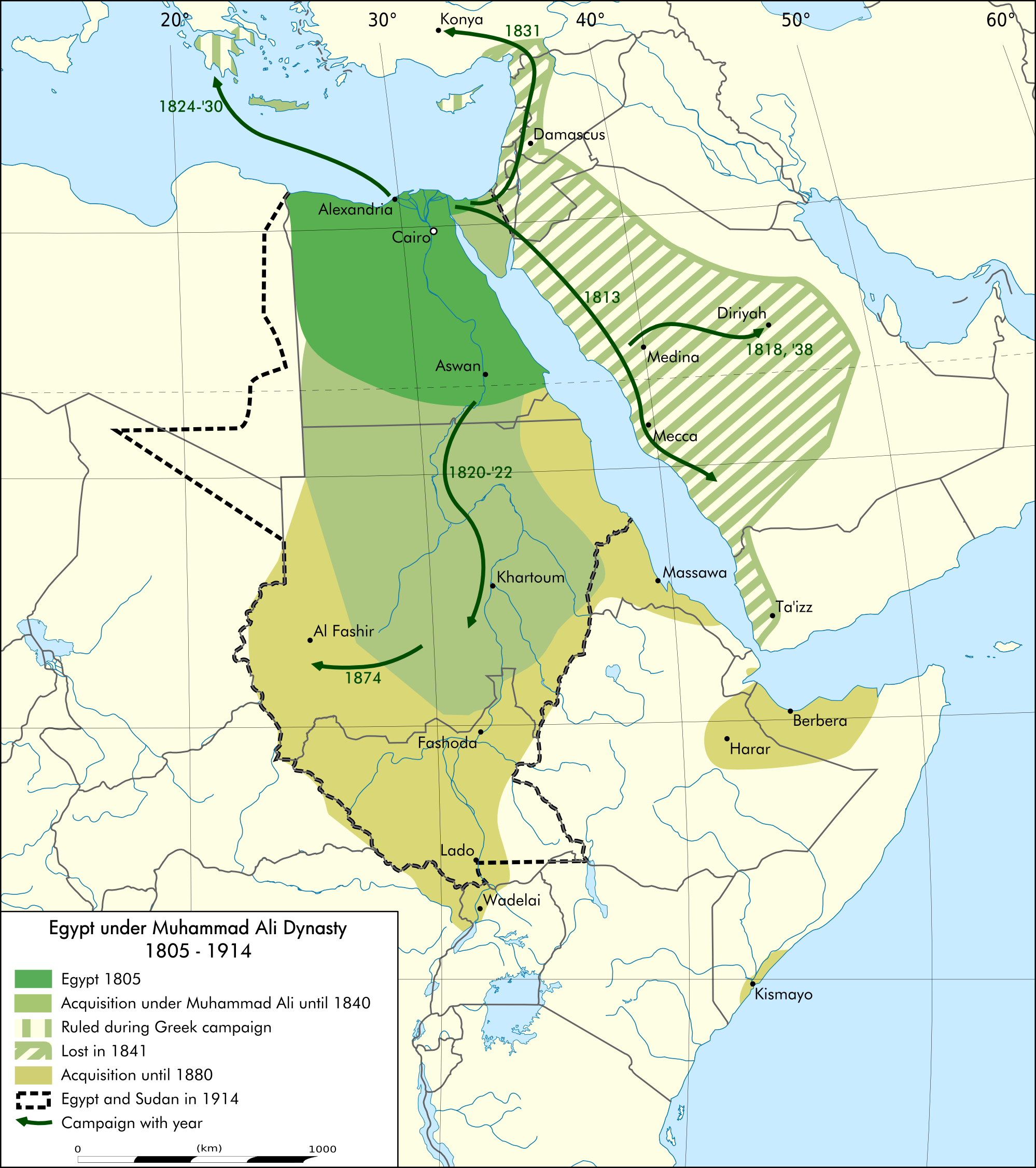
Pada tahun 1821, penguasa Ottoman di Mesir, Muhammad Ali dari Mesir, menyerbu dan menaklukkan Sudan utara. Meskipun secara teknis Wali Mesir di bawah Kekaisaran Ottoman, Muhammad Ali menata dirinya sebagai Khedive dari Mesir yang hampir merdeka. Berusaha untuk menambahkan Sudan ke dalam wilayah kekuasaannya, ia mengirim putra ketiganya Ismail (jangan dikelirukan dengan Ismaʻil Pasha yang disebutkan kemudian) untuk menaklukkan negara itu, dan kemudian menggabungkannya ke dalam Mesir. Kecuali Shaiqiya dan kesultanan Darfur di Kordofan, ia tidak mendapat perlawanan. Kebijakan penaklukan Mesir diperluas dan diintensifkan oleh putra Ibrahim Pasha, Ismaʻil, di bawah pemerintahannya sebagian besar sisa Sudan modern ditaklukkan.
Pihak berwenang Mesir melakukan perbaikan signifikan pada infrastruktur Sudan (terutama di utara), khususnya terkait irigasi dan produksi kapas. Pada tahun 1879, Kekuatan Besar memaksa pemecatan Ismail dan mengangkat putranya Tewfik Pasha sebagai penggantinya. Korupsi dan salah urus Tewfik mengakibatkan pemberontakan 'Urabi, yang mengancam kelangsungan hidup Khedive. Tewfik meminta bantuan Inggris, yang kemudian menduduki Mesir pada tahun 1882. Sudan diserahkan kepada pemerintahan Khedive, dan salah urus serta korupsi para pejabatnya.
3.5.2. Negara Mahdist

Selama periode Khedive, perbedaan pendapat menyebar karena pajak yang berat dikenakan pada sebagian besar kegiatan. Pajak atas sumur irigasi dan lahan pertanian begitu tinggi sehingga sebagian besar petani meninggalkan pertanian dan ternak mereka. Selama tahun 1870-an, inisiatif Eropa terhadap perdagangan budak berdampak buruk pada ekonomi Sudan utara, memicu kebangkitan pasukan Mahdist. Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, sang Mahdi (Yang Terpimpin), menawarkan kepada para ansar (pengikutnya) dan mereka yang menyerah kepadanya pilihan antara memeluk Islam atau dibunuh. Mahdiyah (rezim Mahdist) memberlakukan hukum Islam Syariah tradisional. Pada tanggal 12 Agustus 1881, sebuah insiden terjadi di Pulau Aba, memicu pecahnya apa yang kemudian menjadi Perang Mahdist.
Sejak pengumuman Mahdiyya pada bulan Juni 1881 hingga jatuhnya Khartoum pada bulan Januari 1885, Muhammad Ahmad memimpin kampanye militer yang sukses melawan pemerintahan Turco-Mesir di Sudan, yang dikenal sebagai Turkiyah. Muhammad Ahmad meninggal pada tanggal 22 Juni 1885, hanya enam bulan setelah penaklukan Khartoum. Setelah perebutan kekuasaan di antara para wakilnya, Abdallahi ibn Muhammad, dengan bantuan utama dari Baggara Sudan barat, mengatasi perlawanan yang lain dan muncul sebagai pemimpin Mahdiyah yang tak tertandingi. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya, Abdallahi ibn Muhammad mengambil gelar Khalifa (penerus) Mahdi, membentuk pemerintahan, dan menunjuk Ansar (yang biasanya Baggara) sebagai emir di setiap provinsi.

Hubungan regional tetap tegang selama sebagian besar periode Mahdiyah, sebagian besar karena metode brutal Khalifa untuk memperluas kekuasaannya di seluruh negeri. Pada tahun 1887, pasukan Ansar berkekuatan 60.000 orang menyerbu Etiopia, merangsek hingga sejauh Gondar. Pada bulan Maret 1889, raja Yohannes IV dari Etiopia berbaris menuju Metemma; namun, setelah Yohannes gugur dalam pertempuran, pasukan Etiopia mundur. Abd ar-Rahman an-Nujumi, jenderal Khalifa, mencoba invasi ke Mesir pada tahun 1889, tetapi pasukan Mesir yang dipimpin Inggris mengalahkan Ansar di Tushkah. Kegagalan invasi Mesir mematahkan pesona tak terkalahkan Ansar. Belgia mencegah orang-orang Mahdi menaklukkan Equatoria, dan pada tahun 1893, Italia berhasil memukul mundur serangan Ansar di Agordat (di Eritrea) dan memaksa Ansar mundur dari Etiopia.
Pada tahun 1890-an, Inggris berusaha untuk membangun kembali kendali mereka atas Sudan, sekali lagi secara resmi atas nama Khedive Mesir, tetapi dalam kenyataannya memperlakukan negara itu sebagai koloni Inggris. Pada awal tahun 1890-an, klaim Inggris, Prancis, dan Belgia telah bertemu di hulu Nil. Inggris khawatir bahwa kekuatan lain akan memanfaatkan ketidakstabilan Sudan untuk memperoleh wilayah yang sebelumnya dianeksasi ke Mesir. Selain pertimbangan politik ini, Inggris ingin membangun kendali atas Sungai Nil untuk menjaga bendungan irigasi yang direncanakan di Aswan. Herbert Kitchener memimpin kampanye militer melawan Mahdist Sudan dari tahun 1896 hingga 1898. Kampanye Kitchener memuncak dalam kemenangan telak dalam Pertempuran Omdurman pada tanggal 2 September 1898. Setahun kemudian, Pertempuran Umm Diwaykarat pada tanggal 25 November 1899 mengakibatkan kematian Abdallahi ibn Muhammad, yang kemudian mengakhiri Perang Mahdist.
3.6. Kondominium Inggris-Mesir
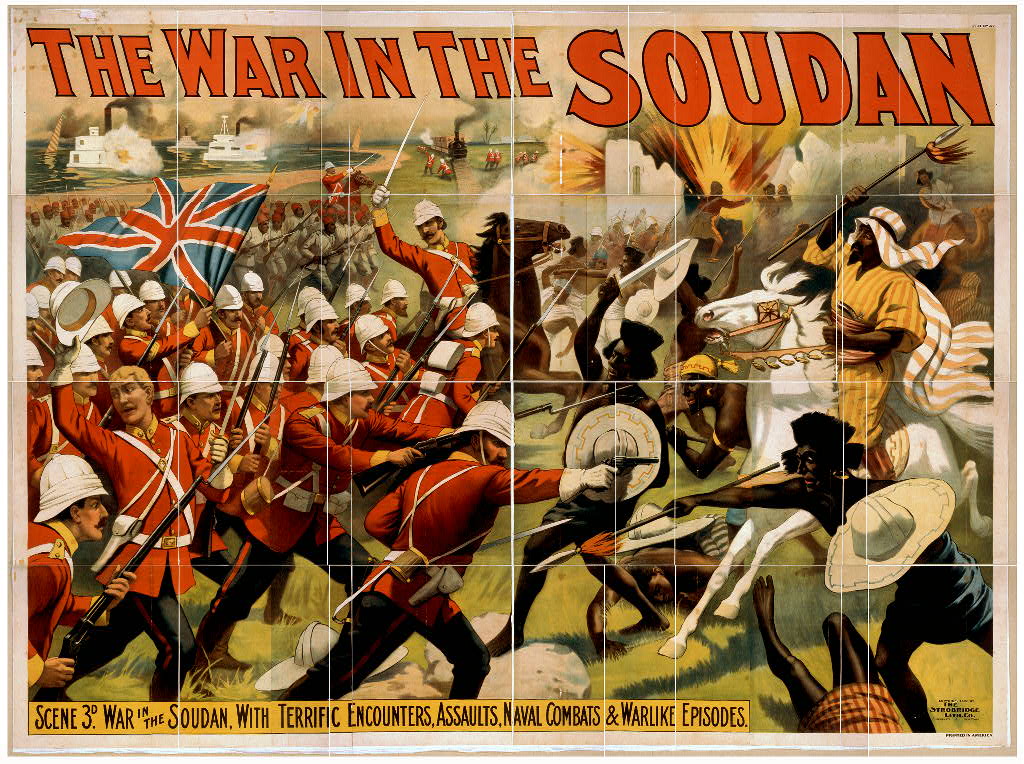
Pada tahun 1899, Inggris dan Mesir mencapai kesepakatan di mana Sudan dijalankan oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Mesir dengan persetujuan Inggris. Pada kenyataannya, Sudan secara efektif dikelola sebagai Koloni Mahkota. Inggris bersemangat untuk membalikkan proses, yang dimulai di bawah Muhammad Ali Pasha, untuk menyatukan Lembah Nil di bawah kepemimpinan Mesir dan berusaha untuk menggagalkan semua upaya yang bertujuan untuk lebih menyatukan kedua negara.
Di bawah Delimitasi, perbatasan Sudan dengan Abyssinia diperebutkan oleh suku-suku perampok yang memperdagangkan budak, melanggar batas-batas hukum. Pada tahun 1905, kepala suku lokal Sultan Yambio, yang enggan hingga akhir, menyerah dalam perjuangan dengan pasukan Inggris yang telah menduduki wilayah Kordofan, akhirnya mengakhiri pelanggaran hukum. Ordonansi yang diterbitkan oleh Inggris memberlakukan sistem perpajakan. Ini mengikuti preseden yang ditetapkan oleh Khalifa. Pajak utama diakui. Pajak-pajak ini dikenakan pada tanah, ternak, dan pohon kurma. Administrasi Inggris yang berkelanjutan atas Sudan memicu reaksi nasionalis yang semakin keras, dengan para pemimpin nasionalis Mesir bertekad untuk memaksa Inggris mengakui persatuan independen tunggal Mesir dan Sudan. Dengan berakhirnya secara formal pemerintahan Ottoman pada tahun 1914, Sir Reginald Wingate dikirim pada bulan Desember itu untuk menduduki Sudan sebagai Gubernur Militer yang baru. Hussein Kamel dinyatakan sebagai Sultan Mesir dan Sudan, begitu pula saudaranya dan penggantinya, Fuad I. Mereka terus bersikeras pada satu negara Mesir-Sudan bahkan ketika Kesultanan Mesir berganti nama menjadi Kerajaan Mesir dan Sudan, tetapi Saad Zaghloul-lah yang terus frustrasi dalam ambisinya hingga kematiannya pada tahun 1927.
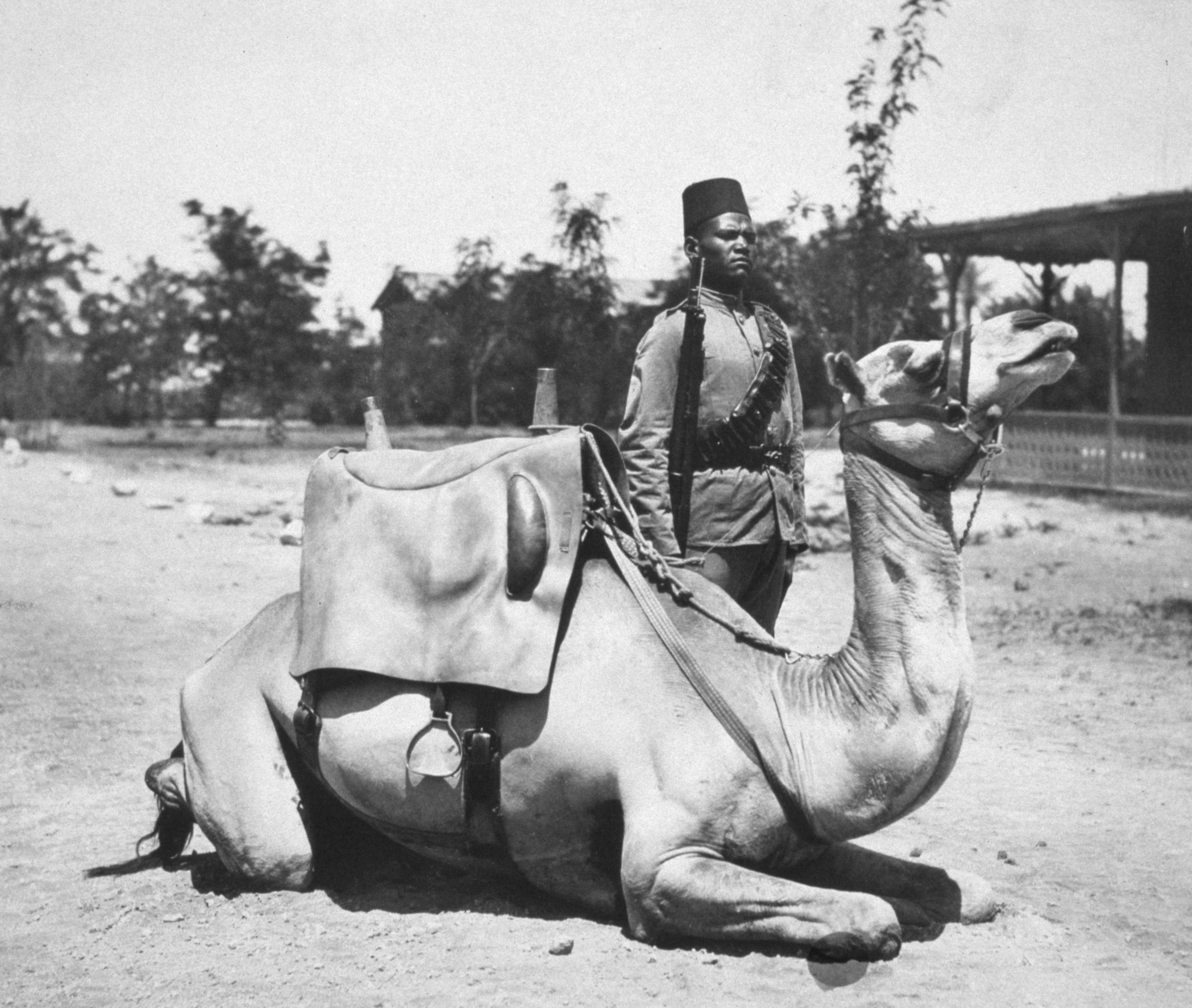
Dari tahun 1924 hingga kemerdekaan pada tahun 1956, Inggris memiliki kebijakan menjalankan Sudan sebagai dua wilayah yang pada dasarnya terpisah; utara dan selatan. Pembunuhan seorang Gubernur Jenderal Sudan Anglo-Mesir di Kairo adalah faktor penyebabnya; hal itu membawa tuntutan dari pemerintah Wafd yang baru terpilih dari pasukan kolonial. Sebuah pendirian permanen dua batalion di Khartoum diubah namanya menjadi Pasukan Pertahanan Sudan yang bertindak di bawah pemerintah, menggantikan garnisun tentara Mesir sebelumnya, kemudian beraksi selama Insiden Walwal. Mayoritas parlemen Wafdist telah menolak rencana akomodasi Sarwat Pasha dengan Austen Chamberlain di London; namun Kairo masih membutuhkan uang. Pendapatan Pemerintah Sudan telah mencapai puncaknya pada tahun 1928 sebesar £6,6 juta, setelah itu gangguan Wafdist, dan serbuan perbatasan Italia dari Somaliland, London memutuskan untuk mengurangi pengeluaran selama Depresi Hebat. Ekspor kapas dan getah dikalahkan oleh kebutuhan untuk mengimpor hampir semuanya dari Inggris yang menyebabkan defisit neraca pembayaran di Khartoum.
Pada bulan Juli 1936, pemimpin Konstitusional Liberal, Muhammed Mahmoud dibujuk untuk membawa delegasi Wafd ke London untuk menandatangani Perjanjian Anglo-Mesir, "awal dari tahap baru dalam hubungan Anglo-Mesir", tulis Anthony Eden. Tentara Inggris diizinkan untuk kembali ke Sudan untuk melindungi Zona Terusan. Mereka dapat menemukan fasilitas pelatihan, dan RAF bebas terbang di atas wilayah Mesir. Namun, hal itu tidak menyelesaikan masalah Sudan: Kaum Intelektual Sudan beragitasi untuk kembali ke pemerintahan metropolitan, bersekongkol dengan agen-agen Jerman.
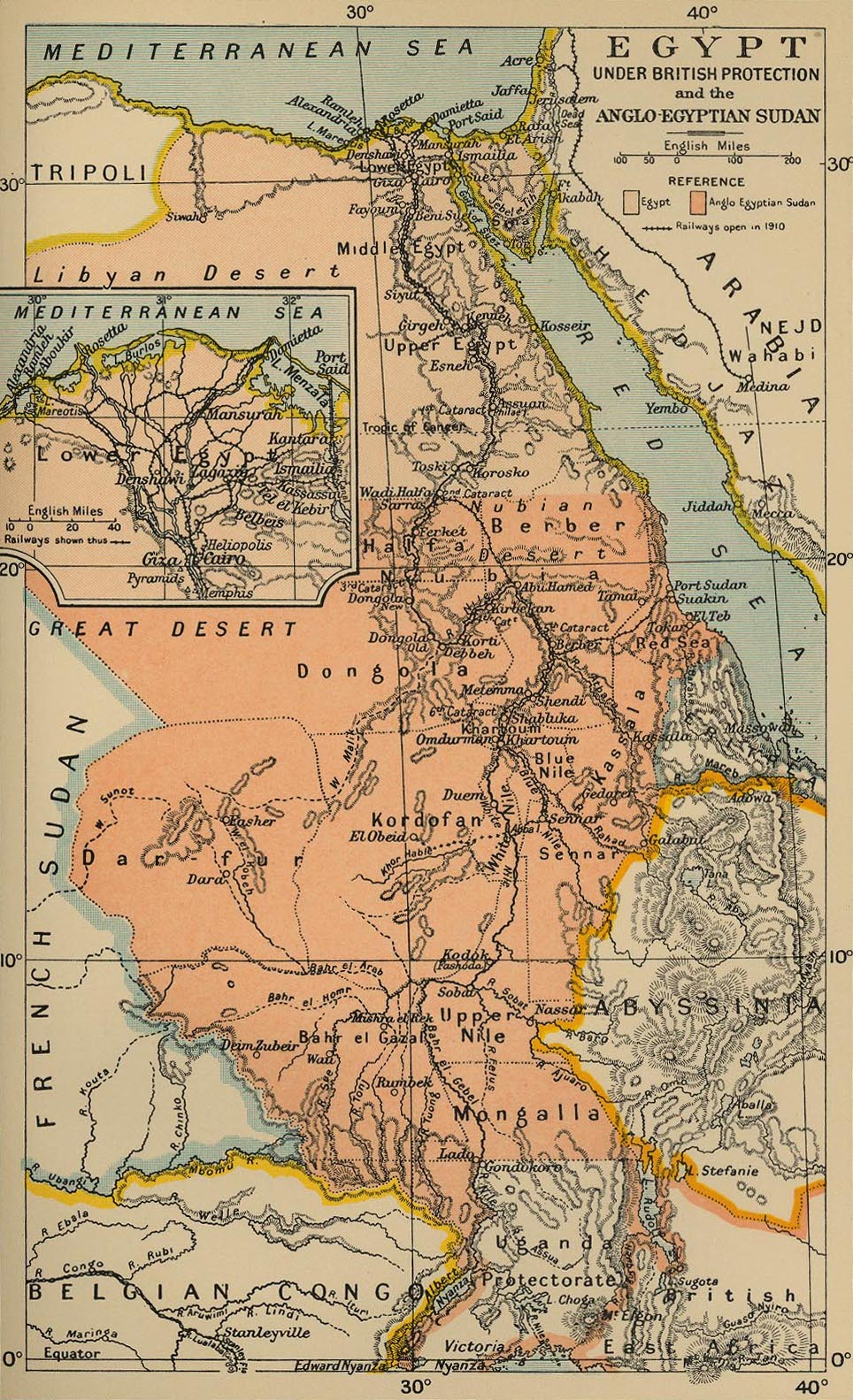
Pemimpin fasis Italia Benito Mussolini menjelaskan bahwa ia tidak dapat menyerbu Abyssinia tanpa terlebih dahulu menaklukkan Mesir dan Sudan; mereka bermaksud menyatukan Libya Italia dengan Afrika Timur Italia. Staf Umum Kekaisaran Inggris mempersiapkan pertahanan militer di wilayah tersebut, yang pasukannya tipis. Duta Besar Inggris memblokir upaya Italia untuk mendapatkan Perjanjian Non-Agresi dengan Mesir-Sudan. Tetapi Mahmoud adalah pendukung Mufti Agung Yerusalem; wilayah tersebut terjebak antara upaya Kekaisaran untuk menyelamatkan orang Yahudi, dan seruan Arab moderat untuk menghentikan migrasi.
Pemerintah Sudan terlibat secara langsung secara militer dalam Kampanye Afrika Timur. Dibentuk pada tahun 1925, Pasukan Pertahanan Sudan memainkan peran aktif dalam menanggapi serbuan pada awal Perang Dunia II. Pasukan Italia menduduki Kassala dan daerah perbatasan lainnya dari Somaliland Italia selama tahun 1940. Pada tahun 1942, SDF juga berperan dalam invasi ke koloni Italia oleh pasukan Inggris dan Persemakmuran. Gubernur jenderal Inggris terakhir adalah Robert George Howe.
Revolusi Mesir 1952 akhirnya menandai dimulainya perjalanan menuju kemerdekaan Sudan. Setelah menghapuskan monarki pada tahun 1953, para pemimpin baru Mesir, Mohammed Naguib, yang ibunya adalah orang Sudan, dan kemudian Gamal Abdel Nasser, percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri dominasi Inggris di Sudan adalah Mesir secara resmi meninggalkan klaim kedaulatannya. Selain itu, Nasser tahu akan sulit bagi Mesir untuk memerintah Sudan yang miskin setelah kemerdekaannya. Sebaliknya, Inggris melanjutkan dukungan politik dan keuangannya untuk penerus Mahdist, Abd al-Rahman al-Mahdi, yang diyakini akan menentang tekanan Mesir untuk kemerdekaan Sudan. Abd al-Rahman mampu melakukan ini, tetapi rezimnya dilanda ketidakmampuan politik, yang menuai kerugian besar dukungan di Sudan utara dan tengah. Baik Mesir maupun Inggris merasakan ketidakstabilan besar yang sedang terjadi, dan karena itu memilih untuk mengizinkan kedua wilayah Sudan, utara dan selatan untuk memberikan suara bebas apakah mereka menginginkan kemerdekaan atau penarikan Inggris.
3.7. Pasca Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, negara ini mengalami periode ketidakstabilan politik yang ditandai oleh perang saudara, kudeta militer, dan perubahan rezim. Perang Saudara Sudan Pertama meletus segera setelah kemerdekaan, menyoroti perpecahan mendalam antara Utara dan Selatan. Rezim Jaafar Nimeiry membawa periode pemerintahan otoriter dan penerapan awal hukum Syariah. Perang Saudara Sudan Kedua yang lebih lama dan lebih merusak dipicu oleh kebijakan Islamisasi lebih lanjut dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah. Rezim Omar al-Bashir yang berkuasa lama menyaksikan konflik Darfur yang brutal, yang menyebabkan tuduhan genosida dan tuntutan dari Pengadilan Kriminal Internasional. Pemisahan diri Sudan Selatan pada tahun 2011 adalah tonggak sejarah, tetapi tidak mengakhiri tantangan internal Sudan. Revolusi Sudan 2019 menggulingkan al-Bashir dan membawa harapan untuk transisi demokrasi, namun proses ini terganggu oleh kudeta militer pada tahun 2021. Akhirnya, perang saudara baru meletus pada tahun 2023 antara faksi-faksi militer, yang semakin memperburuk situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan di negara tersebut.
3.7.1. Perang Saudara Sudan Pertama

Proses pemungutan suara dilakukan yang menghasilkan komposisi parlemen demokratis dan Ismail al-Azhari terpilih sebagai Perdana Menteri pertama dan memimpin pemerintahan Sudan modern pertama. Pada tanggal 1 Januari 1956, dalam sebuah upacara khusus yang diadakan di Istana Rakyat, bendera Mesir dan Inggris diturunkan dan bendera Sudan yang baru, yang terdiri dari garis-garis hijau, biru dan kuning, dikibarkan menggantikannya oleh perdana menteri Ismail al-Azhari.
Ketidakpuasan memuncak dalam kudeta pada tanggal 25 Mei 1969. Pemimpin kudeta, Kol. Gaafar Nimeiry, menjadi perdana menteri, dan rezim baru menghapuskan parlemen dan melarang semua partai politik.
Penyebab utama Perang Saudara Sudan Pertama (1955-1972) adalah ketidakpuasan mendalam dari penduduk Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan non-Arab terhadap dominasi politik dan budaya dari Sudan Utara yang mayoritas Muslim dan Arab. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, kebijakan pemerintah pusat yang berbasis di Khartoum dianggap mengabaikan aspirasi dan hak-hak otonomi Sudan Selatan. Janji-janji untuk sistem federal tidak ditepati, dan upaya Arabisasi serta Islamisasi semakin memperburuk ketegangan. Kelompok-kelompok pemberontak di Selatan, yang dikenal sebagai Anya-Nya, mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Perang ini berlangsung selama 17 tahun, ditandai dengan kekerasan sporadis namun brutal, yang menyebabkan ratusan ribu kematian dan pengungsian besar-besaran. Masalah kemanusiaan menjadi sangat parah, dengan kelaparan dan penyakit merajalela di daerah konflik. Komunitas internasional pada awalnya kurang memberikan perhatian, namun seiring waktu, tekanan mulai meningkat. Perang berakhir dengan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang memberikan otonomi signifikan kepada Sudan Selatan. Meskipun perjanjian ini membawa periode perdamaian selama sekitar satu dekade, akar penyebab konflik tidak sepenuhnya terselesaikan, yang kemudian memicu Perang Saudara Sudan Kedua.
3.7.2. Rezim Jaafar Nimeiry
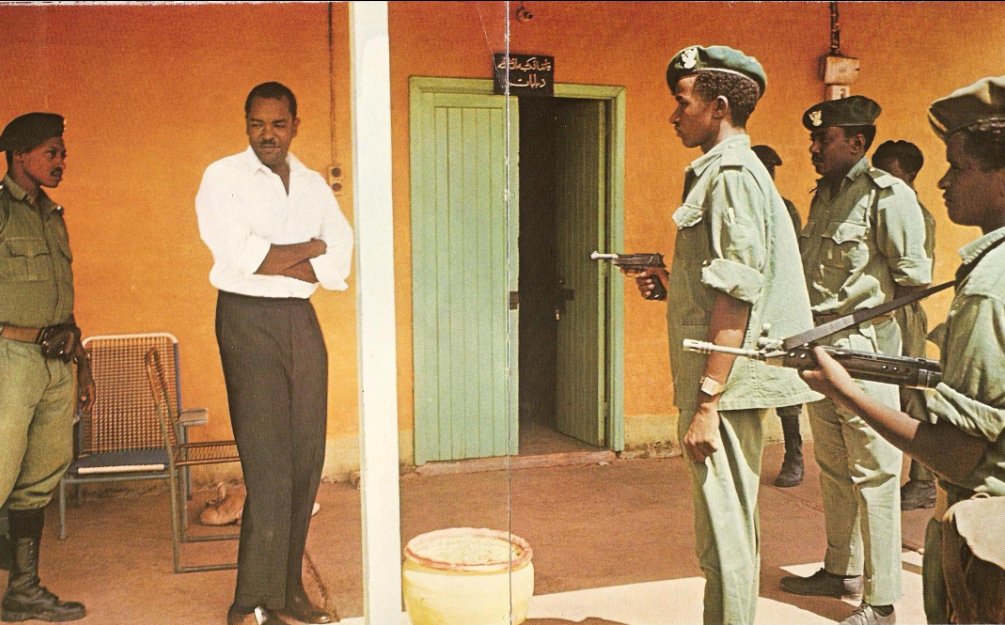
Rezim Jaafar Nimeiry (1969-1985) dimulai dengan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan parlementer. Awalnya, Nimeiry mengadopsi kebijakan sosialis dan nasionalis, menjalin hubungan dekat dengan Blok Timur. Namun, setelah upaya kudeta yang gagal oleh faksi komunis pada tahun 1971, ia bergeser ke arah Barat dan memperkuat kekuasaan pribadinya. Salah satu pencapaian awalnya adalah penandatanganan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang mengakhiri Perang Saudara Sudan Pertama dan memberikan otonomi kepada Sudan Selatan.
Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, rezim Nimeiry menjadi semakin otoriter dan tidak stabil. Menghadapi kesulitan ekonomi dan meningkatnya oposisi, Nimeiry berusaha memperkuat legitimasinya dengan mendekati kelompok-kelompok Islamis. Pada tahun 1983, ia secara kontroversial menerapkan hukum Syariah Islam secara nasional, yang dikenal sebagai "Hukum September". Kebijakan ini mencakup hukuman fisik seperti amputasi dan cambuk, serta pembatasan terhadap non-Muslim. Penerapan Syariah ini berdampak sangat negatif, memicu kemarahan di Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan menjadi salah satu pemicu utama pecahnya Perang Saudara Sudan Kedua. Selain itu, kebijakan ekonomi Nimeiry seringkali tidak efektif, memperburuk kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer, serikat pekerja, dan protes rakyat, akhirnya menyebabkan penggulingannya dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1985 ketika ia berada di luar negeri.
3.7.3. Perang Saudara Sudan Kedua
Perang Saudara Sudan Kedua (1983-2005) merupakan konflik yang jauh lebih lama dan merusak dibandingkan perang pertama. Latar belakang utamanya adalah keputusan Presiden Jaafar Nimeiry pada tahun 1983 untuk mencabut status otonomi Sudan Selatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Addis Ababa 1972, serta penerapan hukum Syariah Islam secara nasional. Tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan penduduk Sudan Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan animisme. Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang menjadi kekuatan pemberontak utama, menuntut pemerintahan sekuler, otonomi yang lebih besar, atau bahkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan.
Pihak-pihak yang bertikai adalah pemerintah Sudan yang berbasis di Khartoum, yang didominasi oleh elit Arab-Muslim dari Utara, melawan SPLA dan faksi-faksi pemberontak lainnya di Selatan. Konflik ini ditandai dengan kekerasan brutal, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan tentara anak-anak, perbudakan, dan taktik bumi hangus. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas oleh kedua belah pihak, meskipun pasukan pemerintah dan milisi sekutunya seringkali dituduh melakukan kekejaman yang lebih sistematis. Krisis kemanusiaan yang diakibatkannya sangat parah, dengan jutaan orang tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit, serta jutaan lainnya menjadi pengungsi internal atau melarikan diri ke negara tetangga.
Intervensi internasional awalnya terbatas, tetapi meningkat seiring dengan memburuknya situasi kemanusiaan dan tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Upaya negosiasi damai yang dimediasi oleh berbagai pihak, termasuk Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan negara-negara Barat, berlangsung bertahun-tahun. Proses ini akhirnya memuncak pada penandatanganan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) pada tahun 2005 di Naivasha, Kenya. CPA mengakhiri perang, memulihkan otonomi Sudan Selatan, dan menjadwalkan referendum kemerdekaan bagi wilayah tersebut, yang akhirnya dilaksanakan pada tahun 2011.
3.7.4. Rezim Omar al-Bashir dan Konflik Darfur

Omar al-Bashir merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 30 Juni 1989. Pemerintahan militernya yang baru menangguhkan partai politik dan memperkenalkan hukum Islam di tingkat nasional. Kemudian, al-Bashir melakukan pembersihan dan eksekusi di jajaran atas tentara, melarang asosiasi, partai politik, dan surat kabar independen, serta memenjarakan tokoh politik dan jurnalis terkemuka. Pada 16 Oktober 1993, al-Bashir mengangkat dirinya sebagai "Presiden" dan membubarkan Dewan Komando Revolusioner. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dewan diambil alih oleh al-Bashir.
Dalam pemilihan umum 1996, ia adalah satu-satunya kandidat yang mencalonkan diri berdasarkan hukum. Sudan menjadi negara satu partai di bawah Partai Kongres Nasional (NCP). Selama tahun 1990-an, Hassan al-Turabi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional, mendekati kelompok-kelompok fundamentalis Islam dan mengundang Osama bin Laden ke negara itu. Amerika Serikat kemudian memasukkan Sudan ke dalam daftar negara sponsor terorisme. Menyusul pemboman kedutaan AS di Kenya dan Tanzania oleh Al Qaeda, AS melancarkan Operasi Infinite Reach dan menargetkan pabrik farmasi Al-Shifa, yang secara keliru diyakini oleh pemerintah AS memproduksi senjata kimia untuk kelompok teroris tersebut. Pengaruh Al-Turabi mulai memudar, dan pihak lain yang mendukung kepemimpinan yang lebih pragmatis mencoba mengubah isolasi internasional Sudan. Negara itu berupaya menenangkan para pengkritiknya dengan mengusir anggota Jihad Islam Mesir dan mendorong bin Laden untuk pergi.

Sebelum pemilihan presiden tahun 2000, al-Turabi memperkenalkan rancangan undang-undang untuk mengurangi kekuasaan Presiden, yang mendorong al-Bashir untuk memerintahkan pembubaran dan mengumumkan keadaan darurat. Ketika al-Turabi mendesak boikot kampanye pemilihan kembali Presiden dan menandatangani perjanjian dengan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, al-Bashir mencurigai mereka merencanakan untuk menggulingkan pemerintah. Hassan al-Turabi dipenjara pada tahun yang sama.
Pada Februari 2003, kelompok Gerakan/Tentara Pembebasan Sudan (SLM/A) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) di Darfur mengangkat senjata, menuduh pemerintah Sudan menindas warga Sudan non-Arab demi Arab Sudan, yang memicu Perang di Darfur. Konflik ini sejak itu digambarkan sebagai genosida, dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan dua surat perintah penangkapan untuk al-Bashir. Milisi nomaden berbahasa Arab yang dikenal sebagai Janjaweed dituduh melakukan banyak kekejaman. Pemerintahan jangka panjang Omar al-Bashir (1989-2019) diwarnai oleh penindasan brutal terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Rezim ini bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 300.000 hingga 400.000 orang, terutama terkait dengan genosida di Darfur yang dimulai pada tahun 2003. Konflik Darfur dipicu oleh keluhan lama dari kelompok-kelompok etnis non-Arab terhadap marjinalisasi politik dan ekonomi oleh pemerintah pusat yang didominasi Arab. Pemerintah merespons pemberontakan dengan mengerahkan milisi Arab Janjaweed, yang melakukan serangan sistematis terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Kekejaman ini menyebabkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Sanksi internasional diberlakukan terhadap Sudan sebagai akibat dari pelanggaran HAM dan dugaan dukungan terhadap terorisme. Krisis kemanusiaan di Darfur dan wilayah konflik lainnya sangat parah, dengan jutaan orang mengungsi dan bergantung pada bantuan internasional. Penindasan terhadap oposisi politik, aktivis HAM, dan jurnalis menjadi hal biasa, menciptakan iklim ketakutan dan membatasi kebebasan sipil secara drastis.
Pada 9 Januari 2005, pemerintah menandatangani Perjanjian Damai Komprehensif Nairobi dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dengan tujuan mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan (UNMIS) didirikan di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1590 untuk mendukung implementasinya. Perjanjian damai ini merupakan prasyarat untuk referendum 2011: hasilnya adalah suara bulat yang mendukung pemisahan Sudan Selatan; wilayah Abyei akan mengadakan referendumnya sendiri di kemudian hari.
Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) adalah anggota utama Front Timur, sebuah koalisi kelompok pemberontak yang beroperasi di Sudan timur. Setelah perjanjian damai, tempat mereka diambil pada Februari 2004 setelah penggabungan Fulani yang lebih besar dan Kongres Beja dengan Singa Bebas Rashaida yang lebih kecil. Sebuah perjanjian damai antara pemerintah Sudan dan Front Timur ditandatangani pada 14 Oktober 2006, di Asmara. Pada 5 Mei 2006, Perjanjian Damai Darfur ditandatangani, bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun hingga saat ini. Konflik Chad-Sudan (2005-2007) meletus setelah Pertempuran Adré memicu deklarasi perang oleh Chad. Para pemimpin Sudan dan Chad menandatangani perjanjian di Arab Saudi pada 3 Mei 2007 untuk menghentikan pertempuran dari konflik Darfur yang meluas di sepanjang perbatasan 1.00 K km negara mereka.
Pada Juli 2007 negara itu dilanda banjir dahsyat, dengan lebih dari 400.000 orang terkena dampak langsung. Sejak 2009, serangkaian konflik yang sedang berlangsung antara suku-suku nomaden yang bersaing di Sudan dan Sudan Selatan telah menyebabkan sejumlah besar korban sipil.
3.7.5. Pemisahan Diri Sudan Selatan

Proses pemisahan diri Sudan Selatan merupakan puncak dari konflik berkepanjangan antara Utara dan Selatan Sudan, yang berakar pada perbedaan budaya, agama, dan politik. Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) tahun 2005, yang mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua, mengatur pelaksanaan referendum kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Referendum ini diadakan pada Januari 2011, dengan partisipasi yang sangat tinggi dari penduduk Sudan Selatan. Hasilnya sangat meyakinkan: hampir 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.
Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya, menjadi negara terbaru di dunia. Pemisahan ini disambut dengan perayaan di Sudan Selatan, namun juga menimbulkan sejumlah isu kompleks yang belum terselesaikan antara kedua negara. Isu-isu utama termasuk pembagian pendapatan minyak (karena sebagian besar cadangan minyak berada di Selatan tetapi infrastruktur ekspor melalui Utara), demarkasi perbatasan yang disengketakan (terutama di wilayah Abyei, Kurdufan Selatan, dan Nil Biru), status kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayah masing-masing, dan pembagian utang nasional.
Hubungan antara Sudan dan Sudan Selatan setelah pemisahan diri tetap tegang, seringkali diwarnai oleh tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak dan bentrokan perbatasan, seperti Krisis Heglig pada tahun 2012. Meskipun ada upaya mediasi internasional, penyelesaian komprehensif atas isu-isu pasca-pemisahan diri ini tetap menjadi tantangan besar bagi kedua negara. Pemisahan ini juga berdampak signifikan pada ekonomi Sudan, yang kehilangan sebagian besar pendapatan minyaknya.
3.7.6. Revolusi 2019 dan Pemerintahan Transisi

Revolusi Sudan 2019 dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, termasuk kenaikan harga roti dan bahan bakar, serta ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan otoriter Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade. Protes massal dimulai pada Desember 2018 dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, dipimpin oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA) dan berbagai kelompok oposisi sipil yang kemudian bersatu dalam Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC). Para demonstran menuntut pengunduran diri al-Bashir dan transisi ke pemerintahan sipil.
Setelah berbulan-bulan protes yang gigih dan seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk pembantaian Khartoum pada 3 Juni 2019 di mana ratusan pengunjuk rasa damai dibunuh oleh pasukan keamanan, militer akhirnya melakukan kudeta pada 11 April 2019, menggulingkan al-Bashir dan membentuk Dewan Militer Transisi (TMC). Namun, para pengunjuk rasa terus menuntut penyerahan kekuasaan penuh kepada warga sipil.
Setelah negosiasi yang alot dan mediasi internasional, TMC dan FFC menandatangani Perjanjian Politik pada Juli 2019 dan Deklarasi Konstitusional Draf pada Agustus 2019. Perjanjian ini membentuk pemerintahan transisi bersama militer-sipil, termasuk Dewan Kedaulatan Sudan sebagai kepala negara kolektif dan penunjukan Abdalla Hamdok sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan transisi bertugas memimpin negara selama 39 bulan menuju pemilihan umum yang demokratis.
Upaya implementasi demokrasi selama periode transisi mencakup pencabutan beberapa hukum represif era al-Bashir, memulai proses perdamaian dengan kelompok-kelompok pemberontak, dan upaya reformasi ekonomi. Perubahan sosial juga mulai terlihat, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik serta ruang publik yang lebih terbuka. Namun, pemerintahan transisi menghadapi tantangan besar, termasuk krisis ekonomi yang berkelanjutan, perpecahan internal, dan tekanan dari sisa-sisa rezim lama serta faksi-faksi militer yang enggan melepaskan kekuasaan.
3.7.7. Kudeta 2021 dan Rezim al-Burhan
Pemerintah Sudan mengumumkan pada 21 September 2021 bahwa telah terjadi upaya kudeta yang gagal dari pihak militer yang menyebabkan penangkapan 40 perwira militer. Sebulan setelah upaya kudeta tersebut, kudeta militer lainnya pada 25 Oktober 2021 mengakibatkan penggulingan pemerintahan sipil, termasuk mantan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Kudeta ini dipimpin oleh jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang kemudian mengumumkan keadaan darurat. Latar belakang kudeta ini adalah meningkatnya ketegangan antara komponen militer dan sipil dalam pemerintahan transisi. Militer, yang dipimpin oleh Jenderal al-Burhan (Ketua Dewan Kedaulatan) dan Jenderal "Hemedti" (Wakil Ketua dan pemimpin Pasukan Dukungan Cepat/RSF), merasa terancam oleh tuntutan reformasi sektor keamanan dan penyerahan kekuasaan penuh kepada sipil.
Kudeta tersebut menyebabkan pembubaran pemerintahan transisi yang dibentuk setelah revolusi 2019. Al-Burhan mengambil alih kekuasaan sebagai kepala negara de facto dan membentuk pemerintahan baru yang didukung militer pada 11 November 2021. Respons domestik terhadap kudeta sangat kuat, dengan protes massal yang meluas menuntut kembalinya pemerintahan sipil. Protes ini seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan, mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, dan negara-negara Barat, mengutuk kudeta tersebut dan menyerukan pemulihan tatanan konstitusional. Sanksi dan penangguhan bantuan diberlakukan oleh beberapa negara.
Meskipun ada tekanan internasional dan upaya mediasi, pada 21 November 2021, Hamdok diangkat kembali sebagai Perdana Menteri setelah perjanjian politik ditandatangani oleh Burhan untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil (meskipun Burhan tetap memegang kendali). Kesepakatan 14 poin tersebut menyerukan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 terus menjadi dasar bagi transisi politik. Hamdok memecat kepala polisi Khaled Mahdi Ibrahim al-Emam dan wakilnya Ali Ibrahim. Namun, perjanjian ini ditolak oleh banyak kelompok pro-demokrasi yang melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer. Hamdok akhirnya mengundurkan diri pada 2 Januari 2022, setelah protes mematikan. Ia digantikan oleh Osman Hussein. Pada Maret 2022 lebih dari 1.000 orang termasuk 148 anak-anak telah ditahan karena menentang kudeta, ada 25 tuduhan pemerkosaan dan 87 orang telah tewas termasuk 11 anak-anak. Kudeta 2021 secara signifikan menghambat kemajuan menuju demokrasi di Sudan, menimbulkan kekhawatiran serius akan kembalinya pemerintahan otoriter dan meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut.
3.7.8. Perang Saudara Pasca-2023

Pada April 2023 - ketika rencana yang ditengahi secara internasional untuk transisi ke pemerintahan sipil sedang dibahas - perebutan kekuasaan meningkat antara komandan angkatan darat (dan pemimpin nasional de facto) Abdel Fattah al-Burhan, dan wakilnya, "Hemedti", kepala paramiliter bersenjata berat Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dibentuk dari milisi Janjaweed. Penyebab utama pecahnya perang saudara pada tahun 2023 adalah perebutan kekuasaan yang mendalam antara dua faksi militer utama: Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti"). Ketegangan antara kedua jenderal ini, yang sebelumnya bersekutu dalam kudeta 2021, meningkat tajam terkait rencana integrasi RSF ke dalam struktur komando SAF, sebuah langkah kunci dalam transisi menuju pemerintahan sipil. Hemedti menolak integrasi tersebut karena khawatir akan kehilangan otonomi dan pengaruh pasukannya.
Konflik meletus pada 15 April 2023, dimulai dengan pertempuran di jalanan Khartoum antara tentara dan RSF - dengan pasukan, tank, dan pesawat. Pada hari ketiga, 400 orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 3.500 lainnya terluka, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antara korban tewas terdapat tiga pekerja dari Program Pangan Dunia, yang memicu penangguhan pekerjaan organisasi tersebut di Sudan, meskipun kelaparan terus melanda sebagian besar negara itu. Jenderal Sudan Yasser al-Atta mengatakan bahwa UEA menyediakan pasokan untuk RSF, yang digunakan dalam perang tersebut.
Perkembangan utama perang ini mencakup pertempuran sengit di ibu kota Khartoum dan kota-kota besar lainnya, serta eskalasi kekerasan etnis di wilayah Darfur, di mana RSF dan milisi sekutunya dituduh melakukan kekejaman massal terhadap komunitas non-Arab, terutama Masalit. Komunitas internasional, termasuk PBB, Uni Afrika, dan negara-negara regional, berupaya menengahi gencatan senjata dan memulai proses perdamaian, namun upaya ini sebagian besar gagal mencapai hasil yang langgeng.
Krisis kemanusiaan akibat perang ini sangat parah. Pada 29 Desember 2023, lebih dari 5,8 juta orang mengungsi secara internal dan lebih dari 1,5 juta lainnya telah melarikan diri dari negara itu sebagai pengungsi, dan banyak warga sipil di Darfur dilaporkan tewas sebagai bagian dari pembantaian Masalit. Hingga 15.000 orang tewas di kota Geneina. Dampak pada hak asasi manusia sangat serius, dengan laporan pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual yang meluas, penjarahan, dan serangan terhadap infrastruktur sipil. Jutaan orang menghadapi kelaparan akut, dan sistem layanan kesehatan runtuh. Fungsi negara praktis lumpuh di banyak wilayah, menciptakan kekosongan keamanan dan memperburuk penderitaan warga sipil. Hingga April 2024, PBB melaporkan bahwa lebih dari 8,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara 18 juta menghadapi kelaparan parah, lima juta di antaranya berada pada tingkat darurat. Pada Mei 2024, pejabat pemerintah AS memperkirakan bahwa setidaknya 150.000 orang telah tewas dalam perang tersebut hanya dalam setahun terakhir. Penargetan RSF terhadap komunitas adat kulit hitam, terutama di sekitar kota El Fasher, telah membuat para pejabat internasional memperingatkan risiko terulangnya sejarah dengan genosida lain di wilayah Darfur.
Pada 31 Mei 2024, sebuah konferensi diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat oleh Anggota Kongres AS Eleanor Holmes Norton untuk mengatasi krisis kemanusiaan Sudan. Sebuah laporan oleh Departemen Luar Negeri mengenai keterlibatan UEA di Sudan, termasuk kejahatan perang dan ekspor senjata, menjadi fokus utama diskusi konferensi tersebut. Seorang panelis, Anggota Dewan Mohamed Seifeldein, menyerukan diakhirinya keterlibatan UEA di Sudan, menyatakan bahwa peran UEA dalam menggunakan RSF di Sudan dan juga dalam perang saudara Yaman "perlu dihentikan". Seifeldein, bersama dengan panelis lain Hagir S. Elsheikh, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan semua dukungan untuk RSF, menunjuk pada peran destruktif kelompok militan tersebut di Sudan. Elsheikh juga merekomendasikan penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesadaran tentang perang Sudan, dan untuk menekan para pejabat terpilih AS untuk menghentikan penjualan senjata ke UEA. Laporan terbaru yang disampaikan kepada PBB menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan ada 30,4 juta orang di Sudan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, akibat konflik militer di negara tersebut. Baik Angkatan Bersenjata Sudan maupun Pasukan Dukungan Cepat dituduh melakukan kejahatan perang.
4. Geografi

Sudan terletak di Afrika Utara, dengan garis pantai sepanjang 853 km yang berbatasan dengan Laut Merah. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Libya. Dengan luas wilayah 1.89 M km2, Sudan adalah negara terbesar ketiga di benua Afrika (setelah Aljazair dan Republik Demokratik Kongo) dan kelima belas terbesar di dunia.
Sudan terletak di antara garis lintang 8° dan 23°LU. Secara umum, medannya berupa dataran datar yang diselingi oleh beberapa rangkaian pegunungan. Di bagian barat, Kaldera Deriba (3.04 K m), yang terletak di Pegunungan Marrah, merupakan titik tertinggi di Sudan. Di bagian timur terdapat Perbukitan Laut Merah.
Sumber daya mineral yang kaya tersedia di Sudan termasuk asbes, kromit, kobalt, tembaga, emas, granit, gipsum, besi, kaolin, timbal, mangan, mika, gas alam, nikel, minyak bumi, perak, timah, uranium, dan seng. Pada tahun 2015, produksi emas Sudan mencapai 82 metrik ton.
4.1. Topografi

Topografi Sudan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang diselingi oleh beberapa formasi geografis penting. Di bagian barat, Pegunungan Marrah menjulang, dengan Kaldera Deriba (3.04 K m) sebagai titik tertinggi negara ini. Pegunungan ini merupakan daerah vulkanik dan memiliki peran penting dalam hidrologi regional. Di bagian tengah dan selatan, dataran luas membentang, dialiri oleh Sungai Nil dan anak-anak sungainya. Wilayah utara didominasi oleh gurun, termasuk Gurun Nubia di timur laut dan Gurun Bayuda di sebelah timur Sungai Nil. Gurun Nubia merupakan bagian dari Gurun Sahara yang lebih besar, ditandai dengan medan berbatu dan bukit pasir. Gurun Bayuda, meskipun juga kering, memiliki beberapa oasis dan vegetasi sporadis. Di bagian timur, dekat pantai Laut Merah, terdapat Perbukitan Laut Merah yang membentang sejajar dengan garis pantai.
4.2. Iklim

Sudan memiliki beberapa zona iklim utama. Bagian utara didominasi oleh iklim gurun (BWh menurut klasifikasi iklim Köppen), yang ditandai dengan suhu yang sangat tinggi pada siang hari, malam yang dingin, dan curah hujan yang sangat minim, seringkali kurang dari 100 mm per tahun. Wilayah tengah, termasuk ibu kota Khartoum, memiliki iklim stepa panas (BSh), dengan musim panas yang sangat panas dan musim hujan singkat antara Juni dan September. Curah hujan di wilayah ini bervariasi, umumnya antara 100 mm hingga 300 mm per tahun. Semakin ke selatan, iklim menjadi lebih lembap. Wilayah selatan Sudan memiliki iklim sabana tropis (Aw), dengan musim hujan yang lebih panjang (biasanya dari Mei hingga Oktober) dan curah hujan tahunan yang dapat mencapai lebih dari 700 mm.
Karakteristik suhu di Sudan sangat bervariasi. Di utara, suhu musim panas dapat melebihi 40 °C, sementara suhu musim dingin bisa turun cukup signifikan pada malam hari. Di wilayah tengah dan selatan, suhu tetap tinggi sepanjang tahun, meskipun sedikit lebih sejuk selama musim hujan. Perubahan musim terutama ditentukan oleh pergerakan Zona Konvergensi Intertropis (ITCZ), yang membawa hujan ke wilayah tersebut. Durasi penyinaran matahari sangat tinggi di seluruh negeri tetapi terutama di gurun di mana ia dapat melonjak hingga lebih dari 4.000 jam per tahun. Daerah kering sering dilanda badai pasir, yang dikenal sebagai haboob, yang dapat menghalangi matahari sepenuhnya.
4.3. Hidrologi
Sistem hidrologi Sudan didominasi oleh Sungai Nil dan dua anak sungai utamanya, yaitu Nil Biru dan Nil Putih. Kedua sungai ini bertemu di ibu kota, Khartoum, membentuk Sungai Nil utama yang kemudian mengalir ke utara menuju Mesir dan Laut Mediterania.
Nil Biru, yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia, menyumbang sebagian besar volume air dan sedimen Sungai Nil, terutama selama musim hujan di dataran tinggi Ethiopia (Juni hingga September). Aliran Nil Biru melalui Sudan hampir sepanjang 800 km dan bergabung dengan Dinder dan Rahad antara Sennar dan Khartoum.
Nil Putih memiliki aliran yang lebih stabil sepanjang tahun, berasal dari wilayah Danau Besar Afrika. Di dalam Sudan, Nil Putih tidak memiliki anak sungai yang signifikan.
Selain Sungai Nil dan anak-anak sungainya, terdapat beberapa wadi (sungai musiman) yang hanya terisi air selama periode hujan singkat. Danau-danau alami di Sudan relatif sedikit dan kecil, namun terdapat Danau Nubia, sebuah danau buatan besar yang terbentuk akibat pembangunan Bendungan Tinggi Aswan, yang sebagian besar terletak di Mesir (dikenal sebagai Danau Nasser) dan sebagian kecil di utara Sudan.
Pembangunan bendungan merupakan aspek penting dalam hidrologi Sudan. Beberapa bendungan telah dibangun di Nil Biru dan Nil Putih untuk tujuan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Di antaranya adalah Sennar dan Roseires di Nil Biru, serta Jebel Aulia di Nil Putih. Pembangunan bendungan ini memiliki dampak signifikan terhadap pola aliran sungai dan ekosistem di sekitarnya.
4.4. Masalah Lingkungan

Sudan menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang serius, yang berdampak signifikan terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan penduduknya. Salah satu masalah utama adalah desertifikasi, yaitu proses perluasan gurun ke lahan yang sebelumnya subur. Hal ini terutama terjadi di wilayah utara dan tengah negara, didorong oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, penggundulan hutan untuk kayu bakar dan pertanian, serta praktik penggembalaan yang berlebihan. Desertifikasi menyebabkan hilangnya lahan produktif, penurunan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya kerentanan terhadap kekeringan.
Erosi tanah adalah masalah terkait lainnya, yang diperburuk oleh hilangnya tutupan vegetasi dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Erosi mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan sedimentasi di sungai dan waduk. Deforestasi, atau penggundulan hutan, juga merupakan masalah serius, terutama di wilayah sabana dan hutan yang lebih lebat. Hutan ditebangi untuk lahan pertanian, kayu bakar, produksi arang, dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya termasuk hilangnya habitat satwa liar, gangguan siklus air, dan peningkatan emisi karbon.
Perluasan pertanian, baik publik maupun swasta, telah berlangsung tanpa tindakan konservasi yang memadai. Konsekuensinya telah mewujud dalam bentuk deforestasi, pengeringan tanah, dan penurunan kesuburan tanah dan permukaan air tanah.
Selain itu, Sudan juga menghadapi tantangan terkait pengelolaan sumber daya air, polusi air akibat limbah industri dan pertanian, serta dampak perubahan iklim seperti peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan dan banjir. Konflik bersenjata yang berkepanjangan juga seringkali memperburuk masalah lingkungan, karena menyebabkan perpindahan penduduk, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam.
4.5. Ekosistem dan Satwa Liar
Sudan memiliki beragam wilayah ekologi, mulai dari gurun pasir di utara hingga sabana dan hutan di selatan. Gurun seperti Gurun Nubia dan Gurun Bayuda memiliki flora dan fauna yang beradaptasi dengan kondisi kering ekstrem, termasuk berbagai jenis akasia, rumput gurun, serta mamalia seperti rusa ramping dan rubah Rüppell.
Wilayah sabana, yang mencakup sebagian besar bagian tengah dan selatan negara, merupakan rumah bagi berbagai jenis rumput, pohon akasia, dan baobab. Satwa liar khas sabana Sudan meliputi gajah afrika, jerapah, berbagai jenis antilop (seperti tiang, waterbuck, dan kudu), singa, macan tutul, dan dubuk. Kawasan lahan basah di sekitar Sungai Nil dan anak-anak sungainya, seperti Sudd (sebagian besar kini di Sudan Selatan namun berdampak pada ekosistem perbatasan), mendukung populasi kuda nil, buaya, dan berbagai jenis burung air.
Pegunungan seperti Pegunungan Marrah di Darfur memiliki ekosistem yang unik dengan flora dan fauna endemik. Hutan tropis yang lebih lebat dapat ditemukan di bagian paling selatan negara yang berbatasan dengan Sudan Selatan.
Beberapa spesies di Sudan terancam punah akibat perburuan liar, hilangnya habitat, dan konflik. Spesies yang terancam kritis meliputi: waldrapp, badak putih utara, hartebeest tora, rusa ramping tanduk ramping, dan penyu sisik. Oryx Sahara telah punah di alam liar. Upaya konservasi di Sudan mencakup pendirian taman nasional dan cagar alam, seperti Taman Nasional Dinder dan Taman Nasional Radom. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, ketidakstabilan politik, dan konflik. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Sudan menjadi tantangan penting di tengah tekanan pembangunan dan masalah lingkungan.
5. Politik
Sistem politik Sudan telah mengalami perubahan signifikan dan ketidakstabilan selama beberapa dekade terakhir. Secara formal, politik Sudan berlangsung dalam kerangka republik otoriter Islam hingga April 2019, ketika rezim Presiden Omar al-Bashir digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ahmed Awad Ibn Auf. Sebagai langkah awal, ia membentuk Dewan Militer Transisi untuk mengelola urusan dalam negeri negara itu. Ia juga menangguhkan konstitusi dan membubarkan parlemen bikameral - Legislatif Nasional, dengan Majelis Nasional (majelis rendah) dan Dewan Negara (majelis tinggi). Namun, Ibn Auf hanya menjabat selama satu hari dan kemudian mengundurkan diri, dengan kepemimpinan Dewan Militer Transisi kemudian diserahkan kepada Abdel Fattah al-Burhan. Pada 4 Agustus 2019, Deklarasi Konstitusional baru ditandatangani antara perwakilan Dewan Militer Transisi dan Pasukan Kebebasan dan Perubahan, dan pada 21 Agustus 2019 Dewan Militer Transisi secara resmi digantikan sebagai kepala negara oleh Dewan Kedaulatan beranggotakan 11 orang, dan sebagai kepala pemerintahan oleh seorang Perdana Menteri sipil. Namun, Dewan Kedaulatan dan pemerintah Sudan dibubarkan pada Oktober 2021 setelah kudeta militer lainnya.
Perkembangan demokrasi di Sudan telah terhambat oleh periode panjang pemerintahan militer, konflik internal, dan penindasan terhadap oposisi. Revolusi 2019 membawa harapan akan transisi menuju demokrasi, tetapi proses ini terbukti sulit dan rapuh. Isu hak asasi manusia tetap menjadi perhatian serius, dengan laporan pelanggaran yang meluas, terutama di daerah konflik. Korupsi juga menjadi masalah kronis yang merusak tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Situasi politik Sudan saat ini sangat tidak stabil, dengan perebutan kekuasaan antara faksi-faksi militer yang memicu perang saudara sejak April 2023, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan dan menghancurkan prospek demokrasi. Menurut indeks Demokrasi V-Dem tahun 2023, Sudan adalah negara paling tidak demokratis ke-6 di Afrika.
5.1. Struktur Pemerintahan
Struktur pemerintahan Sudan telah mengalami perubahan signifikan akibat gejolak politik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penggulingan rezim Omar al-Bashir pada tahun 2019, sebuah pemerintahan transisi dibentuk berdasarkan kesepakatan antara militer dan kelompok sipil. Struktur ini mencakup:
- Dewan Kedaulatan: Bertindak sebagai kepala negara kolektif, terdiri dari perwakilan militer dan sipil. Awalnya dipimpin secara bergantian, namun setelah kudeta 2021, militer di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil kendali penuh.
- Lembaga Eksekutif (Kabinet): Dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sipil yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Abdalla Hamdok menjabat sebagai Perdana Menteri hingga kudeta 2021, dan sempat diangkat kembali sebelum akhirnya mengundurkan diri pada awal 2022. Setelah itu, posisi ini diisi oleh figur yang ditunjuk oleh militer.
- Lembaga Legislatif: Selama periode transisi, direncanakan pembentukan Dewan Legislatif Transisi, namun implementasinya terhambat. Setelah kudeta 2021, fungsi legislatif praktis berada di bawah kendali Dewan Kedaulatan yang didominasi militer. Parlemen bikameral sebelumnya (Majelis Nasional dan Dewan Negara) telah dibubarkan.
- Lembaga Yudikatif: Secara teori independen, terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Nasional, Pengadilan Kasasi, dan pengadilan nasional lainnya. Komisi Layanan Yudisial Nasional bertugas mengelola peradilan secara keseluruhan. Namun, independensi peradilan sering dipertanyakan, terutama di bawah pemerintahan militer.
Sistem pemilihan umum yang demokratis belum sepenuhnya terwujud. Pemilihan umum yang dijadwalkan sebagai bagian dari transisi pasca-2019 ditunda akibat kudeta. Struktur pemerintahan transisi yang dibentuk setelah kudeta 2021 secara efektif mengembalikan dominasi militer dalam pengambilan keputusan, memicu protes luas dari kelompok pro-demokrasi dan kecaman internasional. Pecahnya perang saudara pada tahun 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) semakin menghancurkan struktur pemerintahan yang ada dan menciptakan kekosongan kekuasaan di banyak wilayah.
5.2. Penerapan Hukum Syariah dan Perubahannya
Penerapan hukum Syariah (hukum Islam) di Sudan memiliki sejarah yang panjang dan kontroversial, serta berdampak signifikan terhadap politik dan masyarakat negara tersebut.
- Era Nimeiry: Presiden Jaafar Nimeiry pertama kali memperkenalkan hukum Syariah secara nasional pada tahun 1983, yang dikenal sebagai "Hukum September". Kebijakan ini mencakup penerapan hukuman hudud seperti amputasi dan rajam, serta pembatasan terhadap non-Muslim. Langkah ini memicu kemarahan di Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan menjadi salah satu pemicu utama Perang Saudara Sudan Kedua.
- Era al-Bashir: Setelah Omar al-Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989, penerapan Syariah semakin diperkuat dan menjadi landasan sistem hukum negara. Hukum pidana dan perdata didasarkan pada interpretasi Syariah, meskipun Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) tahun 2005 memberikan beberapa pengecualian untuk non-Muslim di Khartoum dan menetapkan bahwa Syariah tidak berlaku di Sudan Selatan. Namun, dalam praktiknya, non-Muslim dan perempuan sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di bawah sistem ini. Hukuman fisik seperti cambuk untuk pelanggaran moral (misalnya, "pakaian tidak senonoh" bagi perempuan atau konsumsi alkohol) sering diterapkan.
- Pasca-Revolusi 2019: Setelah penggulingan al-Bashir, pemerintahan transisi mengambil langkah-langkah untuk mereformasi sistem hukum. Konstitusi interim yang ditandatangani pada Agustus 2019 tidak menyebutkan Syariah sebagai sumber hukum utama. Pada Juli 2020, beberapa hukum Syariah yang paling kontroversial dicabut atau diubah, termasuk penghapusan hukuman mati untuk murtad, pelarangan cambuk di depan umum, dan pencabutan larangan alkohol bagi non-Muslim. mutilasi genital perempuan juga dikriminalisasi. Pada September 2020, sebuah kesepakatan antara pemerintah transisi dan pimpinan kelompok pemberontak menyetujui pemisahan resmi antara negara dan agama, mengakhiri tiga dekade pemerintahan di bawah hukum Islam dan menetapkan bahwa tidak akan ada agama negara resmi.
- Perdebatan Sosial: Meskipun ada perubahan hukum, perdebatan sosial mengenai peran Syariah dalam sistem hukum dan kehidupan publik terus berlanjut. Beberapa kelompok konservatif menginginkan kembalinya penerapan Syariah yang lebih ketat, sementara kelompok liberal dan sekuler mendukung pemisahan penuh antara agama dan negara serta perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan. Kudeta militer tahun 2021 menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan kemunduran dalam reformasi hukum ini, meskipun belum ada perubahan formal yang signifikan terhadap status hukum Syariah yang telah direformasi.
5.3. Pembagian Administratif

Sudan dibagi menjadi 18 negara bagian (wilayat, tunggal: wilayah). Negara bagian ini selanjutnya dibagi lagi menjadi 133 distrik.
- Al Jazirah
- Al Qadarif
- Nil Biru
- Darfur Tengah
- Darfur Timur
- Kassala
- Khartoum
- Darfur Utara
- Kordofan Utara
- Utara
- Laut Merah
- Sungai Nil
- Sennar
- Darfur Selatan
- Kordofan Selatan
- Darfur Barat
- Kordofan Barat
- Nil Putih
Selain negara bagian, terdapat juga badan administratif regional yang dibentuk melalui perjanjian damai antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak:
- Pemerintah Regional Darfur didirikan berdasarkan Perjanjian Damai Darfur untuk bertindak sebagai badan koordinasi bagi negara-bagian yang membentuk wilayah Darfur.
- Dewan Koordinasi Negara Bagian Sudan Timur didirikan berdasarkan Perjanjian Damai Sudan Timur antara Pemerintah Sudan dan pemberontak Front Timur untuk bertindak sebagai badan koordinasi bagi tiga negara bagian timur.
5.4. Daerah Konflik Utama dan Zona Administratif Khusus
Sudan memiliki beberapa daerah konflik utama dan zona administratif khusus yang statusnya sering menjadi sumber ketegangan dan sengketa.
- Abyei: Wilayah Abyei terletak di perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan dan kaya akan minyak. Statusnya masih disengketakan oleh kedua negara. Sesuai Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) 2005, Abyei seharusnya mengadakan referendum untuk menentukan apakah akan bergabung dengan Sudan atau Sudan Selatan, tetapi referendum ini belum terlaksana karena perselisihan mengenai kelayakan pemilih. Wilayah ini saat ini memiliki status administratif khusus dan dikelola oleh Administrasi Wilayah Abyei, dengan kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (UNISFA). Konflik bersenjata sporadis dan ketegangan antar-komunitas sering terjadi, menyebabkan pengungsian dan krisis kemanusiaan.
- Kordofan Selatan dan Nil Biru: Kedua negara bagian ini terletak di Sudan tetapi memiliki populasi yang signifikan yang bersekutu dengan Sudan Selatan selama perang saudara. CPA mengatur "konsultasi rakyat" untuk menentukan masa depan konstitusional mereka di dalam Sudan, tetapi proses ini tidak memuaskan banyak pihak dan menyebabkan konflik baru antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) sejak 2011. Pertempuran telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, pengungsian massal, dan pelanggaran HAM.
- Segitiga Hala'ib: Ini adalah wilayah yang disengketakan antara Sudan dan Mesir di pantai Laut Merah. Mesir saat ini menjalankan administrasi de facto atas wilayah tersebut, tetapi Sudan terus mengklaim kedaulatannya. Sengketa ini kadang-kadang memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.
- Bir Tawil: Sebuah wilayah kecil di perbatasan antara Mesir dan Sudan yang unik karena merupakan terra nullius, yaitu tanah yang tidak diklaim oleh negara mana pun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara dua demarkasi perbatasan historis yang berbeda.
- Darfur: Meskipun Perjanjian Damai Darfur telah ditandatangani, wilayah Darfur (terbagi menjadi lima negara bagian: Darfur Utara, Selatan, Barat, Tengah, dan Timur) tetap menjadi daerah konflik dengan kekerasan sporadis antara berbagai kelompok bersenjata, milisi, dan pasukan pemerintah. Krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi internal dalam jumlah besar dan kekurangan pangan, terus berlanjut. Perang saudara yang meletus pada tahun 2023 telah memperburuk situasi di Darfur secara signifikan, dengan laporan kekejaman massal dan pembersihan etnis.
Pengelolaan zona administratif khusus ini dan penyelesaian sengketa wilayah tetap menjadi tantangan besar bagi stabilitas Sudan. Dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlanjut di wilayah-wilayah ini sangat parah, dengan jutaan orang membutuhkan bantuan dan perlindungan.
6. Hubungan Luar Negeri

Sudan memiliki hubungan yang bermasalah dengan banyak negara tetangganya dan sebagian besar komunitas internasional, karena apa yang dipandang sebagai sikap Islam radikalnya. Selama sebagian besar tahun 1990-an, Uganda, Kenya, dan Ethiopia membentuk aliansi ad hoc yang disebut "Negara-negara Garis Depan" dengan dukungan dari Amerika Serikat untuk mengendalikan pengaruh pemerintah Front Islam Nasional. Pemerintah Sudan mendukung kelompok pemberontak anti-Uganda seperti Pasukan Perlawanan Tuhan (LRA).
Ketika rezim Front Islam Nasional di Khartoum secara bertahap muncul sebagai ancaman nyata bagi kawasan dan dunia, AS mulai memasukkan Sudan ke dalam daftar Negara Sponsor Terorisme. Setelah AS memasukkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme, NIF memutuskan untuk mengembangkan hubungan dengan Irak, dan kemudian Iran, dua negara paling kontroversial di kawasan itu.
Sejak pertengahan 1990-an, Sudan secara bertahap mulai memoderasi posisinya sebagai akibat dari meningkatnya tekanan AS setelah pemboman kedutaan AS 1998, di Tanzania dan Kenya, dan pengembangan baru ladang minyak yang sebelumnya berada di tangan pemberontak. Sudan juga memiliki sengketa teritorial dengan Mesir atas Segitiga Hala'ib. Sejak 2003, hubungan luar negeri Sudan berpusat pada dukungan untuk mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua dan kecaman atas dukungan pemerintah terhadap milisi dalam perang di Darfur.
Arah kebijakan luar negeri Sudan telah berfluktuasi secara signifikan tergantung pada rezim yang berkuasa dan dinamika regional serta internasional. Secara umum, Sudan berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab dan Afrika, serta terlibat dalam organisasi regional seperti Liga Arab dan Uni Afrika. Namun, kebijakan luar negerinya seringkali dipengaruhi oleh konflik internal, sanksi internasional (terutama terkait tuduhan dukungan terorisme dan pelanggaran HAM di Darfur), dan kebutuhan akan bantuan ekonomi serta investasi. Hubungan dengan negara tetangga seperti Mesir, Ethiopia, Sudan Selatan, Chad, dan Libya seringkali kompleks, ditandai oleh kerja sama di beberapa bidang tetapi juga ketegangan terkait isu perbatasan, sumber daya air (terutama Sungai Nil), dan tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia juga memiliki kepentingan strategis di Sudan, yang memengaruhi dinamika hubungan luar negeri negara tersebut. Sudan juga berupaya memainkan peran dalam mediasi konflik regional, meskipun kredibilitasnya kadang terpengaruh oleh masalah internalnya sendiri.
6.1. Hubungan Bilateral Utama
Sudan menjalin hubungan bilateral yang beragam dengan sejumlah negara kunci, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, ekonomi, politik, dan keamanan.
6.1.1. Hubungan dengan Mesir
Hubungan dengan Mesir sangat penting karena kedekatan geografis, sejarah bersama, dan ketergantungan pada Sungai Nil. Kedua negara memiliki ikatan budaya dan ekonomi yang kuat. Namun, hubungan ini juga diwarnai oleh ketegangan, terutama terkait sengketa perbatasan Segitiga Hala'ib dan isu pengelolaan air Sungai Nil, khususnya setelah pembangunan Bendungan Renaisans Besar Etiopia oleh Ethiopia. Mesir seringkali memainkan peran mediasi dalam konflik internal Sudan.
6.1.2. Hubungan dengan Ethiopia
Hubungan dengan Ethiopia juga signifikan, terutama karena isu perbatasan yang belum terselesaikan (khususnya wilayah Al-Fashaga) dan dampak Bendungan Renaisans Besar Etiopia (GERD) terhadap aliran Sungai Nil Biru yang menjadi sumber air penting bagi Sudan. Meskipun ada kerja sama di beberapa bidang, termasuk perdagangan, isu-isu ini seringkali memicu ketegangan diplomatik dan bentrokan perbatasan sporadis.
6.1.3. Hubungan dengan Sudan Selatan
Sejak pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, hubungan antara kedua negara tetap kompleks dan seringkali tegang. Isu-isu utama meliputi demarkasi perbatasan, pembagian pendapatan minyak, status wilayah Abyei yang disengketakan, dan tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak. Meskipun ada perjanjian kerja sama, implementasinya sering terhambat oleh ketidakpercayaan dan konflik internal di kedua negara.
6.1.4. Hubungan dengan Tiongkok
Tiongkok adalah mitra ekonomi utama Sudan, terutama dalam sektor minyak. Tiongkok memperoleh sepuluh persen minyaknya dari Sudan. Menurut seorang mantan menteri pemerintah Sudan, Tiongkok adalah pemasok senjata terbesar Sudan. Selama periode sanksi Barat, Tiongkok menjadi investor dan mitra dagang penting, dengan fokus pada ekstraksi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Hubungan ini bersifat pragmatis dan didorong oleh kepentingan ekonomi, meskipun Tiongkok juga menghadapi kritik terkait dukungannya terhadap rezim al-Bashir.
6.1.5. Hubungan dengan Amerika Serikat
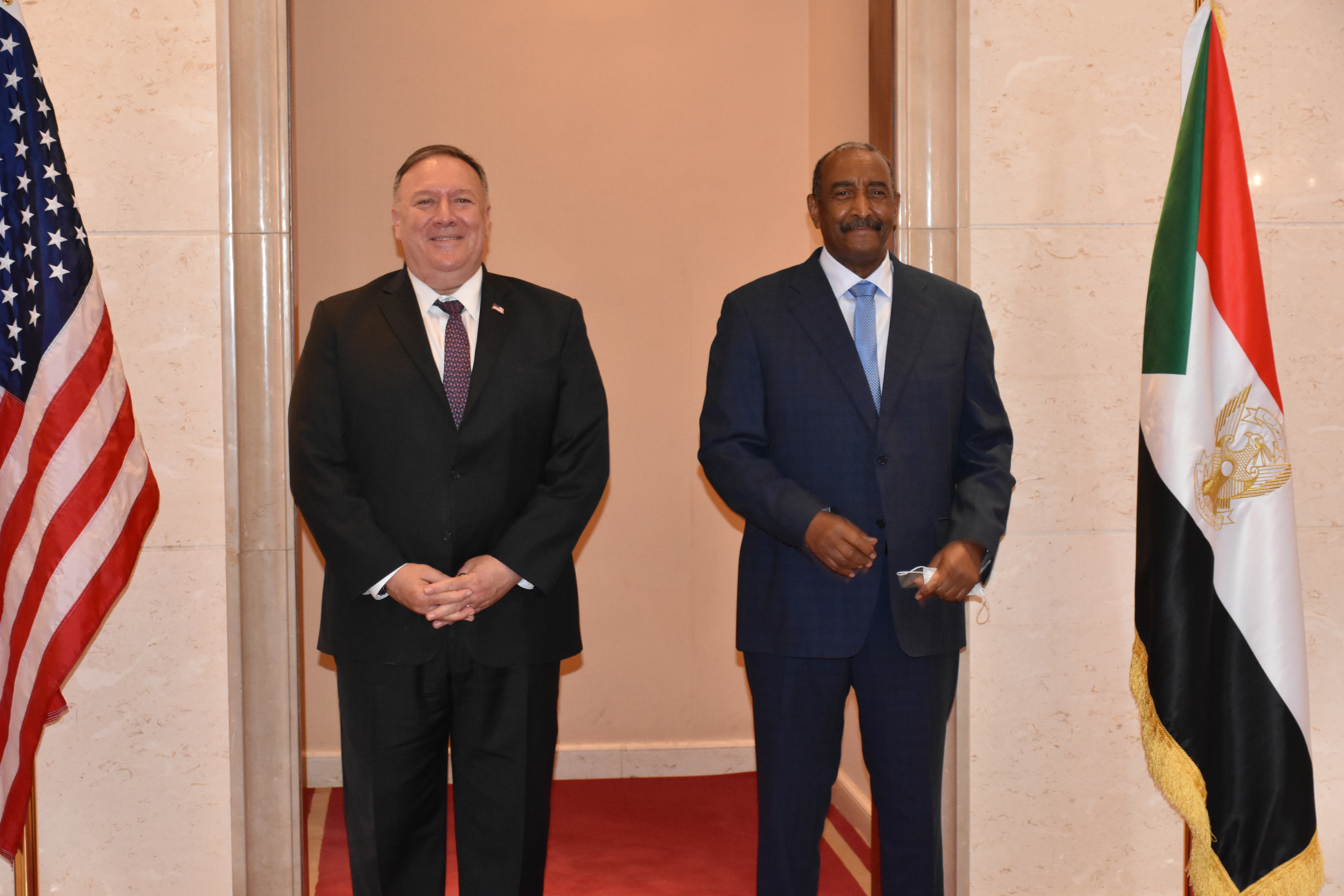
Hubungan Sudan dengan Amerika Serikat telah lama bermasalah, ditandai dengan sanksi ekonomi dan penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme akibat dugaan dukungan terhadap kelompok teroris internasional pada era 1990-an dan pelanggaran HAM di Darfur. Setelah penggulingan al-Bashir, ada upaya untuk memperbaiki hubungan, dan AS mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme pada tahun 2020. Namun, kudeta militer 2021 dan perang saudara 2023 kembali memperburuk hubungan, dengan AS memberlakukan sanksi baru dan menyerukan pemulihan pemerintahan sipil.
6.1.6. Hubungan dengan Rusia
Rusia telah meningkatkan kehadirannya di Sudan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang keamanan dan ekonomi. Ada laporan mengenai kerja sama militer, termasuk potensi pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Port Sudan, serta keterlibatan perusahaan swasta Rusia dalam sektor pertambangan emas. Hubungan ini seringkali dilihat sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Afrika.
6.1.7. Hubungan dengan Indonesia
Sudan dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1960, dengan kedua negara memiliki kedutaan besar di ibu kota masing-masing. Hubungan bilateral ini didasarkan pada solidaritas sebagai sesama negara mayoritas Muslim dan anggota Gerakan Non-Blok serta Organisasi Kerja Sama Islam. Pada Februari 2012, saat kunjungan Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti ke Jakarta, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan ekonomi. Pertukaran budaya dan mahasiswa juga menjadi bagian dari hubungan bilateral ini. Indonesia secara konsisten mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Sudan, serta memberikan bantuan kemanusiaan bila diperlukan.
6.2. Organisasi Internasional
Sudan adalah anggota aktif dari semua organisasi terkait di Afrika dan merupakan anggota piagam Organisasi Kesatuan Afrika, yang didirikan pada tahun 1963 dan berkantor pusat di Addis Ababa. Sudan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai badan khususnya. Negara ini juga aktif dalam organisasi regional seperti Liga Arab, Uni Afrika (AU), dan Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan (COMESA), serta Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Keanggotaan Sudan di organisasi internasional seringkali dipengaruhi oleh situasi politik internalnya. Misalnya, setelah kudeta militer 2019 dan lagi pada 2021, keanggotaan Sudan di Uni Afrika sempat ditangguhkan. Selama rezim Omar al-Bashir, Sudan menghadapi sanksi dari berbagai organisasi internasional dan negara-negara anggota PBB akibat pelanggaran hak asasi manusia, konflik di Darfur, dan tuduhan dukungan terhadap terorisme. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), meskipun bukan organisasi keanggotaan Sudan, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Bashir, yang memengaruhi hubungan Sudan dengan banyak negara anggota Statuta Roma.
Sudan juga menerima dukungan dan bantuan dari berbagai organisasi internasional, terutama dalam bidang kemanusiaan, pembangunan, dan upaya perdamaian. Namun, efektivitas bantuan ini seringkali terhambat oleh konflik yang sedang berlangsung dan pembatasan akses oleh pemerintah. Pada Juli 2019, duta besar PBB dari 37 negara, termasuk Sudan, telah menandatangani surat bersama kepada UNHRC yang membela perlakuan Tiongkok terhadap Uighur di wilayah Xinjiang.
Pada 23 Oktober 2020, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Sudan akan mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, menjadikannya negara Arab ketiga yang melakukannya sebagai bagian dari Perjanjian Abraham yang ditengahi AS. Pada 14 Desember Pemerintah AS menghapus Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme; sebagai bagian dari kesepakatan, Sudan setuju untuk membayar $335 juta sebagai kompensasi kepada para korban pemboman kedutaan tahun 1998.
Sengketa antara Sudan dan Ethiopia mengenai Bendungan Renaisans Besar Etiopia meningkat pada tahun 2021. Seorang penasihat pemimpin Sudan Abdel Fattah al-Burhan berbicara tentang perang air "yang akan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan". Pada Februari 2022, dilaporkan bahwa seorang utusan Sudan telah mengunjungi Israel untuk mempromosikan hubungan antar negara.
7. Militer

Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) adalah kekuatan reguler Sudan dan terbagi menjadi lima cabang: Angkatan Darat Sudan, Angkatan Laut Sudan (termasuk Korps Marinir), Angkatan Udara Sudan, Patroli Perbatasan, dan Angkatan Pertahanan Dalam Negeri, dengan total sekitar 200.000 pasukan. Militer Sudan telah menjadi kekuatan tempur yang dilengkapi dengan baik; hasil dari meningkatnya produksi lokal senjata berat dan canggih. Pasukan ini berada di bawah komando Majelis Nasional dan prinsip-prinsip strategisnya termasuk mempertahankan perbatasan luar Sudan dan menjaga keamanan dalam negeri.
Sejak krisis Darfur pada tahun 2004, menjaga pemerintah pusat dari perlawanan bersenjata dan pemberontakan kelompok-kelompok pemberontak paramiliter seperti Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA), Tentara Pembebasan Sudan (SLA), dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) telah menjadi prioritas penting. Meskipun tidak resmi, militer Sudan juga menggunakan milisi nomaden, yang paling menonjol adalah Janjaweed, dalam melaksanakan perang kontra-pemberontakan. Antara 200.000 dan 400.000 orang telah tewas dalam perjuangan kekerasan tersebut.
Peran milisi, khususnya Pasukan Dukungan Cepat (RSF), menjadi sangat signifikan. RSF, yang berasal dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam dalam konflik Darfur, secara resmi diakui dan diintegrasikan ke dalam aparat keamanan negara di bawah komando langsung presiden. RSF memiliki kekuatan tempur yang besar dan seringkali beroperasi dengan otonomi yang cukup tinggi. Keterlibatan RSF dalam konflik internal, termasuk penindasan protes pro-demokrasi pasca-2019, telah menuai banyak kritik. Persaingan dan ketegangan antara SAF dan RSF akhirnya memuncak menjadi perang saudara terbuka pada April 2023, yang menghancurkan negara dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Konflik ini menyoroti masalah mendasar dalam struktur keamanan Sudan, yaitu keberadaan kekuatan bersenjata paralel dengan loyalitas dan agenda yang berbeda.
8. Ekonomi

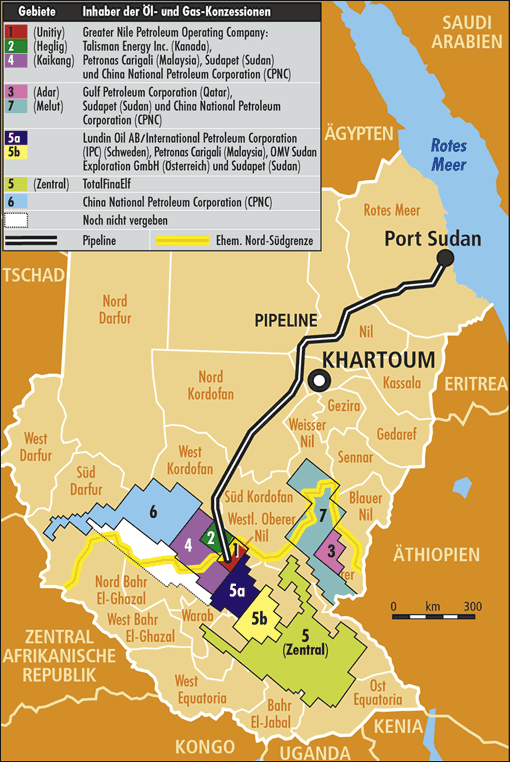

Struktur ekonomi Sudan secara historis sangat bergantung pada pertanian, yang mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dan menyumbang sebagian signifikan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penemuan dan eksploitasi minyak bumi sejak akhir 1990-an mengubah lanskap ekonomi negara, dengan minyak menjadi sumber pendapatan ekspor utama. Pemisahan diri Sudan Selatan pada tahun 2011, yang menguasai sekitar 75% cadangan minyak, memberikan pukulan berat bagi ekonomi Sudan, menyebabkan hilangnya pendapatan signifikan dan memicu stagflasi.
Indikator ekonomi utama seperti PDB, tingkat pertumbuhan, dan inflasi menunjukkan volatilitas yang tinggi, dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik, konflik internal, sanksi internasional, dan fluktuasi harga komoditas global. Tingkat pertumbuhan PDB melambat secara signifikan setelah kehilangan pendapatan minyak, dan inflasi tetap tinggi. Pada tahun 2010, Sudan dianggap sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat ke-17 di dunia dan perkembangan pesat negara itu sebagian besar berasal dari keuntungan minyak bahkan ketika menghadapi sanksi internasional dicatat oleh The New York Times dalam sebuah artikel tahun 2006. PDB Sudan turun dari US$123,053 miliar pada tahun 2017 menjadi US$40,852 miliar pada tahun 2018.
Proses pembangunan ekonomi terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang buruk, kurangnya investasi di sektor non-minyak, korupsi, dan tata kelola yang lemah. Kemiskinan tetap meluas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang terkena dampak konflik. Utang luar negeri juga menjadi beban berat bagi perekonomian. Sanksi internasional yang diberlakukan selama rezim al-Bashir semakin memperburuk situasi ekonomi, membatasi akses ke pasar keuangan global dan investasi asing. Meskipun beberapa sanksi dicabut setelah penggulingan al-Bashir, krisis politik yang berkelanjutan dan perang saudara pasca-2023 telah menghancurkan ekonomi lebih lanjut, menyebabkan hiperinflasi, kelangkaan barang-barang pokok, dan krisis kemanusiaan yang parah. Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Sudan adalah salah satu negara paling korup di dunia. Menurut Indeks Kelaparan Global tahun 2013, Sudan memiliki nilai indikator GHI sebesar 27,0 yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki 'Situasi Kelaparan yang Mengkhawatirkan'. Negara ini menduduki peringkat kelima sebagai negara paling lapar di dunia. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, Sudan menduduki peringkat ke-167 dalam pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa Sudan masih memiliki salah satu tingkat pembangunan manusia terendah di dunia. Pada tahun 2014, 45% penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari 3.2 USD per hari, naik dari 43% pada tahun 2009.
8.1. Tren dan Struktur Ekonomi
Situasi ekonomi makro Sudan ditandai oleh ketidakstabilan yang kronis, inflasi yang tinggi, dan ketergantungan pada sektor primer. Sebelum pemisahan Sudan Selatan pada 2011, minyak bumi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan sumber utama pendapatan ekspor. Namun, setelah kehilangan sebagian besar cadangan minyaknya ke Sudan Selatan, ekonomi Sudan mengalami kontraksi signifikan dan kesulitan neraca pembayaran.
Struktur industri utama masih didominasi oleh pertanian, yang menyerap sebagian besar tenaga kerja tetapi kontribusinya terhadap PDB relatif rendah dibandingkan potensinya. Sektor industri manufaktur kurang berkembang dan sebagian besar terbatas pada pengolahan produk pertanian dan barang konsumsi ringan. Sektor jasa, termasuk perdagangan dan layanan pemerintah, juga berkontribusi pada PDB.
Struktur perdagangan Sudan sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti emas (yang menjadi sumber devisa utama setelah minyak), produk pertanian (kapas, wijen, gom arab, ternak hidup), dan impor barang manufaktur, makanan, bahan bakar, dan mesin. Mitra dagang utama termasuk Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan beberapa negara Afrika.
Lingkungan investasi di Sudan dianggap berisiko tinggi karena ketidakpastian politik, tata kelola yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, dan kerangka hukum yang tidak stabil. Sanksi internasional yang diberlakukan selama bertahun-tahun juga telah menghambat investasi asing. Meskipun ada upaya untuk menarik investasi setelah pencabutan beberapa sanksi, konflik internal yang berkelanjutan, terutama perang saudara pasca-2023, telah menghancurkan kepercayaan investor dan merusak infrastruktur ekonomi lebih lanjut. Dampak ekonomi dari sanksi dan konflik sangat parah, menyebabkan kemiskinan yang meluas, pengangguran tinggi, kelangkaan barang-barang pokok, dan krisis kemanusiaan.
8.2. Industri Utama
Sektor industri inti Sudan masih terfokus pada beberapa bidang utama, dengan potensi pengembangan yang signifikan namun terhambat oleh berbagai tantangan. Dua sektor yang paling menonjol adalah pertanian dan sektor perminyakan serta pertambangan.
8.2.1. Pertanian
Pertanian secara historis merupakan tulang punggung ekonomi Sudan, mempekerjakan sekitar 80% tenaga kerja dan menyumbang sepertiga dari sektor ekonomi, meskipun produksi minyak mendorong sebagian besar pertumbuhan pasca-2000 Sudan. Tanaman pertanian utama meliputi:
- Kapas: Merupakan tanaman komersial penting, terutama jenis serat panjang yang diekspor. Proyek Gezira, salah satu skema irigasi terbesar di dunia, secara historis berfokus pada produksi kapas.
- Sorgum: Tanaman pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Sudan. Ditanam secara luas di berbagai kondisi agroklimat.
- Gom arab: Sudan adalah produsen dan pengekspor gom arab terbesar di dunia, yang berasal dari getah pohon akasia dan digunakan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi.
- Tanaman lain: Termasuk wijen (tanaman ekspor penting), kacang tanah, tebu, gandum, millet, serta buah-buahan dan sayuran.
Metode pertanian sebagian besar masih tradisional, meskipun ada upaya modernisasi di beberapa daerah. Fasilitas irigasi, terutama di sepanjang Sungai Nil dan anak-anak sungainya, sangat penting untuk produksi pertanian, mengingat sebagian besar wilayah negara ini kering atau semi-kering. Kebijakan pertanian pemerintah berfokus pada peningkatan produksi pangan dan komoditas ekspor, namun seringkali terhambat oleh kurangnya investasi, infrastruktur yang buruk, akses terbatas ke kredit dan input pertanian, serta dampak perubahan iklim (kekeringan dan banjir). Masalah ketahanan pangan tetap menjadi tantangan serius, diperburuk oleh konflik internal, pengungsian, dan kenaikan harga pangan global.
8.2.2. Perminyakan dan Pertambangan
Sektor perminyakan menjadi pendorong utama ekonomi Sudan sejak akhir 1990-an hingga pemisahan Sudan Selatan pada 2011.
- Minyak Bumi: Sebelum pemisahan, Sudan memiliki cadangan minyak yang signifikan. Setelah 2011, sebagian besar cadangan dan produksi minyak beralih ke Sudan Selatan, menyebabkan penurunan drastis pendapatan minyak bagi Sudan. Sudan masih memiliki beberapa ladang minyak dan fasilitas pengolahan, serta infrastruktur pipa untuk mengekspor minyak Sudan Selatan melalui Port Sudan. Produksi minyak meningkat secara dramatis selama akhir 2000-an. Dengan meningkatnya pendapatan minyak, ekonomi Sudan berkembang pesat, dengan tingkat pertumbuhan sekitar sembilan persen pada tahun 2007. Kemerdekaan Sudan Selatan yang kaya minyak, bagaimanapun, menempatkan sebagian besar ladang minyak utama di luar kendali langsung pemerintah Sudan dan produksi minyak di Sudan turun dari sekitar 450.000 barel per hari menjadi di bawah 60.000 barel per hari. Produksi sejak itu pulih menjadi sekitar 250.000 barel per hari untuk 2014-15. Untuk mengekspor minyak, Sudan Selatan bergantung pada pipa ke Port Sudan di pantai Laut Merah Sudan, karena Sudan Selatan adalah negara terkurung daratan, serta fasilitas penyulingan minyak di Sudan. Pada Agustus 2012, Sudan dan Sudan Selatan menyetujui kesepakatan untuk mengangkut minyak Sudan Selatan melalui pipa Sudan ke Port Sudan.
- Pertambangan (Emas dan Mineral Lainnya): Setelah kehilangan sebagian besar pendapatan minyak, sektor pertambangan, terutama emas, menjadi sumber devisa yang semakin penting. Sudan memiliki cadangan emas yang cukup besar, dan penambangan emas, baik formal maupun artisanal, telah meningkat pesat. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan terkait regulasi, dampak lingkungan, dan konflik atas sumber daya. Mineral lain yang ada termasuk kromit, bijih besi, mangan, dan gipsum, meskipun eksploitasinya masih terbatas.
Dampak ekonomi dari sektor perminyakan dan pertambangan signifikan, tetapi juga seringkali menjadi sumber konflik, terutama di daerah-daerah di mana sumber daya ini ditemukan. Persaingan atas kontrol sumber daya dan pembagian pendapatan telah berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata di beberapa wilayah.
8.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sudan memiliki sekitar 25-30 universitas; pengajaran utamanya dalam bahasa Arab atau Inggris. Pendidikan di tingkat menengah dan universitas telah sangat terhambat oleh persyaratan bahwa sebagian besar pria harus melakukan dinas militer sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, "Islamisasi" yang didorong oleh presiden Al-Bashir mengasingkan banyak peneliti. Bahasa pengantar resmi di universitas diubah dari Inggris menjadi Arab dan mata kuliah Islam menjadi wajib. Pendanaan sains internal menyusut. Menurut UNESCO, lebih dari 3.000 peneliti Sudan meninggalkan negara itu antara tahun 2002 dan 2014. Pada tahun 2013, negara itu hanya memiliki 19 peneliti untuk setiap 100.000 warga, atau 1/30 rasio Mesir, menurut Pusat Penelitian Nasional Sudan. Pada tahun 2015, Sudan hanya menerbitkan sekitar 500 makalah ilmiah. Sebagai perbandingan, Polandia, negara dengan ukuran populasi yang sama, menerbitkan sekitar 10.000 makalah per tahun.
Program Luar Angkasa Nasional Sudan telah menghasilkan beberapa satelit CubeSat, dan memiliki rencana untuk memproduksi satelit komunikasi Sudan (SUDASAT-1) dan satelit penginderaan jauh Sudan (SRSS-1). Pemerintah Sudan berkontribusi pada kumpulan penawaran untuk Satelit survei darat sektor swasta yang beroperasi di atas Sudan, Arabsat 6A, yang berhasil diluncurkan pada 11 April 2019, dari Kennedy Space Center. Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir menyerukan Badan Antariksa Afrika pada tahun 2012, tetapi rencana tersebut tidak pernah final.
9. Masyarakat
Masyarakat Sudan sangat beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, dan budaya, yang seringkali menjadi sumber kekayaan sekaligus ketegangan. Struktur sosial tradisional, termasuk loyalitas suku dan klan, masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan politik. Konflik etnis telah menjadi masalah yang berulang, seringkali diperburuk oleh persaingan atas sumber daya seperti tanah dan air, serta manipulasi politik. Masalah integrasi sosial menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya membangun identitas nasional yang inklusif yang dapat mengakomodasi keragaman negara. Perbedaan antara wilayah utara yang didominasi Arab-Muslim dan wilayah-wilayah lain dengan populasi non-Arab atau non-Muslim telah menjadi garis patahan utama dalam sejarah Sudan. Perang saudara yang berkepanjangan dan konflik internal lainnya telah menyebabkan perpecahan sosial yang mendalam, pengungsian massal, dan trauma kolektif. Upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali kohesi sosial menjadi krusial bagi masa depan Sudan.
9.1. Hak Asasi Manusia

Situasi hak asasi manusia (HAM) di Sudan secara umum sangat memprihatinkan dan telah menjadi subjek kecaman internasional selama bertahun-tahun. Pelanggaran HAM terjadi secara luas, terutama di daerah-daerah konflik seperti Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru, serta selama periode penindasan politik oleh rezim otoriter. Sejak 1983, kombinasi perang saudara dan kelaparan telah merenggut nyawa hampir dua juta orang di Sudan. Diperkirakan sebanyak 200.000 orang telah diperbudak selama Perang Saudara Sudan Kedua.
Masalah HAM utama meliputi:
- Hak-hak Perempuan: Perempuan di Sudan menghadapi diskriminasi sistemik dalam hukum dan praktik. Mutilasi genital perempuan (FGM) masih tersebar luas, meskipun telah dikriminalisasi pada tahun 2020. Menurut laporan UNICEF tahun 2013, 88% perempuan di Sudan telah menjalani FGM. Undang-undang Status Pribadi Sudan tentang perkawinan telah dikritik karena membatasi hak-hak perempuan dan mengizinkan perkawinan anak. Bukti menunjukkan bahwa dukungan untuk mutilasi genital perempuan tetap tinggi, terutama di kalangan pedesaan dan kelompok berpendidikan rendah, meskipun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, sering tidak dilaporkan dan jarang dituntut.
- Hak-hak Anak: Anak-anak sangat rentan terhadap dampak konflik, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Penggunaan tentara anak oleh berbagai kelompok bersenjata merupakan masalah serius. Pernikahan anak juga masih terjadi.
- Hak-hak Minoritas: Minoritas etnis dan agama sering menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Muslim yang berpindah agama ke Kristen dapat menghadapi hukuman mati karena murtad. Kelompok non-Arab di daerah konflik sering menjadi target kekerasan dan pengusiran.
- Tahanan Politik dan Kebebasan Sipil: Penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap aktivis politik, pembela HAM, jurnalis, dan pengunjuk rasa merupakan praktik umum, terutama di bawah rezim otoriter. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat sangat dibatasi.
- Pelanggaran HAM di Daerah Konflik: Di daerah seperti Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru, serta selama perang saudara pasca-2023, terjadi pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan di luar hukum, serangan terhadap warga sipil, pemindahan paksa, penghancuran properti, dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.
Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM seringkali tidak memadai atau tidak ada sama sekali. Komunitas internasional, termasuk PBB dan organisasi HAM, terus menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran HAM dan reformasi sektor keamanan dan peradilan. Meskipun ada beberapa kemajuan setelah revolusi 2019, kudeta militer dan perang saudara telah menyebabkan kemunduran signifikan dalam situasi HAM.
9.1.1. Konflik Darfur dan Masalah Hak Asasi Manusia
Surat tanggal 14 Agustus 2006 dari direktur eksekutif Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah Sudan tidak mampu melindungi warganya sendiri di Darfur dan tidak mau melakukannya, dan bahwa milisinya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat itu menambahkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini telah ada sejak tahun 2004. Beberapa laporan mengaitkan sebagian pelanggaran tersebut dengan para pemberontak serta pemerintah dan Janjaweed. Laporan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS yang dikeluarkan pada Maret 2007 mengklaim bahwa "[s]emua pihak dalam konflik melakukan pelanggaran serius, termasuk pembunuhan warga sipil secara luas, pemerkosaan sebagai alat perang, penyiksaan sistematis, perampokan, dan perekrutan tentara anak-anak."
Lebih dari 2,8 juta warga sipil telah mengungsi dan jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 300.000 orang. Baik pasukan pemerintah maupun milisi yang bersekutu dengan pemerintah diketahui menyerang tidak hanya warga sipil di Darfur, tetapi juga pekerja kemanusiaan. Simpatisan kelompok pemberontak ditahan secara sewenang-wenang, begitu pula jurnalis asing, pembela hak asasi manusia, aktivis mahasiswa, dan pengungsi di dalam dan sekitar Khartoum, beberapa di antaranya menghadapi penyiksaan. Kelompok pemberontak juga dituduh dalam laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS menyerang pekerja kemanusiaan dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Menurut UNICEF, pada tahun 2008, terdapat sebanyak 6.000 tentara anak-anak di Darfur.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Human Rights Watch pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa Sudan tidak melakukan upaya berarti untuk memberikan akuntabilitas atas pelanggaran di masa lalu dan saat ini. Laporan tersebut mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Darfur, Kordofan selatan, dan Nil Biru. Selama tahun 2018, Badan Intelijen dan Keamanan Nasional (NISS) menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan protes dan menahan puluhan aktivis dan anggota oposisi. Selain itu, pasukan Sudan memblokir Operasi Hibrida Uni Afrika-Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan bantuan internasional lainnya untuk mengakses orang-orang yang mengungsi dan daerah-daerah yang dilanda konflik di Darfur.
9.1.2. Kebebasan Pers
Di bawah pemerintahan Omar al-Bashir (1989-2019), media Sudan diberi sedikit kebebasan dalam pemberitaannya. Pada tahun 2014, peringkat kebebasan pers Reporters Without Borders menempatkan Sudan di urutan ke-172 dari 180 negara. Setelah penggulingan al-Bashir pada tahun 2019, ada periode singkat di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin sipil di mana ada beberapa kebebasan pers. Namun, para pemimpin kudeta 2021 dengan cepat membatalkan perubahan ini. "Sektor ini sangat terpolarisasi", kata Reporters Without Borders dalam ringkasan kebebasan pers tahun 2023 di negara itu. "Kritikus jurnalistik telah ditangkap, dan internet secara teratur dimatikan untuk memblokir arus informasi." Penindasan tambahan terjadi setelah dimulainya perang saudara Sudan tahun 2023.
Lingkungan media di Sudan secara historis sangat terkekang, dengan tingkat kontrol pemerintah yang tinggi terhadap konten berita dan operasi media. Selama rezim Omar al-Bashir, sensor, intimidasi, penangkapan, dan penutupan media independen atau kritis menjadi hal biasa. Jurnalis sering menghadapi ancaman, pelecehan, dan tuntutan hukum yang dibuat-buat.
Setelah revolusi 2019, ada periode singkat pelonggaran pembatasan dan harapan akan kebebasan pers yang lebih besar. Namun, kudeta militer tahun 2021 dan perang saudara pasca-2023 telah menyebabkan kemunduran signifikan. Pihak berwenang kembali meningkatkan kontrol atas media, membatasi akses informasi, dan menargetkan jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau kritis terhadap pemerintah atau faksi-faksi yang bertikai. Pemadaman internet dan telekomunikasi juga sering digunakan untuk menghalangi aliran informasi, terutama selama periode protes atau eskalasi konflik. Situasi ini sangat menghambat kemampuan media untuk beroperasi secara independen dan menyediakan informasi yang akurat dan objektif kepada publik, serta meningkatkan risiko bagi jurnalis yang berupaya menjalankan profesinya.
9.2. Ketertiban Umum dan Keamanan
Situasi ketertiban umum dan keamanan di Sudan sangat rapuh dan telah memburuk secara signifikan akibat perang saudara yang meletus pada April 2023. Tingkat kriminalitas umum, seperti perampokan dan pencurian, meningkat di banyak daerah, terutama di perkotaan, diperburuk oleh krisis ekonomi dan runtuhnya layanan keamanan di beberapa wilayah.
Upaya pemeliharaan keamanan oleh aparat negara seringkali tidak efektif dan diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia. Polisi dan pasukan keamanan lainnya sering dituduh menggunakan kekuatan berlebihan, melakukan penangkapan sewenang-wenang, dan terlibat dalam korupsi. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh berbagai faksi bersenjata, warga sipil seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan menjadi sasaran kekerasan.
Ketidakamanan akibat perang saudara dan konflik internal lainnya sangat parah. Pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, pengungsian massal, dan kekosongan keamanan di banyak wilayah. Kelompok-kelompok bersenjata lain dan milisi etnis juga mengambil keuntungan dari situasi ini, meningkatkan serangan dan memperburuk ketidakstabilan. Warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, dan penculikan. Akses bantuan kemanusiaan sering terhambat oleh pertempuran dan blokade, memperburuk kondisi kemanusiaan. Secara keseluruhan, ketertiban umum dan keamanan di Sudan berada dalam kondisi krisis, dengan dampak yang menghancurkan bagi kehidupan jutaan orang.
9.3. Masalah Kelaparan dan Kemiskinan
Sudan menghadapi krisis kelaparan dan kemiskinan yang parah dan semakin memburuk, terutama akibat konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Situasi ketahanan pangan di negara ini sangat genting, dengan jutaan orang tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi.
Prevalensi kelaparan dan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak, sangat tinggi. Konflik internal, seperti perang saudara yang meletus pada tahun 2023, telah menghancurkan produksi pertanian, mengganggu pasar, dan menghalangi akses bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Pengungsian massal akibat konflik juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan.
Tingkat kemiskinan di Sudan sangat tinggi, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis ekonomi, termasuk inflasi yang melonjak dan devaluasi mata uang, semakin memperburuk daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Upaya bantuan domestik dan internasional terus dilakukan untuk mengatasi krisis kelaparan dan kemiskinan. Organisasi seperti Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF, dan berbagai LSM menyediakan bantuan pangan, dukungan nutrisi, dan program mata pencaharian. Namun, skala kebutuhan seringkali jauh melebihi kapasitas bantuan yang tersedia, dan akses ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik seringkali menjadi tantangan besar. Sebagai akibat dari perang, Program Pangan Dunia merilis laporan pada 22 Februari 2024 yang menyatakan bahwa lebih dari 95% populasi Sudan tidak mampu membeli makanan sehari-hari. Penyelesaian konflik, pemulihan ekonomi, dan investasi jangka panjang dalam pertanian berkelanjutan dan jaring pengaman sosial sangat penting untuk mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan yang mendalam di Sudan.
10. Kependudukan
Populasi Sudan diperkirakan sekitar 50 juta jiwa pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi, meskipun angka pastinya sulit diperoleh karena kurangnya sensus terbaru yang komprehensif dan dampak konflik yang menyebabkan pengungsian besar-besaran. Distribusi penduduk tidak merata, dengan konsentrasi terbesar di sepanjang Lembah Sungai Nil, terutama di sekitar ibu kota Khartoum, serta di beberapa daerah pertanian yang subur. Wilayah gurun di utara dan daerah-daerah yang dilanda konflik memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Karakteristik demografis Sudan mencerminkan negara dengan populasi muda, dengan persentase anak-anak dan remaja yang tinggi. Tingkat urbanisasi meningkat, dengan semakin banyak orang pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk mencari peluang ekonomi dan keamanan, meskipun proses ini seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan layanan dan infrastruktur yang memadai.
10.1. Statistik Kependudukan
Indikator kependudukan utama Sudan menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi negara ini. Tingkat kelahiran relatif tinggi, sementara tingkat kematian juga cukup tinggi, terutama angka kematian bayi dan anak-anak, meskipun ada beberapa perbaikan dalam beberapa dekade terakhir sebelum eskalasi konflik terbaru. Harapan hidup rata-rata lebih rendah dibandingkan standar global.
Kepadatan penduduk bervariasi secara signifikan di seluruh negeri, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah perkotaan seperti Khartoum dan di sepanjang Lembah Nil. Tingkat urbanisasi terus meningkat, tetapi banyak penduduk perkotaan tinggal di permukiman informal dengan akses terbatas ke layanan dasar.
Status pengungsi dan pengungsi internal (IDP) merupakan aspek penting dari demografi Sudan. Negara ini telah lama menjadi tuan rumah bagi pengungsi dari negara tetangga seperti Eritrea, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Selain itu, konflik internal yang berkepanjangan, terutama di Darfur, Kordofan Selatan, Nil Biru, dan perang saudara pasca-2023, telah menyebabkan jutaan warga Sudan mengungsi di dalam negeri (IDP) atau mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Krisis pengungsian ini memberikan tekanan besar pada sumber daya dan layanan sosial, serta menciptakan tantangan kemanusiaan yang kompleks. Data statistik kependudukan yang akurat dan terkini seringkali sulit diperoleh karena ketidakstabilan dan kurangnya kapasitas pengumpulan data yang komprehensif.
10.2. Kelompok Etnis

Sudan adalah negara dengan keragaman etnis yang sangat tinggi, terdiri dari ratusan kelompok etnis dan sub-kelompok dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Kelompok etnis utama meliputi:
- Arab Sudan: Merupakan kelompok etnis terbesar, diperkirakan sekitar 70% dari total populasi. Mereka sebagian besar adalah Muslim dan berbicara dialek Arab Sudan. Namun, identitas "Arab" di Sudan lebih bersifat budaya dan linguistik daripada genetik murni, karena banyak kelompok ini adalah hasil dari perkawinan campuran selama berabad-abad antara migran Arab dan penduduk asli Afrika. Mereka terkonsentrasi terutama di wilayah utara dan tengah Sudan. Beberapa suku Arab utama termasuk Ja'alin, Shaigiya, dan Baggara (meskipun beberapa Baggara juga memiliki identitas non-Arab yang kuat).
- Beja: Kelompok etnis semi-nomaden yang mendiami wilayah timur Sudan, terutama di sepanjang pantai Laut Merah dan perbukitan di sekitarnya. Mereka memiliki bahasa dan budaya Kushitik yang khas.
- Fur: Kelompok etnis non-Arab terbesar di Darfur, yang memberi nama pada wilayah tersebut. Mereka secara tradisional adalah petani dan memiliki kesultanan historis mereka sendiri.
- Nuba: Istilah kolektif untuk berbagai kelompok etnis yang mendiami Pegunungan Nuba di Kordofan Selatan. Mereka memiliki beragam bahasa dan tradisi budaya, dan banyak di antaranya telah memeluk Kristen atau mempertahankan kepercayaan adat, meskipun Islam juga tersebar luas.
- Kelompok Lainnya: Termasuk berbagai kelompok Nilotik di selatan yang berbatasan dengan Sudan Selatan (meskipun sebagian besar kini berada di Sudan Selatan), kelompok-kelompok seperti orang Masalit, orang Zaghawa di Darfur, serta berbagai kelompok etnis yang lebih kecil di seluruh negeri seperti orang Hausa, orang Fulani, Nubia (yang berbeda dari Arab Nubia), dan Koptik.
Distribusi kelompok etnis seringkali terkait dengan wilayah geografis tertentu. Budaya masing-masing kelompok sangat beragam, mencakup tradisi, adat istiadat, seni, dan struktur sosial yang unik. Status sosial kelompok etnis dapat bervariasi, dan diskriminasi berdasarkan etnisitas telah menjadi masalah serius. Hubungan antar-etnis seringkali kompleks, ditandai oleh periode koeksistensi damai maupun konflik, terutama terkait persaingan atas sumber daya dan representasi politik. Isu etnisitas memainkan peran penting dalam politik dan konflik di Sudan.
10.3. Bahasa
Sudan adalah negara multibahasa dengan sekitar 70 bahasa asli yang digunakan.
- Bahasa Resmi: Bahasa Arab (khususnya dialek Arab Sudan) dan Bahasa Inggris adalah bahasa resmi negara menurut konstitusi 2005. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan sebagai lingua franca di sebagian besar wilayah negara. Bahasa Inggris juga digunakan dalam pendidikan tinggi dan dalam beberapa konteks resmi, meskipun penggunaannya kurang merata.
- Bahasa-Bahasa Regional Utama: Selain bahasa Arab, terdapat banyak bahasa regional dan bahasa minoritas etnis yang penting. Di antaranya adalah:
- Bahasa-bahasa Nubia: Digunakan oleh kelompok Nubia di sepanjang Sungai Nil di utara.
- Bahasa Beja (Bedawiyet): Digunakan oleh kelompok Beja di timur Sudan.
- Bahasa Fur: Digunakan oleh kelompok Fur di Darfur.
- Bahasa-bahasa Nuba: Berbagai bahasa yang digunakan oleh kelompok Nuba di Pegunungan Nuba.
- Bahasa Dinka, Nuer, Shilluk: Meskipun mayoritas penuturnya kini berada di Sudan Selatan, masih ada komunitas penutur di wilayah perbatasan Sudan.
- Bahasa Hausa dan Fulfulde: Digunakan oleh komunitas Hausa dan Fulani yang tersebar.
- Bahasa Isyarat: Sudan memiliki beberapa bahasa isyarat regional, yang tidak saling dipahami. Sebuah usulan tahun 2009 untuk Bahasa Isyarat Sudan yang terpadu telah dikerjakan.
Penggunaan bahasa-bahasa minoritas seringkali terbatas pada komunitas lokal dan kurang mendapat dukungan resmi dalam pendidikan atau media. Tingkat melek huruf di Sudan adalah 70,2% dari total populasi (pria: 79,6%, wanita: 60,8%). Upaya untuk mempromosikan dan melestarikan keragaman bahasa di Sudan menghadapi tantangan akibat dominasi bahasa Arab dan dampak konflik internal.
10.4. Agama


Agama utama di Sudan adalah Islam, yang dianut oleh lebih dari 90,7% populasi pada saat perpecahan tahun 2011 yang memisahkan Sudan Selatan. Mayoritas Muslim di Sudan adalah Islam Sunni, dengan pengaruh kuat dari berbagai tarekat Sufi seperti Ansar dan Khatmia. Tarekat-tarekat ini secara tradisional memiliki hubungan dengan partai-partai politik tertentu, misalnya Ansar dengan Partai Umma dan Khatmia dengan Partai Persatuan Demokrat (DUP). Salafisme juga memiliki pengikut. Hanya wilayah Darfur yang secara tradisional tidak memiliki persaudaraan Sufi yang umum di bagian lain negara itu.
Kekristenan merupakan agama minoritas terbesar, mencakup sekitar 5,4% populasi. Kelompok Kristen yang telah lama ada termasuk Kristen Koptik Ortodoks dan Kristen Ortodoks Yunani, terutama di Khartoum dan kota-kota utara lainnya. Komunitas Ortodoks Ethiopia dan Ortodoks Eritrea juga ada, sebagian besar terdiri dari pengungsi dan migran dari beberapa dekade terakhir. Gereja Apostolik Armenia juga memiliki kehadiran yang melayani orang Sudan-Armenia. Gereja Presbiterian Injili Sudan juga memiliki anggota. Selain itu, terdapat berbagai denominasi Protestan dan Katolik Roma.
Kepercayaan adat Afrika juga masih dianut oleh sebagian kecil populasi, terutama di beberapa daerah pedesaan dan di antara kelompok-kelompok etnis tertentu yang belum sepenuhnya terasimilasi ke dalam Islam atau Kristen.
Identitas agama memainkan peran penting dalam politik dan masyarakat Sudan. Dominasi Islam dalam sistem politik dan hukum telah menjadi sumber ketegangan dan konflik, terutama dengan populasi non-Muslim di Sudan Selatan (sebelum kemerdekaan) dan di wilayah-wilayah seperti Pegunungan Nuba dan Nil Biru. Masalah kebebasan beragama menjadi isu penting, dengan laporan diskriminasi dan pembatasan terhadap minoritas agama. Meskipun ada upaya reformasi hukum setelah revolusi 2019 untuk memisahkan agama dan negara, implementasi dan penerimaan sosialnya masih menghadapi tantangan.
10.5. Kota-kota Utama
Sudan memiliki beberapa kota utama yang menjadi pusat populasi, ekonomi, dan budaya.
- Khartoum: Ibu kota Sudan dan kota terbesar. Terletak di pertemuan Nil Biru dan Nil Putih, Khartoum adalah pusat politik, administrasi, komersial, dan pendidikan negara. Populasinya, bersama dengan kota-kota tetangganya, Omdurman dan Khartoum Utara (Bahri), membentuk wilayah metropolitan yang padat penduduk, sering disebut sebagai "Tiga Kota Kembar". Peran ekonominya sangat signifikan sebagai pusat perdagangan, industri ringan, dan jasa keuangan. Khartoum juga memiliki banyak universitas, museum, dan institusi budaya.
- Omdurman: Terletak di seberang Sungai Nil Putih dari Khartoum, Omdurman adalah kota terbesar kedua dan secara historis merupakan pusat keagamaan dan budaya penting, terutama terkait dengan gerakan Mahdist. Kota ini memiliki pasar tradisional yang ramai (souq) dan merupakan pusat kerajinan tangan.
- Khartoum Utara (Bahri): Terletak di sebelah utara Nil Biru dari Khartoum, Bahri adalah pusat industri penting dengan banyak pabrik dan kawasan industri. Bersama Khartoum dan Omdurman, ia membentuk inti perkotaan Sudan.
- Port Sudan: Kota pelabuhan utama Sudan di Laut Merah. Port Sudan adalah gerbang utama perdagangan internasional negara, menangani sebagian besar impor dan ekspor. Kota ini juga merupakan pusat pariwisata potensial karena terumbu karangnya.
- Kassala: Kota penting di timur Sudan, dekat perbatasan dengan Eritrea. Kassala adalah pusat pertanian dan perdagangan regional, terkenal dengan kebun buah-buahan dan Pegunungan Taka yang ikonik.
- El-Obeid: Kota terbesar di wilayah Kordofan dan pusat perdagangan penting untuk produk pertanian seperti gom arab, kacang tanah, dan wijen. El-Obeid juga merupakan pusat transportasi regional.
- Wad Madani: Terletak di selatan Khartoum, Wad Madani adalah ibu kota negara bagian Al Jazirah dan pusat Proyek Irigasi Gezira yang terkenal, salah satu skema irigasi terbesar di dunia yang berfokus pada produksi kapas dan tanaman lainnya.
Kota-kota ini memainkan peran penting dalam ekonomi dan kehidupan sosial Sudan, meskipun banyak di antaranya juga menghadapi tantangan terkait urbanisasi yang cepat, infrastruktur yang tidak memadai, dan dampak konflik.
10.6. Kesehatan
Sistem kesehatan Sudan menghadapi tantangan besar akibat kemiskinan, konflik berkepanjangan, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya manusia serta keuangan. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang dilanda konflik. Harapan hidup Sudan adalah 65,1 tahun menurut data terbaru untuk tahun 2019 dari macrotrends.net. Angka kematian bayi pada tahun 2016 adalah 44,8 per 1.000.
Penyakit utama yang menjadi masalah kesehatan masyarakat meliputi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, penyakit diare, dan infeksi saluran pernapasan akut. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker juga semakin meningkat. Wabah penyakit seperti kolera dan campak sering terjadi, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan cakupan vaksinasi rendah.
Status gizi penduduk, terutama anak-anak dan perempuan, seringkali buruk. Malnutrisi kronis dan akut tersebar luas, diperburuk oleh kekurangan pangan, praktik pemberian makan yang tidak tepat, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
Harapan hidup di Sudan relatif rendah, dan angka kematian bayi serta ibu masih tinggi dibandingkan dengan standar global. Konflik internal dan perang saudara pasca-2023 telah menghancurkan sistem kesehatan lebih lanjut, dengan banyak fasilitas kesehatan rusak atau hancur, petugas kesehatan mengungsi, dan pasokan obat-obatan serta peralatan medis terganggu. Upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat menghadapi banyak kendala, termasuk pendanaan yang tidak memadai, kurangnya tenaga kesehatan terlatih (terutama di daerah terpencil), dan ketidakstabilan politik yang menghambat perencanaan dan implementasi program kesehatan jangka panjang. UNICEF memperkirakan bahwa 87% perempuan Sudan berusia antara 15 dan 49 tahun telah menjalani mutilasi genital perempuan.
10.7. Pendidikan

Sistem pendidikan di Sudan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas pengajaran yang bervariasi, dan dampak konflik serta ketidakstabilan politik. Pendidikan di Sudan gratis dan wajib bagi anak-anak berusia 6 hingga 13 tahun, meskipun lebih dari 40% anak-anak tidak bersekolah karena situasi ekonomi. Faktor lingkungan dan sosial juga meningkatkan kesulitan untuk bersekolah, terutama bagi anak perempuan.
- Struktur Sekolah: Sistem pendidikan formal umumnya terdiri dari pendidikan dasar (8 tahun), diikuti oleh pendidikan menengah (3 tahun). Tangga pendidikan sebelumnya 6 + 3 + 3 diubah pada tahun 1990. Bahasa pengantar utama di semua tingkatan adalah bahasa Arab.
- Tingkat Melek Huruf: Tingkat melek huruf secara keseluruhan adalah 70,2% dari total populasi, dengan perbedaan antara laki-laki (79,6%) dan perempuan (60,8%). Upaya untuk meningkatkan melek huruf terus dilakukan, tetapi menghadapi kendala terutama di daerah pedesaan dan di antara kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
- Aksesibilitas Pendidikan: Akses terhadap pendidikan tidak merata di seluruh negeri. Sekolah-sekolah terkonsentrasi di daerah perkotaan; banyak di antaranya di wilayah barat telah rusak atau hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Anak-anak di daerah pedesaan, daerah konflik, dan dari keluarga miskin seringkali memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali ke pendidikan. Anak perempuan juga menghadapi hambatan budaya dan ekonomi yang lebih besar dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Pada tahun 2001 Bank Dunia memperkirakan bahwa pendaftaran sekolah dasar adalah 46 persen dari siswa yang memenuhi syarat dan 21 persen dari siswa sekolah menengah. Pendaftaran sangat bervariasi, turun di bawah 20 persen di beberapa provinsi.
- Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan seringkali menjadi perhatian, dengan kurangnya guru terlatih, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan, dan fasilitas belajar yang tidak memadai.
- Masalah Sosial Terkait Pendidikan dan Upaya Perbaikan: Konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan infrastruktur pendidikan di banyak wilayah dan menyebabkan pengungsian guru serta siswa. Kemiskinan juga memaksa banyak anak putus sekolah untuk bekerja. Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, dan pembangunan kembali sekolah di daerah yang terkena dampak konflik, seringkali dengan dukungan dari organisasi internasional. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar.
11. Budaya
Budaya Sudan merupakan perpaduan yang kaya dari perilaku, praktik, dan kepercayaan sekitar 578 kelompok etnis, yang berkomunikasi dalam berbagai dialek dan bahasa yang berbeda, di wilayah yang merupakan mikrokosmos Afrika, dengan kondisi geografis ekstrem yang bervariasi dari gurun pasir hingga hutan tropis. Bukti terbaru menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar warga negara ini sangat mengidentifikasi diri dengan Sudan dan agama mereka, identitas supranasional Arab dan Afrika jauh lebih mempolarisasi dan diperdebatkan. Musik, tarian, sastra lisan, dan kerajinan tangan memainkan peran penting dalam ekspresi budaya. Pengaruh Islam Arab sangat kuat, terutama di wilayah utara dan tengah, yang tercermin dalam arsitektur, kaligrafi, dan praktik keagamaan. Namun, tradisi-tradisi Afrika pra-Islam juga tetap bertahan dan berakulturasi dengan budaya Islam, menciptakan sinkretisme yang unik. Nilai-nilai seperti keramahan, solidaritas komunitas, dan penghormatan terhadap orang tua sangat dijunjung tinggi.
11.1. Tradisi dan Gaya Hidup

Kehidupan sehari-hari di Sudan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pakaian tradisional masih banyak dikenakan. Untuk pria, pakaian yang umum adalah jalabiya, yaitu jubah longgar berwarna putih atau berwarna, berlengan panjang, tanpa kerah, dan panjangnya hingga mata kaki, yang juga umum di Mesir. Jalabiya sering disertai dengan serban besar dan syal, dan pakaian tersebut dapat berwarna putih, berwarna, bergaris-garis, dan terbuat dari kain dengan ketebalan yang bervariasi, tergantung pada musim dan preferensi pribadi.
Pakaian yang paling umum untuk wanita Sudan adalah thobe atau thawb, diucapkan tobe dalam dialek Sudan. Thobe adalah selembar kain panjang berwarna putih atau berwarna-warni yang dililitkan oleh wanita di atas pakaian dalam mereka, biasanya menutupi kepala dan rambut mereka.
Karena hukum pidana tahun 1991 (Hukum Ketertiban Umum), wanita tidak diizinkan mengenakan celana panjang di depan umum, karena dianggap sebagai "pakaian tidak senonoh". Hukuman karena mengenakan celana panjang bisa mencapai 40 cambukan, tetapi setelah dinyatakan bersalah pada tahun 2009, seorang wanita didenda setara dengan 200 dolar AS sebagai gantinya.
Adat istiadat terkait peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian sangat dijaga. Pernikahan seringkali melibatkan perayaan besar dengan musik, tarian, dan makanan tradisional, serta prosesi yang rumit. Solidaritas keluarga dan komunitas sangat kuat, dengan jaringan dukungan sosial yang erat. Keramahan adalah nilai penting, dan tamu seringkali disambut dengan hangat dan dijamu dengan murah hati. Kehidupan sehari-hari juga dipengaruhi oleh ritme ibadah bagi mayoritas Muslim. Norma sosial menekankan pada kesopanan, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, dan pemisahan gender dalam beberapa konteks sosial. Meskipun modernisasi membawa perubahan, banyak aspek tradisional gaya hidup Sudan tetap bertahan dan menjadi bagian integral dari identitas budaya.
11.2. Kuliner

Masakan Sudan sangat dipengaruhi oleh masakan Mesir. Keduanya berbagi hidangan seperti falafel (tamiya), yang dibuat dengan buncis di Sudan, bukan kacang fava seperti di Mesir; ful medames, hidangan nasional Sudan dan Mesir; molokhia, sup kental yang terbuat dari daun rebus; kamounia, sup hati daging yang dimakan di Sudan, Mesir, dan Tunisia; serta hidangan penutup seperti umm ali dan basbousa. Jibna bayda, keju putih lembut, juga dimakan.
Makanan khas Sudan lainnya antara lain elmaraara dan umfitit, yaitu masakan yang terbuat dari jeroan domba (termasuk paru-paru, hati, dan lambung), bawang bombay, selai kacang, dan garam. Makanan ini dimakan mentah. Salad kacang yang disebut salatat dakwa juga disantap. Terdapat juga berbagai jenis semur (stew) seperti waika, bussaara, dan sabaroag, yang menggunakan ni'aimiya (campuran bumbu Sudan) dan okra kering. Miris adalah sup yang terbuat dari lemak domba, bawang bombay, dan okra kering. Abiyad terbuat dari daging kering, sedangkan kajaik terbuat dari ikan kering.
Roti pipih seperti kisra (roti tipis dari tepung sorgum) dan gurasa (roti gandum tebal) adalah makanan pokok. Hidangan berbahan dasar sorgum dan millet umum di banyak daerah. Daging, terutama domba dan kambing, serta ayam, seringkali disajikan dengan berbagai cara, baik dipanggang, direbus, atau digoreng. Penggunaan bumbu dan rempah-rempah memberikan cita rasa khas pada masakan Sudan. Minuman populer termasuk teh (seringkali disajikan dengan banyak gula), kopi (jabana), dan berbagai jus buah segar. Etiket makan menekankan pada berbagi makanan dan makan bersama dari satu nampan besar, terutama dalam acara-acara sosial dan keluarga.
11.3. Seni
Seni di Sudan mencerminkan perpaduan pengaruh budaya Afrika dan Arab-Islam, serta pengalaman sejarah negara tersebut. Seni tradisional mencakup kerajinan tangan seperti tembikar, anyaman (keranjang, tikar), ukiran kayu, dan perhiasan yang seringkali memiliki pola geometris dan simbolis yang khas. Lukisan tubuh dengan henna (pacar) juga merupakan bentuk seni tradisional yang populer di kalangan wanita.
Seni kontemporer Sudan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, dengan munculnya gerakan seni modern yang dipengaruhi oleh pendidikan seni Barat namun tetap berakar pada tradisi lokal. Pelukis dan pematung Sudan seringkali mengeksplorasi tema-tema identitas, sejarah, spiritualitas, dan isu-isu sosial politik melalui karya mereka. "Sekolah Khartoum" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok seniman modernis Sudan yang menggabungkan kaligrafi Arab, motif Afrika, dan teknik modern.
Konflik dan ketidakstabilan politik seringkali memengaruhi perkembangan seni, namun juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman untuk mengekspresikan pengalaman dan kritik sosial mereka. Meskipun menghadapi tantangan, komunitas seni di Sudan terus berupaya untuk berkarya dan mempromosikan seni Sudan baik di tingkat nasional maupun internasional.
11.3.1. Musik

Sudan memiliki budaya musik yang kaya dan unik yang telah melalui ketidakstabilan kronis dan penindasan selama sejarah modern Sudan. Dimulai dengan penerapan interpretasi Salafi yang ketat terhadap hukum syariah pada tahun 1983, banyak penyair dan seniman terkemuka negara itu, seperti Mahjoub Sharif, dipenjara sementara yang lain, seperti Mohammed el Amin (kembali ke Sudan pada pertengahan 1990-an) dan Mohammed Wardi (kembali ke Sudan 2003), melarikan diri ke Kairo. Musik tradisional juga menderita, dengan upacara Zār tradisional diinterupsi dan drum disita.
Pada saat yang sama, militer Eropa berkontribusi pada pengembangan musik Sudan dengan memperkenalkan instrumen dan gaya baru; band militer, terutama bagpipe Skotlandia, terkenal, dan mengatur musik tradisional menjadi musik baris-berbaris militer. Mars March Shulkawi No 1, adalah contohnya, diatur dengan suara orang Shilluk. Sudan Utara mendengarkan musik yang berbeda dari bagian lain Sudan. Jenis musik yang disebut Aldlayib menggunakan alat musik yang disebut Tambur. Tambur memiliki lima senar, terbuat dari kayu dan menghasilkan musik yang diiringi oleh suara tepuk tangan manusia dan penyanyi.
Musik tradisional Sudan sangat beragam, mencerminkan keragaman etnis negara tersebut. Setiap daerah dan kelompok etnis memiliki gaya musik, ritme, dan instrumen khasnya sendiri. Instrumen tradisional yang umum digunakan termasuk berbagai jenis drum (seperti tabla dan daluka), lira (seperti kissar atau tanbūra), seruling, dan alat musik gesek. Musik Sufi, dengan nyanyian zikir dan penggunaan drum, juga memiliki peran penting dalam tradisi musik Sudan.
Musik populer Sudan, yang dikenal sebagai haqiiba, berkembang pada awal abad ke-20 dan menggabungkan melodi dan ritme tradisional dengan pengaruh musik Arab dan Barat. Penyanyi legendaris seperti Mohammed Wardi, Abdel Karim al Kabli, dan Sayed Khalifa adalah tokoh-tokoh penting dalam genre ini. Musik pop modern Sudan terus berkembang, dengan generasi baru musisi yang bereksperimen dengan berbagai gaya dan pengaruh. Meskipun menghadapi tantangan akibat ketidakstabilan politik dan pembatasan budaya pada periode tertentu, musik tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekspresi budaya di Sudan.
11.3.2. Sastra
Sastra Sudan memiliki tradisi lisan yang kaya, mencakup cerita rakyat, puisi, peribahasa, dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi lisan ini memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal berbagai kelompok etnis di Sudan.
Sastra tulis modern Sudan mulai berkembang pada abad ke-20, dipengaruhi oleh gerakan sastra Arab dan pendidikan modern. Puisi memiliki tempat yang sangat penting dalam sastra Sudan, dengan banyak penyair terkenal yang karya-karyanya seringkali mencerminkan tema-tema nasionalisme, identitas, kritik sosial, dan cinta.
Novel dan cerita pendek juga berkembang, dengan penulis seperti Tayeb Salih yang mendapatkan pengakuan internasional. Karyanya yang paling terkenal, Musim Hijrah ke Utara (Mawsim al-Hijra ila al-Shamal), dianggap sebagai salah satu novel Arab modern terpenting. Penulis Sudan lainnya telah mengeksplorasi berbagai tema, termasuk sejarah kolonial, kehidupan pedesaan dan perkotaan, konflik, dan pencarian identitas.
Namun, perkembangan sastra di Sudan seringkali menghadapi tantangan akibat sensor, pembatasan kebebasan berekspresi, dan kurangnya dukungan infrastruktur penerbitan. Meskipun demikian, para penulis Sudan terus berkarya dan memberikan kontribusi penting bagi khazanah sastra Arab dan Afrika.
11.3.3. Sinema dan Fotografi
Sinema Sudan dimulai dengan sinematografi oleh kehadiran kolonial Inggris pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, tradisi film dokumenter yang kuat didirikan, tetapi tekanan keuangan dan kendala serius yang diberlakukan oleh pemerintah Islamis menyebabkan penurunan pembuatan film sejak tahun 1990-an dan seterusnya. Sejak tahun 2010-an, beberapa inisiatif telah menunjukkan kebangkitan yang menggembirakan dalam pembuatan film dan minat publik terhadap pertunjukan film dan festival, meskipun sebagian besar terbatas di Khartoum.
Penggunaan fotografi di Sudan sudah ada sejak tahun 1880-an dan pemerintahan Anglo-Mesir. Seperti di negara lain, semakin pentingnya fotografi untuk media massa seperti surat kabar, serta bagi fotografer amatir menyebabkan dokumentasi fotografi yang lebih luas dan penggunaan foto di Sudan selama abad ke-20 dan seterusnya. Pada abad ke-21, fotografi di Sudan telah mengalami perubahan penting, terutama karena fotografi digital dan distribusi melalui media sosial dan internet.
11.4. Arsitektur
Arsitektur Sudan mencerminkan perpaduan pengaruh budaya, iklim, dan sejarah yang beragam. Gaya arsitektur tradisional sangat bervariasi antar wilayah dan kelompok etnis, seringkali menggunakan bahan-bahan lokal seperti bata lumpur, kayu, dan jerami. Di wilayah utara, arsitektur Nubia kuno meninggalkan warisan berupa kuil-kuil megah dan piramida-piramida unik di situs-situs seperti Kerma, Napata, dan Meroë. Arsitektur Islam juga memiliki pengaruh kuat, terutama terlihat pada desain masjid-masjid dengan menara dan halaman tengah, serta rumah-rumah tradisional dengan ruang-ruang yang dirancang untuk privasi dan ventilasi alami.
Di daerah pedesaan, rumah-rumah seringkali dibangun dalam bentuk melingkar atau persegi panjang dengan atap kerucut atau datar, disesuaikan dengan iklim setempat. Penggunaan bata lumpur (jalous) umum karena ketersediaannya dan sifat insulasi termalnya yang baik. Di kota-kota, arsitektur kolonial Inggris meninggalkan jejak berupa bangunan-bangunan publik dan rumah-rumah dengan beranda luas dan jendela tinggi.
Arsitektur modern di Sudan, terutama di Khartoum, menunjukkan pengaruh gaya internasional, meskipun ada upaya untuk menggabungkan elemen-elemen desain tradisional. Lanskap perkotaan utama ditandai oleh campuran bangunan-bangunan tua dan baru, dengan tantangan terkait perencanaan kota, infrastruktur, dan perumahan yang terjangkau. Konflik dan ketidakstabilan seringkali menghambat pembangunan dan pelestarian warisan arsitektur.
11.5. Olahraga
Seperti di banyak negara, sepak bola juga merupakan olahraga paling populer di Sudan. Asosiasi Sepak Bola Sudan didirikan pada tahun 1936 dan dengan demikian menjadi salah satu asosiasi sepak bola tertua yang ada di Afrika. Namun, sebelum berdirinya Asosiasi Sepak Bola, Sudan telah mulai mengalami sepak bola yang dibawa ke negara itu oleh penjajah Inggris sejak awal abad ke-20 melalui Mesir. Klub Sudan lainnya yang didirikan pada waktu itu termasuk Al-Hilal Omdurman, Al-Merrikh, yang menyebabkan populernya sepak bola di negara itu. Liga Khartoum menjadi liga nasional pertama yang dimainkan di Sudan, meletakkan dasar bagi perkembangan sepak bola Sudan di masa depan.
Sejak September 2019, telah ada liga nasional resmi untuk klub sepak bola wanita yang dimulai berdasarkan klub wanita informal sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun 2021, tim nasional sepak bola wanita Sudan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam Piala Wanita Arab, yang diadakan di Kairo, Mesir.
Tim nasional bola voli pantai Sudan berkompetisi di Piala Kontinental Bola Voli Pantai CAVB 2018-2020 di bagian wanita dan pria. Pada Juni 2022, Patricia Seif El Din El Haj, wanita Sudan pertama pegulat yang berpartisipasi dalam kejuaraan Afrika, difoto oleh fotografer Reuters Mohamed Nureldin Abdallah, saat ia bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Nigeria untuk mempersiapkan pertandingan Olimpiade Musim Panas 2024.
Selain sepak bola, olahraga lain seperti bola basket, bola voli, dan atletik juga dimainkan, meskipun popularitas dan tingkat pengembangannya lebih rendah. Sudan telah berpartisipasi dalam Olimpiade dan kompetisi olahraga regional lainnya.
11.6. Hari Libur Nasional
Sudan memiliki beberapa hari libur nasional utama yang merayakan peristiwa keagamaan dan peringatan nasional. Hari libur keagamaan Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, ditentukan berdasarkan kalender lunar Islam dan tanggalnya berubah setiap tahun dalam kalender Gregorian. Hari libur nasional lainnya meliputi:
- Hari Kemerdekaan: 1 Januari (memperingati kemerdekaan Sudan dari Inggris dan Mesir pada tahun 1956).
- Natal Koptik: 7 Januari (dirayakan oleh komunitas Kristen Koptik).
- Revolusi Desember (peringatan dimulainya protes yang menggulingkan Bashir): Tanggal dapat bervariasi, sering dikaitkan dengan peristiwa penting dalam revolusi 2018-2019.
- Paskah Koptik: Tanggal bervariasi setiap tahun (dirayakan oleh komunitas Kristen Koptik).
- Maulid Nabi (Kelahiran Nabi Muhammad SAW): Tanggal bervariasi berdasarkan kalender Islam.
- Tahun Baru Islam (Muharram): Tanggal bervariasi berdasarkan kalender Islam.
Selain hari libur resmi, berbagai festival budaya dan keagamaan lainnya juga dirayakan oleh komunitas-komunitas tertentu di seluruh negeri.
11.7. Warisan Dunia
Sudan memiliki beberapa situs yang diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, yang menyoroti kekayaan sejarah dan alam negara tersebut:
1. Gebel Barkal dan Situs-Situs Wilayah Napatan: Ditetapkan pada tahun 2003, situs ini mencakup Gebel Barkal (gunung suci) dan beberapa situs arkeologi penting lainnya dari periode Napatan Kerajaan Kush (sekitar abad ke-9 hingga ke-4 SM). Situs-situs ini, termasuk kuil, istana, dan piramida, menunjukkan perpaduan budaya Mesir dan Nubia serta signifikansi religius dan politik wilayah tersebut sebagai pusat utama peradaban Kush. Nilai utamanya terletak pada kesaksian luar biasa terhadap peradaban Kushitik dan interaksinya dengan Mesir kuno.
2. Situs Arkeologi Pulau Meroë: Ditetapkan pada tahun 2011, situs ini terdiri dari tiga komponen utama: kota kerajaan Meroë, serta situs-situs Naqa dan Musawwarat es-Sufra. Meroë adalah ibu kota Kerajaan Kush dari sekitar abad ke-3 SM hingga abad ke-4 M. Situs ini terkenal dengan sisa-sisa istana, kuil, dan terutama ratusan piramida kecil dengan gaya yang khas. Naqa dan Musawwarat es-Sufra adalah pusat keagamaan dan seremonial penting lainnya. Warisan ini menunjukkan kekuasaan, kekayaan, dan budaya unik Kerajaan Meroitik, yang mengembangkan tulisan dan seni sendiri serta memiliki jaringan perdagangan yang luas.
3. Taman Nasional Laut Sanganeb dan Taman Nasional Laut Teluk Dungonab - Pulau Mukkawar: Ditetapkan pada tahun 2016 sebagai situs warisan alam. Terletak di Laut Merah, situs ini mencakup dua kawasan lindung laut yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Sanganeb adalah satu-satunya atol di Laut Merah, sementara Teluk Dungonab dan Pulau Mukkawar memiliki ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau yang penting. Situs ini merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan, mamalia laut (termasuk duyung), penyu, dan burung laut, serta memiliki nilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati laut global.
12. Transportasi
Sistem transportasi di Sudan menghadapi banyak tantangan akibat luasnya negara, kondisi geografis yang sulit, kurangnya investasi infrastruktur, dan dampak konflik berkepanjangan. Moda transportasi utama meliputi kereta api, penerbangan, jalan raya, dan angkutan laut.
12.1. Kereta Api

Jaringan kereta api Sudan, yang sebagian besar dibangun pada masa kolonial, memiliki total panjang sekitar 5.31 K km. Jalur utama menghubungkan ibu kota Khartoum dengan kota-kota penting lainnya seperti Port Sudan (pelabuhan utama di Laut Merah), Wadi Halfa (di perbatasan Mesir), El-Obeid (di Kordofan), dan Nyala (di Darfur). Sebagian besar jaringan menggunakan rel sempit (1067 mm). Peran kereta api dalam sistem transportasi nasional penting untuk angkutan barang jarak jauh, terutama komoditas ekspor dan impor. Namun, kondisi infrastruktur kereta api umumnya buruk akibat kurangnya perawatan dan modernisasi. Banyak jalur dan lokomotif sudah tua dan tidak efisien, menyebabkan layanan yang lambat dan tidak dapat diandalkan. Upaya untuk merehabilitasi dan memodernisasi jaringan kereta api telah dilakukan, seringkali dengan bantuan investasi asing, tetapi kemajuannya terbatas. Jalur kereta api dari Khartoum ke Wau di Sudan Selatan saat ini tidak beroperasi akibat konflik. Jalur yang paling penting adalah yang menghubungkan Khartoum dengan Port Sudan, yang menangani dua pertiga dari transportasi kereta api Sudan dan telah dimodernisasi armadanya dengan bantuan Tiongkok.
12.2. Penerbangan
Sudan memiliki beberapa bandara utama, dengan Bandar Udara Internasional Khartoum (KRT) sebagai gerbang udara internasional utama. Bandara ini melayani penerbangan ke berbagai tujuan di Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Maskapai penerbangan nasional adalah Sudan Airways. Selain Khartoum, terdapat bandara domestik di kota-kota besar lainnya seperti Port Sudan, Kassala, El Fasher, dan Nyala. Konektivitas udara domestik penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang luas dan terpencil, terutama mengingat kondisi jalan raya yang seringkali buruk. Namun, industri penerbangan Sudan juga menghadapi tantangan, termasuk armada yang menua, sanksi internasional di masa lalu yang membatasi akses ke suku cadang dan teknologi baru, serta masalah keamanan dan keselamatan. Perang saudara pasca-2023 sangat mengganggu operasi penerbangan, dengan bandara Khartoum menjadi medan pertempuran dan banyak layanan penerbangan ditangguhkan atau dialihkan.
12.3. Jalan Raya
Jaringan jalan raya di Sudan masih terbatas dan kualitasnya bervariasi. Jalan beraspal utama menghubungkan Khartoum dengan kota-kota besar lainnya seperti Port Sudan, Wad Madani, El-Obeid, dan beberapa ibu kota negara bagian. Namun, sebagian besar jaringan jalan masih berupa jalan tanah atau kerikil, yang seringkali tidak dapat dilalui selama musim hujan. Kondisi jalan yang buruk dan kurangnya pemeliharaan menjadi tantangan utama. Rute utama seperti jalan raya Khartoum-Port Sudan sangat penting untuk transportasi barang dan penumpang. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan raya merupakan prioritas, tetapi kemajuannya lambat akibat keterbatasan dana dan ketidakstabilan. Transportasi darat, terutama menggunakan truk dan bus, memainkan peran penting dalam perdagangan domestik dan pergerakan orang, meskipun seringkali memakan waktu lama dan tidak nyaman.
12.4. Angkutan Laut
Port Sudan adalah pelabuhan utama dan satu-satunya pelabuhan laut komersial yang signifikan di Sudan, terletak di pantai Laut Merah. Pelabuhan ini menangani sebagian besar perdagangan maritim negara, termasuk impor barang-barang penting seperti makanan, bahan bakar, dan mesin, serta ekspor komoditas seperti produk pertanian dan ternak hidup. Port Sudan juga merupakan titik transit penting untuk minyak mentah yang diekspor dari Sudan Selatan melalui pipa. Fasilitas pendukung di pelabuhan mencakup terminal peti kemas, terminal barang curah, dan fasilitas penyimpanan. Pengembangan dan modernisasi pelabuhan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensinya. Selain Port Sudan, terdapat beberapa pelabuhan kecil lainnya di sepanjang pantai Laut Merah, tetapi peranannya dalam perdagangan internasional terbatas. Angkutan sungai di Sungai Nil juga ada, tetapi lebih banyak digunakan untuk transportasi lokal dan pariwisata daripada perdagangan skala besar.